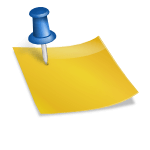Sylvia Tiwon*
“[I]t was in the Silicon Valley that the new world economy was being forged, the new historical and contemporary capitalism,” demikian Yann Boutang, pengamat ekonomi politik Perancis. Menurutnya, di tempat bernama Silicon Valley [Lembah Silikon] kapitalisme baru sedang dibentuk, sebuah sistem ekonomi dunia baru yang berbeda dengan bentuk kapitalisme industrial yang timbul pada abad ke 19 dan mencapai puncaknya pada abad ke-20.[1] Bentuk kapitalisme baru ini oleh Boutang disebut sebagai “kapitalisme kognitif” (“cognitive capitalism“), yaitu bentuk penumpukan keuntungan yang tidak sekedar bertumpu pada tenaga kerja fisik sebagai sumber daya sosial yang dihisap dan diuangkan, tetapi semakin bertumpu pada penghisapan (ekspropriasi) sumber daya sosial yang tidak berbentuk fisik atau materi, yaitu pengetahuan, daya pikir, daya kreatif serta daya emosional/rasa [affective labour] untuk diuangkan. Pengetahuan (cognition) ini kadang-kadang juga disebut sebagai “general intellect” atau “nalar umum”, yaitu pengetahuan yang tidak hanya berupa ilmu pengetahuan seperti yang terdapat dalam buku dan institusi formal, tetapi juga pengetahuan umum yang tumbuh-kembang dalam keseharian kehidupan, bisa berupa tradisi, cara atau metode melakukan sesuatu, konsep keindahan, dan sebagainya.
Secara singkat, perkembangan kapitalisme ini sering disebut era “post Fordist” atau pasca-Fordisme, di mana “Fordisme” mengacu kepada jenis kapitalisme industri/manufaktur konvensional.[2] Inti kapitalisme baru ini adalah teknologi informasi, internet, dan jaringan sosial dunia maya. Prakarsa untuk mendorong tumbuhnya “ekonomi kreatif” di Indonesia bersumber pada konsep ini, seakan membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang jauh dari eksploitasi kasar yang terjadi dalam sistem kapitalisme klasik. Ada optimisme yang menyertai bentuk baru ini; bahkan ada kesan bahwa dengan bentuk baru kapitalisme ini juga akan lahir berbagai bentuk gerakan sosial baru yang berkembang bersama dengan meluasnya jaringan-jaringan maya, pertukaran cepat informasi dan ide-ide yang tak mengenal batas-batas ruang dan negara. Jaringan-jaringan pertukaran pengetahuan ini tidak dikuasai oleh “majikan-majikan” lama, dan karenanya membuka ruang bagi suara-suara baru dan kelompok-kelompok baru untuk tampil, bertindak, dan meraih keuntungan dari upayanya. Kapitalisme baru ini juga dibayangkan lebih ramah bagi lingkungan hidup karena–berbeda dengan industri klasik–tidak tergantung pada sumber energi yang terbatas dan merusak alam (terutama BBM). Oleh para pengamat ekonomi politik ini, kapitalisme baru ini dianggap dalam waktu tidak terlalu lama akan menggeser sistem ekonomi lama dan mengubah relasi perburuhan secara drastis. Namun perlu ditanya, bagaimana kenyataannya?
Sehari-hari, saya jalan kaki dari kampus ke rumah di Berkeley, kota universitas di pinggiran pusat pengembangan industri teknologi tinggi (hi-tech) yang sering disebut “Silicon Valley,” di bagian utara California, markasnya korporasi-korporasi besar Abad ke-21 seperti Apple, Google, facebook, twitter, Yahoo, Pixar dan masih banyak lagi. Saking besarnya peran wilayah ini secara global, kepala-kepala negara yang mengunjungi A.S. tidak lagi cukup mendatangi Washington D.C., ibukota negara dan bertemu dengan presiden. Kalau belum menginjakkan kaki di San Francisco dan sekitarnya, bertemu dengan pemuka-pemuka dunia industri teknologi tinggi, kunjungan kenegaraan seakan belum lengkap. Termasuk juga Jokowi dan berbagai anggota kabinetnya.
Pesatnya perkembangan dalam bidang hi-tech menimbulkan kesan–terutama di negara-negara bagian Utara–bahwa paradigma industri telah mengalami perubahan mendasar, dan karenanya, di era digital ini, hubungan industrial pun sudah berubah. Rasanya tiap hari ada saja perusahaan “start-up” baru — usaha kecil, yang nampak menjanjikan karena mempunyai potensi pertumbuhan tinggi , dan menarik perhatian dari investor (“venture capitalist“). Banyak di antara start-up ini bergerak di bidang teknologi informasi/kreatif dan tidak mempekerjakan orang secara langsung. Contoh yang sudah sangat dikenal adalah Uber.com, perusahaan berbasis aplikasi internet dalam bidang transportasi yang menekankan bahwa supir-supir tidak seperti supir taksi biasa, melainkan “orang seperti Anda…ibu dan ayah. Pelajar dan guru…tetangga.”
Relasi perburuhan juga berbeda karena mereka tidak terikat pada mesin milik majikan melainkan “menyetir mobilnya sendiri–dengan jadwal waktunya sendiri…” Dan ini semua dilakukan “demi kebaikan bersama” [for the good of all].[3] Model yang ditawarkan seakan bebas dari kerangka pabrik lama, memindahkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kerja dalam tangan pelaku sendiri. Ingin uang banyak? carilah penumpang sebanyak-banyaknya — tidak ada yang menghalangi. Ingin istirahat dulu? silakan, tidak ada “boss” yang memaksa memenuhi target.
Tetapi, dalam perjalanan pulang dari kampus, yang lebih sering saya lihat di trotoar, di emperan toko, di kolong-kolong jembatan adalah para gelandangan, atau dalam bahasa sopan, “homeless” alias “tunawisma.” Di udara yang sering dingin dan lembab, mereka membungkus tubuh dengan lapisan-lapisan selimut kumal, sambil mendorong kereta supermarket berisi sisa barang yang masih mereka miliki. Ada yang meminta uang, ada yang mengais-ngais tong sampah mencari kaleng dan botol bekas untuk dijual ke perusahaan daur ulang, ada juga yang merogoh tong sampah mencari sisa makanan orang lain.
Jumlah orang-orang terbuang ini tidak sedikit: untuk kota San Francisco yang luasnya hanya 121,7 kilometer persegi, dan penduduknya cuma 868.816 jiwa, tercatat 6.686 orang tunawisma (angka tahun 2015).[4] Kampung-kampung tenda menjamur di kolong-kolong jembatan fly-over. Di lampu merah atau halte bis, ada saja yang meminta-minta. Tentu tidak dibiarkan oleh pemerintah kota dan polisi: aksi penggusuran kota tenda menjadi acara harian. Inikah wajah kapitalisme baru?
Sementara itu, di wilayah-wilayah industri klasik seperti negara bagian Michigan, khususnya kota Detroit, angka kemiskinan mencapai lebih dari 40% penduduk pada tahun 2012. Tahun 2014 angka kemiskinan hanya mengalami penurunan sedikit menjadi 39,3 %. [5] Ironinya ialah bahwa Detroit terletak di pusat industri manufaktur AS, dan merupakan jantung industri mobil pada Abad ke-20. Perubahan terjadi secara bertahap, dengan dipindahkannya berbagai sektor manufaktur ke luar negara bagian Michigan, bahkan ke luar negeri.
Menurut laporan Pusat Perburuhan Universitas California tahun 2016, sejak tahun 1989 semakin banyak buruh manufaktur merupakan pekerja tidak tetap, sementara tingkat upah mengalami kemerosotan sehingga tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini tentu menguntungkan bagi korporasi tetapi berdampak negatif bagi negara yang harus menyediakan jaringan penyelamat sosial (social safety net). Menurut laporan ini, antara tahun 2009 dan 2013, pemerintah federal dan negara bagian mengeluarkan jumlah sebesar $10,2 milyar setiap tahun untuk menutupi kebutuhan buruh manufaktur dan keluarga mereka yang tidak terjangkau oleh upahnya yang rendah. Ironinya, negara bagian California (tempatnya Silicon Valley), merupakan salah satu dari sepuluh negara bagian dengan jumlah terbesar buruh yang terpaksa menggunakan jaringan sosial untuk menutupi kebutuhan hidupnya.[6]
Dalam kondisi yang semakin buruk ini, persentase buruh yang menjadi anggota serikat buruh mengalami kemerosotan tajam, dari 33% pada abad ke 20, menjadi hanya sekitar 11% sekarang ini. Walaupun eknomi baru menghasilkan kekayaan baru, kebanyakan jenis pekerjaan yang tercipta oleh kapitalisme baru terbagi dalam dua kategori: upah tinggi untuk pengetahuan dan keterampilan tertinggi, dan upah rendah untuk keterampilan rendah. [7] Dari aspek keadilan gender kebanyakan pekerjaan peringkat atas dipegang oleh laki-laki. Inikah wajah kapitalisme baru?
Membaca tulisan-tulisan buruh dalam koleksi ini, kita menangkap bahwa kalau di A.S. negara harus menutup kekurangan upah rendah, di Indonesia yang berfungsi sebagai jaringan penyelamat sosial ialah keluarga, biasanya keluarga di pedesaan, atau sektor informal (makanan, ojek, dsb), di mana terjadi persaingan yang cukup ketat. Buruh industri di Indonesia juga selalu hidup dengan ancaman penutupan pabrik karena pemodal lari ke negara atau wilayah yang menjanjikan upah yang lebih rendah dan/atau keringanan pajak dan berbagai fasilitas yang lebih baik. Sementara, angan-angan bahwa kapitalisme baru lebih ramah lingkungan juga ternyata jauh dari kenyataan.
Berbagai laporan mengungkap bahwa kapitalisme pengetahuan tetap menyangga pada eksploitasi sumberdaya yang menyisakan kerusakan alam untuk menghasilkan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi.[8]
Di Indonesia, berbagai laporan dari organisasi-organisasi seperti Sawit Watch menunjukkan bahwa praktik-praktik perburuhan di perkebunan kelapa sawit –sumber devisa terbesar sekarang ini–belum beranjak jauh dari praktik-praktik perburuhan zaman kolonial. Jelaslah bahwa walaupun kapitalisme sedang berubah bentuk, dasarnya yang eksploitatif tidak menunjukkan perubahan. “Ekonomi dunia baru” melanggengkan struktur ketidakadilan ekonomi dan sosial, malah meruncingkan perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, yang dikenal dengan istilah 1% dan 99% untuk menggambarkan kondisi global di mana 1% penduduk terkaya memiliki sekitar 50% dari kekayaan dunia, atau kekayaan 80 orang terkaya di bumi sama dengan milik 3,5 milyar penduduk termiskin di dunia.[9]
Pekerjaan dalam bidang teknologi komputer pun ternyata membawa cara-cara eksploitasi baru terhadap pekerja-pekerja digital. Lilly Irani, seorang peneliti kondisi perburuhan digital, mengungkap ketidakadilan struktural dalam metode yang digunakan perusahaan Amazon dalam Web Services–nya yang menawarkan jasa teknologi baru intelijensi buatan (artificial intelligence). Ternyata yang ditawarkan sebenarnya adalah jasa data processing yang dilakukan oleh pekerja-pekerja lepas dengan bayaran yang sangat rendah. Karena tidak kelihatan, pekerja-pekerja digital ini tidak mendapat perlindungan, misalnya kalau ada pengguna jasa yang menolak untuk membayar karena berbagai alasan.[10]
Dalam kondisi seperti ini, suara dan aksi serikat dan organisasi perburuhan semakin dibutuhkan. Koleksi tulisan ini menunjukkan bahwa serikat dan organisasi buruh tidak sekedar mengikuti pola perserikatan konvensional. Jenis aksi, karakteristik pengorganisasian dan pilihan tuntutan pun sangat inovatif dan bervariasi, termasuk aspek pengorganisasian berdasarkan wilayah, dan juga ide-ide untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan reproduktif buruh seperti tempat penitipan anak. Kritik yang sering dilontarkan pada serikat buruh ialah bahwa konsepsi dasar, ideologi dan metode-metodenya sudah usang dan tidak dibutuhkan lagi dalam era kapitalisme baru. Sebaliknya, setidaknya, kalau saya melihat kecenderungan-kecenderungan yang sedang bergulir di sekitar saya, perserikatan, kesetiakawanan dan pergerakan justru perlu diperkuat. Tentu ini tidak berarti bahwa metode yang ada bisa dituruti tanpa refleksi: perburuhan juga perlu meningkatkan segi kognitif. ***
* Tulisan ini merupakan Epilog dari kumpulan tulisan “Buruh Menuliskan Perlawanannya Jilid II” yang diterbitkan oleh LIPS dan TAB.
____________________
[1] Yann Moulier Boutang, Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity Press. 2011. Pertama terbit dalam bahasa Perancis tahun 2008, hal. 6.
[2] Seperti yang umum terdapat di Indonesia untuk menghasilkan produk-produk dari mobil hingga sepatu, makanan dan mainan anak-anak.
[3] Dikutip dari situs uber-com bahasa Inggris.
[4] San Francisco Point-in-time Count & Survey, 2015. https://sfgov.org/lhcb/sites/sfgov.org.lhcb.
[5] Sumber: detroitnews.com. September 17, 2015.
[6] Producing Poverty: The Public Cost of Low-Wage Production Jobs in Manufacturing oleh Ken Jacobs, Zohar Perla, Ian Perry, dan Dave Graham-Squire. Research Brief, U.C Berkeley Center for Labor Research and Education, May 2016.
[7] Work, Money and Power: Unions in the 21st Century. laborcenter.berkeley.edu. 2013.
[8] Lihat, misalnya, laporan BBC mengenai eksploitasi mineral-mineral untuk produksi industri teknologi, “The Worst Place on Earth” (Tempat terburuk di dunia) http://www.bbc.com/future/story/20150402-the-worst-place-on-earth
[9] “Richest 1% will own more than all the rest by 2016”, laporan Oxfam, 19 January 2015. http://www.oxfam.org.uk/blogs/2015/01/richest-1-per-cent-will-own-more-than-all-the-rest-by-2016
[10] Tulisan lengkap, berjudul “Difference and Dependence among Digital Workers: The Case of Amazon Mechanical Turk” South Atlantic Quarterly , 2015, bisa diperoleh di http://saq.dukejournals.org/content/114/1/225.full.pdf. Irani juga berusaha membangun jaringan alternatif antara pekerja digital tersebut sebagai upaya melawan ketidakadilan tersebut.
Jika Anda menikmati membaca cerita ini, maka kami akan senang jika Anda membagikannya!