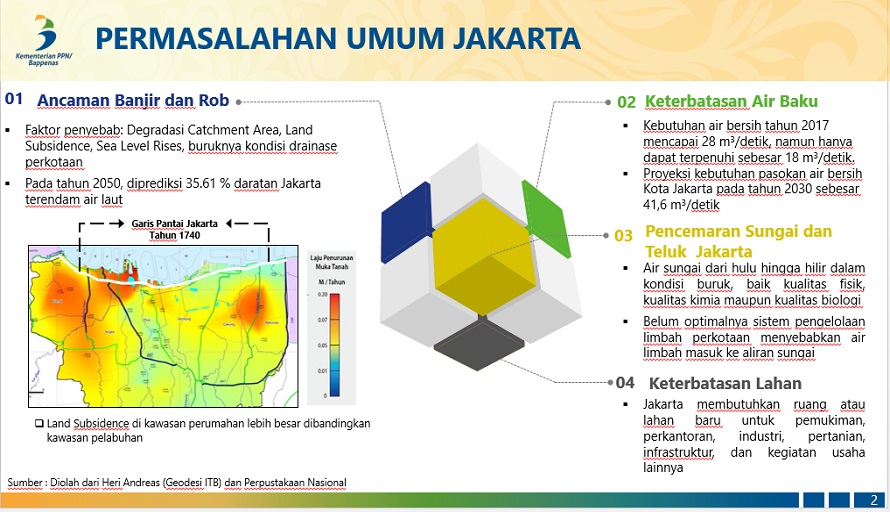Sejak 2017, saya dan beberapa kawan ‘berkeliaran’ di beberapa wilayah industri lama (seperti Jabodetabek, Serang, Sukabumi dan Karawang) dan wilayah industri baru (beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat). Tujuannya, mengamati bagaimana pola pabrik-pabrik di wilayah industri lama merelokasi dan meluaskan basis produksinya ke wilayah industri baru.[1]
Pertanyaan mendasar dari proses tersebut adalah faktor apa saja yang memungkinkan perusahaan merelokasikan sebagian atau seluruh basis produksinya ke wilayah baru? Faktor apa saja yang membuat perusahaan dapat diterima dan beroperasi dengan leluasa di wilayah baru? Konteks perusahaan yang dimaksud di sini adalah perusahaan manufaktur yang dikategorikan oleh pemerintah sebagai industri padat karya. Sebagian besar perusahaan tersebut memiliki jejaring perusahaan di berbagai negara. Produknya berorientasi ekspor, seperti garmen, alas kaki, sepatu, dan elektronik.
Di wilayah industri lama, kami menemukan faktor utama yang mendorong perusahaan memindahkan sebagian atau seluruh basis produksinya ke wilayah baru. Yakni, biaya produksi di wilayah industri lama meningkat secara signifikan setelah habis-habisan memeras untung dari keringat para buruh dengan mudah dan murah, serta mengeruk untung dari rezim privatisasi sumber-sumber penghidupan rakyat. Pemerasan dan pengerukan tersebut memiliki ambang batas ketika kapital tidak lagi dapat mengakumulasikan keuntungan yang lebih besar lagi.
Selain biaya produksi yang meningkat akibat krisis sosial-ekologis dan difasilitasi oleh negara, ambang batas lainnya adalah perlawanan dari gerakan buruh yang massif. Dalam konteks itulah kapital mencari cara untuk mengatasi krisisnya. Yakni, dengan cara kabur dan mencari ruang baru agar tetap dapat mempertahankan keuntungan. Di tempat baru, kapital melakukan hal yang sama: mengendalikan buruh untuk dieksploitasi dan mengontrol sumber-sumber penghidupan untuk dikuras, bahkan dengan skala yang lebih intensif.
Di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung misalnya, dari total 104 perusahaan, kini hanya tersisa 27 perusahaan. Sejak 2007, beberapa perusahaan di KBN Cakung telah melakukan ekspansi ke wilayah Sukabumi dan Bogor. Kemudian puncak relokasi terjadi pada periode 2014-2016, di mana hampir 90 persen perusahaan yang beroperasi di KBN Cakung memindahkan seluruh produksinya ke wilayah baru dan menutup produksinya di KBN Cakung. Relokasi tersebut terjadi setelah gelombang gerakan buruh mempersoalkan kenaikan upah minimum (Dokumentasi LIPS, 2010), membuka kebobrokan jenis-jenis hubungan kerja kontrak, jam kerja panjang dan mendesak kenaikan upah minimum sebesar 44 persen pada 2013.
Di antara wilayah yang menjadi sasaran relokasi dan ekspansi adalah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di wilayah industri baru kami bertemu dengan buruh-buruh muda yang baru memasuki pasar tenaga kerja. Mereka memiliki pandangan dunia sesuai dengan zamannya. Barangkali karakter buruh muda ini penting diperhatikan dalam konteks pengorganisasian buruh.
Di wilayah industri baru, rata-rata jenis industri yang datang didominasi oleh industri padat karya seperti pakaian jadi dan alas kaki dengan merek ternama, seperti Adidas, Nike, H&M, dan lain sebagainya. Pabrik-pabrik yang melakukan relokasi dan ekspansi adalah perusahaan yang memiliki jaringan produksi di beberapa negara. Dengan memanfaatkan perbedaan upah tiap negara, memungkinkan perusahaan-perusahaan pemasok ini melempar produksinya ke negara atau wilayah-wilayah yang berupah murah. Pabrik-pabrik tersebut pun harus bersaing dengan ratusan pabrik pemasok lainnya agar tetap mendapatkan order dari pemilik merek. Persaingan antarpabrik ini juga turut mendorong perusahaan transnasional untuk mencari wilayah-wilayah baru yang berupah murah.
Dengan demikian, pemburuan upah murah bukan sekadar mendapat untung dari upah yang murah. Tapi strategi untuk mempertahankan dan melipatkangandakan keuntungan. Dengan kata lain, perluasan dan relokasi produksi merupakan strategi untuk meningkatkan keuntungan, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas, kerja intensif, dan jam kerja panjang. Peningkatan produktivitas mensyaratkan biaya tenaga kerja per unit rendah. Sebagaimana yang dikatakan Suwandi (2022), peningkatan dalam produktivitas merupakan bagian integral dari perampasan rantai nilai kerja dengan tujuan untuk menjaga biaya tenaga kerja per unit tetap rendah dan berpengaruh pada daya saing perusahaan.
Agar tetap mempertahankan biaya kerja per unit rendah, serangkaian kontrol dipaksakan oleh perusahaan multinasional. Suwandi (2022) membagi tiga bentuk kontrol: Pertama, kontrol atas pengetahuan teknologi sebagai cara perusahaan-perusahaan multinasional untuk dapat menuntut para pemasok menggunakan standardisasi produksi. Kedua, memaksa pemasok agar mengirim produk yang sesuai target dan waktu yang ditentukan. Ketiga, penerapan serangkaian kode etik untuk mengakomodasi tuntutan buruh sekaligus pencitraan sebagai “praktik bisnis yang adil” seperti sertifikasi internasional atau klaim praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia.
Namun, semua hal di atas, pertimbangan terpenting yang menentukan lokasi relokasi dan ekspansi pabrik adalah sejauh mana resistensi gerakan buruh di wilayah baru. Oleh karenanya, pengendalian buruh dan serikat buruh menjadi pekerjaan harian dari pemilik modal dan lembaga-lembaga negara.
Memperluas Aliansi dan Memperkuat Solidaritas
Temuan-temuan investigasi di PT Sai Apparel Industries Grobogan mencerminkan bagaimana kekuatan modal melalui serangkaian kontrolnya menaklukkan buruh dan serikat buruh di dalam pabrik. Bentuk-bentuk kontrol perusahaan terhadap serikat buruh di satu sisi kerap menggunakan narasi yang seolah memberikan ruang dialog antara pengusaha dan serikat, namun di sisi lain serikat tak diberikan ruang untuk memperkuat anggotanya. Forum-forum semacam LKS bipartit dibuat untuk menjauhkan serikat buruh dari kerja-kerja pembelaan dan hanya menempuh mekanisme ‘resmi’ yang diakui negara dan pemilik perusahaan. Mekanisme-mekanisme tersebut diarahkan dalam bingkai mendukung produktivitas perusahaan.
Manajemen mengendalikan buruh melalui perjanjian kerja, perintah dan penugasan kerja yang bersifat harian maupun nonharian serta melalui peraturan-peraturan di tempat kerja. Faktor-faktor tersebut menandai kekuasaan manajemen di dalam pabrik. Manajemen pun mengendalikan serikat buruh dengan membatasi peran serikat buruh untuk merekrut anggota, menjauhkan para pengurus dengan anggota dan menghambat serikat buruh memperluas jaringan.
Dalam konteks pengendalian buruh dan serikat buruh itu pula, lembaga negara tak sungkan untuk memperlihatkan keberpihakannya kepada pemilik modal. Lembaga negara mengendalikan buruh dan serikat buruh dengan membiarkan pelanggaran ketenagakerjaan di tempat kerja, memosisikan diri seolah-olah menjadi ‘wasit’ sembari mencampuri urusan internal serikat buruh, dan menasehati buruh agar tidak mengganggu investasi.
Sejak Orde Baru hingga Reformasi, kebijakan perburuhan di Indonesia selalu tidak menguntungkan buruh, sebaliknya, malah melegitimasi upah murah dan pasar kerja fleksibel. Dengan kalimat lain, kebijakan perburuhan dari waktu ke waktu tersebut tak mengubah wajah asli perbudakan di bawah atap pabrik. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh serikat buruh jika menyadari bahwa undang-undang perburuhan dan sistem ekonomi yang neoliberal tidak berpihak ke buruh?
Untuk memantik diskusi atas pertanyaan di atas, perlu kiranya kita merefleksikan beberapa peristiwa protes gerakan buruh yang berhasil maupun yang gagal. Bagaimana tuntutan dirumuskan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana protes dilakukan?
Sebelum itu, saya ingin menegaskan gerakan buruh tidak sama dengan gerakan serikat buruh pabrik. Gerakan serikat buruh adalah salah satu bagian dari gerakan buruh. Dari pengertian tersebut kita dapat memahami perlawanan buruh di era rezim jagal Soeharto bukan gerakan serikat buruh dan tidak hanya diwakili oleh buruh pabrik. Tidak sedikit pula cerita, ketika perlawanan buruh mengemuka aktor-aktor yang mengatasnamakan wakil buruh membuat kesepakatan dengan pengusaha atau pemerintah, yang merugikan buruh.
Di era Soeharto, satu-satunya serikat buruh yang diakui negara selalu mendukung dan membiarkan penindasan terhadap buruh. Tapi perlawanan buruh baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi terus bermunculan hingga rezim bengis tersebut runtuh. Perlawanan tersebut dilakukan oleh aktor-aktor yang mengumandangkan persoalan perburuhan baik kelas menengah, pekerja seni, jurnalis hingga buruh pabrik (Ford, 2009). Dan, isu perburuhan merentang dari mempersoalkan militerisme, korupsi, upah lembur yang tidak dibayar hingga kekerasan berbasis gender. Sebagaimana diketahui, salah satu warisan Soeharto dan didukung oleh beberapa serikat buruh internasional adalah nasihat: tugas serikat buruh adalah menegakkan norma-norma ketenagakerjaan di tempat kerja.
Dari pemahaman di atas, kita dapat pula mengartikan bahwa buruh terorganisasi atau buruh berserikat bukan berarti organisasi yang tercatat di lembaga negara. Namun, buruh yang berkumpul, saling memperkuat solidaritas, membagi tugas dan peran, serta menyusun agenda perlawanan. Karena ada pula serikat buruh yang tercatat di lembaga negara dan memiliki anggota namun kegiatannya hanya mendukung kebijakan perusahaan atau negara, bahkan sekadar papan nama.
Selama sistem penghisapan beroperasi, perlawanan buruh selalu hadir. Perlawanan tersebut ada yang menang dan banyak pula yang kalah. Ketika perlawanan buruh kalah berarti lawan gerakan buruh lebih kuat. Gerakan buruh pun akan terus berupaya melakukan perlawanan.
Sejak rezim Soeharto takluk oleh gerakan rakyat, perlawanan buruh mengemuka. Bentuk-bentuk perlawanan diekspresikan dengan demonstrasi, pawai hingga pemogokan. Tidak sedikit perlawanan pun dilakukan dengan menguasai jalan umum–saluran yang sedianya diabdikan untuk memperlancar sirkulasi kapital dan dinarasikan sebagai fasilitas umum. Tidak sedikit pula ekspresi perlawanan buruh diperlihatkan dengan mendatangi atau menduduki kantor-kantor pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat—kantor yang mengaku memikirkan kepentingan buruh tapi hak buruh tidak pernah terlindungi.
Di jalanan itulah gerakan buruh memperlihatkan kondisi umum di dalam pabrik ke khalayak umum dari persoalan lembur hingga jaminan sosial. Dengan kata lain, barang-barang yang diperjualbelikan di pasar, dikemas dengan elegan dan diiklankan oleh artis tersohor, diproduksi oleh buruh yang dibayar murah dengan kondisi kerja yang buruk. Di depan kantor pemerintahan itu pula, para buruh memperlihatkan bahwa kinerja lembaga pemerintahan yang mendaku bekerja untuk rakyat tidak memberikan manfaat bagi buruh.
Terdapat beberapa tonggak penting perlawanan buruh seperti Aliansi Tolak PHK, yang menduduki Kantor Depnakertrans, pada 2004; pawai buruh dalam Aliansi Buruh Menggugat pada 2006-2008; pemogokan Kawasan Berikat Nusantara, pada 2010; blokade jalan tol Bitung Banten dan Jakarta-Cikampek pada 2011 dan 2012; grebek pabrik pada 2012; mogok nasional pada 2013; longmarch Jakarta-Bandung pada 2015; perlawanan terhadap UU Cipta Kerja 2020; dan ratusan perlawanan lainnya; tidak terlepas dari peran-peran ‘kecil’ yang menopangnya, yaitu kelompok-kelompok diskusi yang digagas secara mandiri oleh buruh di kontrakan. Diskusi yang dihadiri segelintir orang dengan sukarela, di ruangan pengap, tanpa ganti uang transportasi, tidak ada kegiatan foto bersama dan narasumber terkenal.
Dalam diskusi-diskusi kecil itulah, kondisi kerja buruk di pabrik dan di kawasan industri menjadi masalah bersama. Diskusi-diskusi di kontrakan buruh, di kawasan industri dan di sekretariat serikat semakin massif ketika menjelang akhir tahun, ketika menuntut kenaikan upah. Diskusi-diskusi kecil lintas pabrik dan kawasan, pada akhirnya, mendorong pembentukan aliansi antarserikat buruh dan menumbuhkan solidaritas antarburuh pabrik dan bahkan buruh antarkawasan.
Situasi buruk yang sama di dalam pabrik berhasil didudukkan sebagai masalah bersama. Keluhan-keluhan harian buruh dirumuskan sebagai tuntutan bersama dan disuarakan melalui beragam aksi massa di luar pabrik. Kaum buruh menyadari bahwa persoalan perburuhan tidak dapat dititipkan ke politisi, apalagi sekadar disuarakan oleh influencer. Satu-satunya yang menjelaskan gerakan buruh mengekspresikan kekuatannya karena keberhasilannya membangun aliansi perlawanan. Kekuatan buruh berhasil digalang di luar pabrik hingga menjadi kemarahan. Aksi jalanan pun menjadi satu-satunya cara karena di dalam pabrik buruh tak punya kekuatan. Mereka melakukan protes dengan memblokade jalan tol, grebek pabrik, sweeping, longmarch hingga mogok nasional.
Kita juga menyaksikan melalui aksi massa jalanan gerakan buruh tak hanya merespons isu-isu normatif perburuhan, tapi juga isu-isu yang lebih luas. Seperti jaminan sosial, kenaikan BBM, dan isu-isu ketersediaan air.
Dengan serangkaian peraturan perundangan yang mengatur perburuhan yang diproduksi negara membuat buruh maupun serikat buruh sulit untuk melakukan perlawanan di pabrik. Di satu sisi, pemilik modal menggunakan alasan-alasan ekonomi untuk menyingkirkan perlawanan buruh. Di sisi lain, advokat buruh begitu telaten menyusun argumen hukum dan gagal memenangkan hak buruh di pengadilan. Namun, gerakan buruh akan selalu menemukan celah untuk menyusun perlawanan.
Kasus-kasus yang mengarah pada union busting misalnya, kerap tidak bisa dibuktikan oleh serikat buruh di hadapan pengadilan karena pengusaha menggunakan alasan-alasan yang bersifat ekonomi: putus kontrak, efisensi dan penilaian kinerja buruh. Hal lain soal ketatnya jam kerja dalam rangka produktivitas perusahaan membuat pengorganisasian serikat buruh di dalam pabrik memiliki keterbatasan. Pemberlakuan lembur wajib dengan alasan target ekspor kerap memproduksi umpatan, pelecehan dan perendahan buruh sebagai manusia di tengah tekanan ekonomi dan persaingan individual dalam pasar kerja. Situasi yang demikian kerap dinormalisasi oleh buruh bahkan serikat buruh yang berhasil ditundukkan pemilik perusahaan.
Meski demikian, buruh hidup di ruang yang sama. Berada di lingkungan dengan polutan industri yang sama, berada di ruang yang pengeluaran ekonomi tinggi, serta di bawah rezim kerja yang sama. Kesamaan kondisi inilah yang dapat mempertemukan buruh melalui solidaritas. Meskipun kita tidak menafikkan antarserikat buruh maupun antarburuh kadang muncul ketidakcocokan yang menimbulkan perpecahan dan kesulitan untuk menjalin perlawanan bersama. Perpecahan tersebut merupakan hasil dari rezim kerja ekploitatif atau intervensi dari aparatus negara. Perlawanan buruh akan terus muncul mencari bentuk-bentuknya yang lebih efektif. Sebagaimana ditulis Juliawan (2011) politik jalanan memiliki signifikansi tersendiri bagi buruh, baik secara material maupun immaterial. Dengan demikian aksi massa jalanan dengan skala yang lebih besar dan terorganisasi memungkinkan buruh mendesakkan kepentingan mereka di hadapan negara dan kapital ketimbang dengan dialog sosial yang tak pernah memperhitungkan kekuatan massa.[]
[1] Tulisan ini merupakan bagian dari publikasi hasil investigasi. Penaklukan dan Perlawanan!: Laporan Investigatif tentang Kontrak Kerja, Kekerasan Berbasis Gender, Pencurian Upah dan Kebebasan Berserikat di PT Sai Apparel Grobogan. Yogyakarta. Tanah Air Beta. 2023.