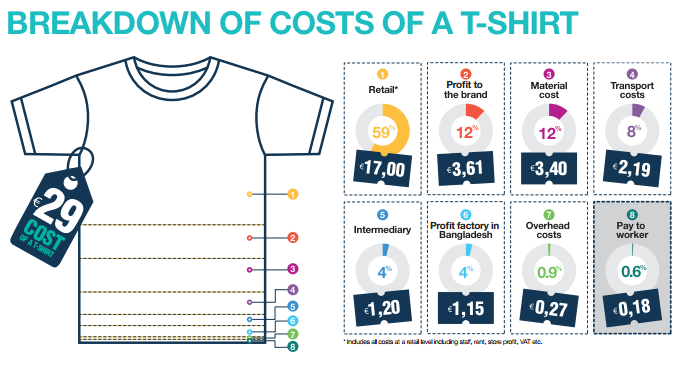Muda, fashionable, humble, funny, dan lihai dalam mengolah dan menyeduh kopi. Mungkin itu kesan pertama yang muncul kala kita melihat barista di suatu kedai kopi. Bahkan tak jarang apa yang melekat pada tubuh mereka jauh lebih mahal dari apa yang kita kenakan—jam tangan seharga Rp500 ribu hingga jutaan, pakaian branded dan berkelas, handphone merek iphone, sepatu harga jutaan seperti Nike, Adidas, hingga Docmart; tak sedikit juga dari mereka mengendarai Vespa matic seharga Rp30-Rp50 juta, belum lagi ada yang membuat tato di tubuhnya yang harga per jamnya saja dapat mencapai jutaan rupiah. Secara logika, melihat lifestyle mereka yang begitu ciamik pastilah upah mereka sebagai barista sungguh-lah lumayan. Tapi, apakah benar kenyataannya seperti itu?
Sekelebat Realitas yang Tertutur
Matahari tepat di atas kepala. Jakarta bak kuali raksasa. Klakson kendaraan dan makian merambat ke ruas-ruas jalan. Tiba-tiba wangi parfum lokal—yang katanya dipakai sebagian menteri dan selebritas tanah air—menendang hidungku. “Ayok, friend,” Naufal menginstruksikanku untuk segera naik ke atas motor matic andalannya. Hari itu aku menemani dia bekerja sembari numpang ngopi dan membuat konten untuk client. Ya, Naufal adalah seorang buruh kedai kopi yang mendedikasikan 6 tahun hidupnya sebagai seorang barista.
Naufal bekerja di kedai kopi rumahan bernama Khayang. Meski Khayang hanya kedai kopi rumahan yang tidak berbentuk PT, namun Khayang sudah memiliki 6 outlet yang tersebar di Jakarta, Bali, dan Ambon. Ini sih itungannya PT berkedok UMKM ya Malihh.
Di kedai kopi Khayang ini, Naufal bekerja 8 jam sehari dengan 1 hari libur di ujung pekan. Namun, pekerjaan Naufal di kedai kopi ini bukan hanya soal menyeduh kopi dan menemani curhat pelanggan; tapi juga membersihkan tempat, ‘menumis’ biji kopi, menggiling kopi, bahkan mengepak hampers yang jadi usaha sampingan si pemilik kedai kopi—di luar jobdesk ya, namun, semua itu terhitung loyalitas dan dedikasi. Tuman!
Aku pun sampai di kedai kopi Khayang dan langsung duduk di bangku pelanggan, menyalakan laptop, dan mengaktifkan layanan Wi-Fi gratisan. Naufal segera menuju ruang kerjanya—bar ukuran 2×2,5 meter yang dipenuhi mesin-mesin kopi yang canggih, beraneka biji kopi, sirup, dan perkakas barista lainnya—lalu segera melakukan kalibrasi ala-ala barista kedai kopi pada umumnya.
Hari itu lengang, hanya beberapa pelanggan. Setelah menyiapkan pesanan pelanggan dan membuat kopi susu gratisan untuk kami berdua, Naufal menghampiri mejaku yang terletak di sebelah meja barnya. Datang. Menaruh kopi susu gratisan di atas meja. Duduk. Menyambungkan iPhonenya ke speaker wireless. Menyetel lagu. Lalu melontarkan pernyataan yang tidak bisa langsung aku sambut, “Kayaknya baru kemarin gue nerima gaji pertama, tiba-tiba besok udah enam tahun aja gue kerja di sini. Malah sekarang gaji cuman numpang lewat doang. Bingung gue!” celetuknya.
Pada perbincangan yang sebentar namun dalam itu, Naufal sempat mencurahkan dan mengeluhkan beberapa hal seperti, harga bahan pokok yang makin mencekik, mahalnya gaya hidup di Jakarta sebagai modal sosial agar dapat relasi, gaji yang kecil, tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja ataupun BPJS ketenagakerjaan, bahkan ia tak pernah mendapat THR sebesar upah sebulan penuh (gaji ke-13) selama 6 tahun bekerja.
Upah Naufal hanya Rp4 juta per bulan. Itu pun baru didapat ketika masa kerjanya masuk tahun keenam. Sebagai seorang anak tertua dari pasangan pensiunan, yang dilimpahi banyak adik yang masih dalam jenjang pendidikan, upah segitu jelas hanya numpang lewat. Ya, Naufal adalah cerminan generasi sandwich, yang mesti menanggung kebutuhan dirinya, membantu keuangan orang tuanya, dan adik-adiknya. Bahkan, tak jarang Naufal mesti berurusan dengan pinjaman online dan kredit barang online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan gaya hidupnya.
Naufal sempat mencoba peruntungan di lini UMKM, dengan membuat usaha kopi gerobakan bersama kawannya. Bukannya untung malah buntung. Kawannya lari. Sementara Naufal harus menanggung kesialan sendiri sampai-sampai ketiban utang puluhan juta rupiah dari pinjaman online yang dulu ia pakai sebagai modal usaha. Dalam industri perkopian, UMKM yang benar-benar mikro jelas pasti dilahap para raksasa kedai kopi berkedok UMKM. Menurutku, harusnya pemerintah mampu melihat ini sih, biar gak fafifu mulu soal UMKM.
“Kopi dong, Fal!”—Herman datang. Herman juga seorang barista. Ia juga bekerja di kopi Khayang sebagai pekerja paruh waktu. Hari ini ia libur di kopi Khayang, namun baru saja pulang kerja dari tempat kerjanya yang satunya, kopi Puan. Herman rela mengambil dua job untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, akhir-akhir ini Herman menggunakan waktu liburnya untuk bekerja sambilan menjadi guru beladiri Wing Chun di salah satu tempat di Jakarta Selatan.
“Beli dong lo! Duit lo kan banyak!” jawab Naufal.
“Mana ada banyak, cuma permisi doang gaji gue. Kebutuhan gue kan bejibun,” timpal Herman.
Herman adalah seorang perantau. Orang tuanya tinggal di Banten, sementara ia harus kerja di Jakarta. Jarak antara tempat kerja dengan rumah Herman yang jauh membuat Herman harus menyewa kamar kost di Jakarta.
Sudah 6 tahun Herman berprofesi sebagai barista/pekerja di coffeeshop rumahan. Herman mesti berakhir jadi pekerja di coffeeshop rumahan sebab kekalahannya bersaing jadi orang kantoran. Padahal ia lulusan terbaik dari perguruan tinggi negeri terbaik se-Malang Raya.
Herman pada awalnya adalah pekerja penuh waktu di kopi Khayang. Upahnya sama seperti Naufal. Semenjak ia memilih untuk mengambil double job, Herman akhirnya bekerja paruh waktu di kopi Khayang, dengan upah Rp2 juta per bulan, dan jam kerja 5-6 jam per hari, dengan waktu libur sehari di ujung pekan.
Di tempat kerja satunya, kopi Puan, Herman berposisi sebagai headbar, upahnya hanya Rp4 juta per bulan. Jam kerjanya pun 54 jam per pekan. Total upah Herman kerja di dua tempat sebesar Rp6 juta. Upahnya ia gunakan untuk biaya sewa indekos per bulan dan tagihan listrik sebesar Rp2 juta, biaya makan dan bensin sebulan kisaran Rp3 juta, sisanya dikirim untuk keluarga di rumah. Maka dari itu, Herman nyambi sebagai guru bela diri Wing Chun. Untuk satu sesi per hari mengajar ia dibayar Rp200 ribu. Dalam satu bulan ia empat kali mengajar. Lumayan untuk tambahan uang jajan atau biaya cicilan.
Tak terasa kami berbincang sampai rembulan telah muncrat mengisi kegelapan. Tiba-tiba handphone-ku berdering. Bunyi telepon. Kuangkat. Nama pacarku keluar dari layar handphone-ku, “Aku baru selesai pemotretan. Kamu di mana? Bisa kesini gak? Temenin aku sekalian cari makan. Aku di Studio Selatan,” ucap pacarku.
Seketika aku ingat bahwa Studio Selatan yang terletak di daerah Blok M itu berada di lantai 3, dan di lantai dasarnya ada sebuah kedai kopi yang lumayan gaul dan kalcer abis (kalau kata anak Jaksel), Coffee On Seven, namanya. Kebetulan tiga orang kawanku bekerja di sana.—“Okay. Tunggu. Aku kesana,” jawabku.
Aku pun meminjam kendaraan Naufal, dan meminta Herman untuk pulang bareng dengan Naufal, karena kebetulan tempat tinggal Herman bersebelahan dengan rumah Naufal. Betewe, gak modal banget ya gue, kopi gratisan, kendaraan minjam, makan pun ditraktir pacar. Ya, namanya juga pengangguran berkedok freelancer… hahaha…. Nanti gue bales pas sukses hahaha… .
Akhirnya aku tiba di Coffee On Seven. Aku segera menuju ke dalam. Pacarku menunggu sambil menikmati salad dan secangkir matcha green tea. Tiba-tiba dari arena bar, kedua kawanku memanggil, “Woey, gak sopan lo ye, main lewat-lewat aja.” Itu adalah suara Sadam dan Husen. Dua bapak muda yang menekuni profesi sebagai barista.
Sadam sudah tiga tahun bekerja di Coffee On Seven, bapak satu anak ini sudah jadi headbar di tempat ini. Sementara Husen baru setahun bekerja di Coffee On Seven untuk menghidupi tiga anaknya yang masih balita.
“Hahaha bentar. Gue nemenin cewek gue dulu. Nanti kita ngobrol,” kataku menjawab sapaan mereka sambil berlalu menghampiri pacarku. Salam. Chitchat. Tanya kabar dan kondisi. Fafifu ala Kahlil Gibran. Pergi cari makan.
Long story short, aku dan pacarku telah selesai makan dan kembali ke Coffee On Seven. Coffeeshop yang jadi tempat nongkrong anak “Skena” dan para penikmat vinyl (piringan hitam)—Coffee On Seven juga menjual vinyl musik dan juga kaset tape—ini hanya buka sampai pukul 22, namun setelah coffeeshop ini tutup dan para pekerjanya closingan mereka kerap lanjut nongkrong hingga dini hari bersama para pengunjung lainnya yang masih ingin menetap di situ. Acap kali pengunjungnya juga para barista dari kedai kopi lainnya.
Aku dan pacarku akhirnya ngobrol dengan Sadam dan Husen selepas mereka bekerja, dan ada juga Juminten (tapi gak kuliah di Washington. Kalau malam nongkrongnya pun di Wijaya bukan di Las Vegas), seorang barista dari kedai kopi paling terkenal dan katanya terenak se-Jakarta. Kopi Meser.
Topik yang kuangkat dalam obrolan pun masih sama dengan apa yang kuperbincangkan bersama Naufal dan Herman tadi. Serentak ketiganya menjawab, “Ah temen lo mah masih mending! Lah gue?!” Mereka akhirnya menuturkan kisahnya.
Sadam, bapak satu anak yang antikerja formal. Dia tidak bisa bekerja di kantoran yang terlalu tertib dan tidak santai. Ketika ia menikah dan berkeluarga, ia memilih bekerja sebagai barista untuk menafkahi keluarganya. Sebagai seorang headbar ia mendapat upah Rp3,5 juta per bulan. Uang sebesar itu di Jakarta, jelas tidak cukup untuk menanggung biaya hidup dirinya beserta keluarganya. Akhirnya, istrinya pun ikut bekerja untuk membantu keuangan keluarga, dan anaknya diasuh oleh kakek-neneknya selama orang tuanya bekerja. Bahkan, orang tua Sadam dan istri juga kerap membantu keuangan mereka, dan pinjal-pinjol sudah jadi hal yang lumrah buat mereka.
Begitu pun dengan Husen. Husen hanyalah barista biasa. Upahnya hanya Rp2,5 juta per bulan. Sementara anaknya tiga. “Gila, bisa-bisanya ini orang punya anak banyak dengan upah sekecil ini,” batinku.
Sama seperti Sadam, Husen bekerja 8 jam per hari dengan sehari waktu libur selama sepekan. Upah Husen sebagai barista hanya cukup untuk membayar uang sewa kontrakan dan tagihan listrik. Sementara untuk kebutuhannya dan keluarga sehari-hari ia dapatkan dari berdagang dan bantuan dari orang tuanya masing-masing. Kebetulan isteri Husen berdagang perabotan rumah tangga secara online di salah satu e-commers. Modalnya ia dapat dari hasil Pinjol, bantuan orang tua, dan menjual kendaraan istrinya. Husen juga kerap mencari sambilan menjadi joki game Moba, Mobil Legend untuk tambahan keuangan keluarga. Coffeeshop dengan profit mencapai puluhan juta rupiah kok bisa-bisanya mengupah pekerja semurah ini. Duh, gak habis pikri.
Berbeda dengan Sadam dan Husen yang sudah berkeluarga, Juminten masih lajang. Usianya pun baru 23 tahun, terpaut 7 tahun dari usia Sadam dan Husen. Juminten adalah gambaran barista Jakarta yang sering kita lihat: muda, fashionable, humble, funny, menggunakan iPhone terbaru, dan Vespa matic. Outfit-nya pun tidaklah murah. Ia mengenakan tank top Uniqlo seharga Rp230 ribu, outers Zara seharga Rp500 ribu, jam tangan Daniel Wellington seharga Rp6,2 juta, celana Jeans TRF Cargo merek Zara seharga Rp1,1 juta, dan sepatu boots Docmart X Jean Michel Basquiat seharga Rp5 juta. Semuanya orisinil maprend, gokil. Jika ditotal, harga outfit-nya saja mencapai Rp14 jutaan. WOW!
Memangnya berapa upah Juminten sebagai seorang barista di Coffeeshop Kopi Meser? Ternyata hanya Rp3,5 juta per bulan. Dengan jam kerja 48 jam sampai 54 jam per pekan. Padahal Kopi Meser adalah kedai kopi yang sangat terkenal di Jabodetabek, karena Kopi Meser-lah yang menciptakan dan mempopulerkan kopi susu gula aren yang kerap kita minum sekarang. Bahkan Presiden Jokowi suka ngopi di sini loh—bodoamat sih doi mau ngopi di mana juga harga, ‘kan bahan baku tetap makin mencekik dan korupsi, kolusi, nepotisme tetap tumbuh lebih subur dari sawah yang digusur. Upss! Becyandaaa, becyandaaa.
Kopi Meser juga sudah memiliki 12 cabang dengan jumlah pekerja sebanyak 200 orang (data: ukmindonesia.id). Per hari Kopi Meser berhasil menjual ribuan gelas kopi dengan keuntungan bersih ratusan juta sampai miliaran per bulan (data: sunmedia). Namun upah pekerjanya hanya kisaran Rp1,5 juta sampai 3,5 juta per bulan. Sungguh di luar nurul.
Aku masih sibuk misuh-misuh mendengar realitas upah barista yang sungguh ramasook, cuk! Tiba-tiba pacarku nyeletuk, “Lah, itu anaknya mbak Rica-rica deket rumah kita kan juga kerja di kedai kopi. Bareng sama adiknya kawanmu lho, Mas. Kata mbak Rica-rica, anaknya cuma digaji Rp700 ribu – Rp900 ribu per bulan. Jam kerjanya pun 48 jam per pekan. Bahkan, ia mengerjakan semua pekerjaan. Dari bikin kopi, ngantar kopi, memasak, bersih-bersih, nyuci piring dan gelas, hingga memastikan stock opname. Untung aja dia gak sekalian di suruh bikin plang jalan dan ngajar anak-anak kecil kayak anak KKN”. Nih, nih, nih, nih, parah sih, fak kata gua teh.
Sebuah Ironi dan Semburat “Kalcer”
Setelah perbincangan hari itu, aku jadi punya spirit yang berbeda ketika ngopi di kedai kopi: Ngajakin cengkrama kawan-kawan pekerja kedai kopi. Dari sekian buruh kedai kopi yang kutemui banyak sekali para pekerja seperti Naufal, Husen, maupun Juminten. Berpenghasilan kecil, tidak punya pilihan hingga harus bertahan meskipun getir, terkena ilusi kemapanan dan kalcer metropolis, tak terelakan untuk berjabat erat dengan Pinjol, sembari berucap harap, “Semoga kelak nasib pekerja kedai kopi jauh lebih layak dari saat ini”.
Tapi, jangan salah paham, Gaes. Tanpa bermaksud melakukan normalisasi, pilihan dan cara berpakaian para barista itu bukan sebab nafsu angkara duniawi, tapi karena jenis dan lingkungan pekerjaan menuntut para pekerja bertindak demikian. Hanya masalahnya, tuntutan pekerjaan dalam wujud pakaian fashionable tidak diperhitungkan sebagai bagian dari yang harus diperhitungkan dalam upah. Kan gak mungkin juga barista pake baju koko atau pake jaket Ojol.
Bisa kita lihat, banyak sekali karya-karya budaya pop yang berhasil memotret kehidupan barista atau pekerja kedai kopi. Dari film, musik, video clip, maupun video iklan. Mereka memotret para pekerja kedai kopi dari apa yang dilakukan hingga apa yang melekat di tubuh mereka. Namun, hampir tidak ada budaya pop di Indonesia yang merekam hiperrealitas dari para pekerja kedai kopi; berupah kecil, tidak memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tidak dipayungi dengan tegas oleh undang-undang, mesti berurusan dengan pinjol dan pegadaian untuk menyokong biaya hidup dan gaya hidup mereka, dan tidak saling terhubung bahkan dengan kata lain tidak berserikat!
Potret budaya pop yang secara serampangan mencampur aduk momok pekerja kedai kopi dengan momok para pemuda borjuis metropolis inilah yang akhirnya menjadi spektrum pekerja kedai kopi khususnya barista mesti fashionable, humble, funny, memakai outfit dan atau barang-barang branded berkelas, hingga terlihat keren dan elegan bak muda-mudi borjuis metropolis. Ditambah lagi dengan aturan gak genah dalam lowongan pekerjaan, ‘berpenampilan menarik.’What defak! Akhirnya, momok ini menjadi fenomena yang melahirkan kalcer barista ibu kota yang hedonis.
Fenomena kalcer barista ini juga menimbulkan bias kelas pada sesama pekerja atau barista kedai kopi. Mereka yang terlihat fashionable dan berkelas yang bekerja dengan mesin kopi yang canggih dan mahal (harganya mencapai puluhan juta rupiah) akan mengentaskan para barista yang sederhana namun bersahaja seperti pekerja kedai kopi Jatiman dengan sebutan tukang kopi Warkop, bukan barista. Seakan menerjunkan mereka ke jurang kasta yang lebih rendah. Padahal, sejatinya, mereka sama-sama penyeduh kopi, sama-sama pekerja kedai kopi, sama-sama buruh, dan jelas sama-sama proletariat.
Dari sekian banyak kompleksitas problematika yang dialami para pekerja kedai kopi, negara, lewat segala kuasa dan kebijakannya ternyata belum mampu memayungi dan menaungi para pekerja kedai kopi. Alih-alih mencoba menyejahterakan para pekerja kedai kopi, negara malah menambah parah kegetiran dengan disahkannya UU Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) menjadi Cipta Kerja. Sebab, dalam UU yang tidak berpihak pada kelas pekerja itu, negara tidak mewajibkan para pengusaha mikro kecil untuk membayar upah pekerja sesuai dengan standar upah minimum. Akibatnya, banyak para pengusaha yang semena-mena dan serampangan dalam mengupah pekerja. Dalam konteks kedai kopi, banyak kedai kopi yang sudah memiliki PT tapi masih berlindung dan menyamar sebagai UMKM. Sialan!
Sebuah ironi juga bisa kita lihat kepada kawan-kawan aktivis perburuhan, yang hingga saat ini masih memfokuskan lini gerak dan sorotan landscape kelas pekerja kepada para buruh pabrik atau buruh manufaktur. Padahal, segala kesenjangan dan penghisapan juga dialami oleh kawan-kawan buruh FnB, termasuk para pekerja kedai kopi. Kantongnya cekak dicekik kebutuhan hidup, lambungnya tergerus caffein dan pikiran batin, dan kesejahteraannya masih sekedar angin dalam angan.[]
***
Catatan: Nama kedai kopi disamarkan. Penulis khawatir para pemilik kedai kopi akan melayangkan somasi atau ajakan berkelahi di dalam ring tinju ala Jefri Nicole.