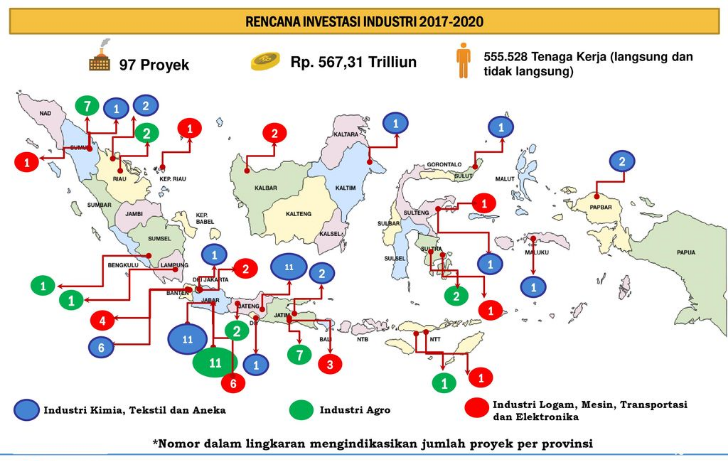Review “The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto’s New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area” karya Deden Rukmana.
Anak kecil pun tahu bahwa Indonesia sedang berjalan menuju bencana. Korupsi merajalela, lingkungan hidup diperkosa, dan rakyat makin melarat. Dalam menelusuri sejarah tata ruang di Indonesia, Rukmana memberi beberapa alasan yang umum didengar: kesewenangan demi keluarga pejabat, kurangnya pakar dalam negara, penerimaan suap, korupsi, tidak diberlakukannya rencana jangka panjang, sentralisasi berlebih, dan seterusnya. Alhasil, jumlah wilayah konservasi, penyerapan air, dan daerah pertanian diubah menjadi ‘hutan beton’ kota industri.
Rencana tata ruang tidak ada artinya karena bisa diubah sesuka hati penguasa berdasarkan keperluan developer. Hanya 8% bangunan di Jawa Barat yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sementara hukuman atas penyelewengan rencana tata ruang hampir tidak pernah ditegakkan. Sekarang, ruang hijau di Jakarta hanya sebesar seperlima ruang hijau semasa 1970an. Kelapa Gading Mall dibangun di atas daerah penyerapan air dan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk dibangun dengan membabat hutan lindung.
Solusinya, mengutip seorang akademisi UI, adalah birokrasi hukum ketat dengan kerangka berpikir baru dan budaya baru, seperti Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Jawaban seorang birokrat sejati. Masalah politik disulap menjadi masalah teknis dan budaya.
Ruang itu sendiri adalah komoditas, alat produksi, lingkungan hidup, dan situs perang kelas sekaligus. Hubungan manusia dengan ruang, dan ruang itu sendiri terbentuk oleh hubungan kerja dan tenaga produksi bersama dengan kontradiksinya, bukan birokrasi, kerangka berpikir, dan budaya tertentu.
Pemikiran tidak turun ajaib dari langit. “Bukan kesadaran yang membentuk kehidupan. Kehidupan membentuk kesadaran.”[1] Misalnya, seperti dikutip dalam artikel Rukmana, pembangunan bangunan tinggi datang dari keterbatasan tanah murah terpusatkan untuk kepentingan pengusaha dan kemajuan teknologi produksi alat kendaraan. Sebaliknya, ruang menciptakan pola perilaku, tanggapan emosi, dan pemikiran tertentu, yang mempengaruhi perkembangan hubungan kerja dan tenaga produksi.
Novel Pramoedya Gadis Pantai adalah salah satu penelitian tata ruang paling provokatif dalam sastra Indonesia. Argumen dasarnya adalah tata ruang kota perkawinan Islam dengan feodalisme Jawa menciptakan istri dan ‘atasan’ ideal: taat pada atasan (suami) dalam segala urusan, pendiam, ikut-ikutan, tidak bekerja, kecanduan berdandan, dan menghilangkan kesadaran atas diri sendiri.
Penelitian Rukmana bernilai sebagai catatan rinci perkembangan dan implementasi birokrasi tata ruang di Indonesia. Sayangnya, pendekatan ideologi teknis pada tata ruang, Rukmana menghilangkan ruang itu sendiri dan berbagai kontradiksinya. Alhasil, hanya kumpulan catatan hukum, efektivitas birokrasi, dan dokumentasi maraknya kesewenangan.
Perjuangan petani melawan penggusuran seakan tidak pernah terjadi, ideologi rasial dalam tata ruang Indonesia menjadi buta warna, dan akumulasi primitif sebagai syarat industrialisasi yang mengharuskan kesewenangan rencana tata ruang oleh pengusaha melenyap jauh. Bukan hilang tanpa alasan, semua ini menjadi tak terlihat berkat ideologi kelas berkuasa. Dalam kalimat lain: ruang tidak muncul dalam penelitian tata ruang. Halusinasi luar biasa!
Salah berpikir maka salah bertindak, salah bertindak maka salah berpikir. Rekomendasi Rukmana adalah sistem tata ruang gaya Lee Kuan Yew.
Biarlah Lee Kuan Yew sendiri berbicara. “Saya sering dituduh mengganggu kehidupan pribadi warga. Ya, jika saya tidak melakukannya, kita tidak akan berada di sini hari ini. Dan saya katakan tanpa sedikitpun penyesalan, bahwa kita tidak akan berada di sini, kita tidak akan mencapai kemajuan ekonomi, jika kita tidak campur tangan dalam hal-hal yang sangat pribadi – siapa tetangga Anda, bagaimana Anda hidup, kebisingan yang Anda buat, bagaimana Anda meludah, atau bahasa apa yang Anda gunakan. Kami yang memutuskan apa yang benar. Tidak peduli apa yang dipikirkan rakyat.”[2] Sekejap ideologi teknis telanjang dan tampak apa adanya sebagai taring berdarah penindasan. Di mata birokrasi, rakyat hanya hewan ternak, terus bekerja dan berkembang biak di dalam kandang demi kemajuan ekonomi.
Perubahan Singapura dari desa nelayan primitif menjadi kota industri modern dibangun atas penderitaan rakyat. Setengah abad sebelum pembakaran Pancoran Buntu II untuk kepentingan Pertamina, negara Singapura sudah membakar perumahan 16,000 warga Bukit Ho Swee sembari membunuh 4 warga dan melukai 54 warga lainnya.[3]
Akar kebijakan perumahan Singapura datang dari penjajahan Inggris, terutama masa darurat militer melawan gerilya pergerakan komunis. Rakyat dipisahkan dari tanah pertanian, lahan peternakan, dan perumahan asalnya dengan jarak sangat lebar antar rumah di sekitar perhutanan–dalam kata lain, kondisi ideal untuk perang gerilya.
Penciptaan sistem perumahan didatangkan bersama dengan kontrol pemerintahan atas alat produksi dan penguatan kontrol negara. Terceraikan dari usaha mereka sendiri, rakyat diawasi ketat dan tidak diberi makanan jika tidak menjual informasi tentang pejuang komunis.[4]
Kiranya Inggris mencontek tanggapan penjajahan Belanda dalam melawan gerilya rakyat di Bangka Belitung. “Kampung” adalah hasil ciptaan penjajahan, bukan tradisi sistem produksi Bangka Belitung. Petani biasanya tinggal di lahan sendiri, berpindah-pindah, dan jauh dari tetangga lainnya, walaupun ikatan saling membantu erat. “Kampung” padat dengan rumah saling bersebelahan diciptakan untuk memotong suplai makanan perjuangan gerilya.[5] Inikah yang didambakan para akademisi pemakan uang rakyat?
Rakyat terjajah dengan mentalitas budak memang suka meniru penjajahnya sendiri. Kebijakan tata ruang rasis periode Soekarno dengan PP10 yang melarang orang “asing” (Tionghoa) berdagang di kota kecil dan pedesaan sama saja dengan kebijakan Belanda sebelum tahun 1910. Sebenarnya lebih biadab dari Belanda karena PP10 disusul dekrit mengizinkan militer untuk menendang orang “asing” dari rumahnya sendiri. Berbagai menteri sepanjang periode Soekarno ikut mengulang propaganda rasis Belanda. Pramoedya, yang menulis Hoakiau di Indonesia untuk mengkritik PP10, dipenjarakan tanpa pengadilan.
Berdasarkan pendekatan ideologi teknis Rukamana, tidak ada ras dalam sejarah tata ruang Indonesia. Ras hanya “politik identitas”, perbedaan budaya yang dimanipulasi kekuasaan. Lantas apakah PP10 datang dari langit? Atau mungkin Soekarno sedang bosan main perempuan, maka iseng memutuskan untuk menginjak kepala setengah juta orang Tionghoa? Sama sekali konyol. Pada tahun tersebut, monopoli negara militer diperluas ke 75% sektor impor sehingga jumlah importir turun dari 4,000 ke hanya 100 pengusaha.[6] Untuk menciptakan vakum ekonomi yang bisa diisi pengusaha mantan importir, pedagang kecil Tionghoa dijadikan tumbal kepentingan negara militer. Kaburnya orang Tionghoa dari Indonesia kemudian kembali memperkuat ideologi bahwa orang Tionghoa sejatinya adalah orang asing. Memang, kami tercinakan dan terasingkan di rumah sendiri. Demikian contoh singkat tali temali proses akumulasi kapital, negara militer, pembentukan ras, dan sejarah penjajahan di Indonesia.
Kita ingin perubahan. Ruang, isi dan bentuknya, adalah titik perjuangan penting bagi perlawanan Indonesia. Reforma agraria perkotaan perlu merombak bentuk ruang dan lingkungan hidup, bukan hanya hak milik atas tanah. Maraknya perampasan tanah petani, perampokan hutan adat, banjir rutin setiap tahun, perumahan penuh penyakit, derita anak jalanan, dan korban kekerasan seksual yang tidak punya ruang, semuanya saling terikat dalam permasalahan ruang sebagai proses akumulasi kapital dan pembentukan ideologi negara.
Ruang bukan hanya penting sebagai sesuatu yang perlu diubah setelah revolusi, namun masuk dalam aspek strategis perjuangan revolusioner itu sendiri. Kenapa serikat buruh daerah masih berkumpul di ruang Jakarta untuk demo hari buruh? Kenapa wawasan teoritik kita identik dengan ruang pulau Jawa, seperti karya Rukmana itu sendiri? Kenapa ruang kolektif punk kotor bukan main dan penuh nyamuk? Kenapa pertemuan diskusi aktivis di kafe setengah terang dengan musik ngantuk? Sekali lagi: salah bertindak maka salah berpikir, salah berpikir maka salah bertindak!
Catatan kaki
[1] Karl Marx, The German Ideology
[2] The Straits Times. 20 April 1987.
[3] Loh Kah Seng, Squatters into Citizens: The 1961 Bukit Ho Swee Fire and the Making of Modern Singapore.
[4] Wen Qing Ngoei. Arc of Containment.
[5] Mary F. Somers. Bangka Tin and Mentok Pepper.
[6] J.A.C Mackie. The political economy of guided democracy.