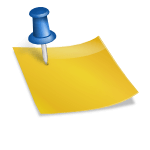Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Tujuannya, menyediakan perlindungan kepada buruh, alat kerja dan material kerja agar produktivitas perusahaan tercapai.
Dalam pelaksanaannya, K3 diturunkan menjadi produk peraturan perundang-undangan. Misalnya dari aturan terbawah di suatu perusahaan yakni SOP serta Manual, hingga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan paling tertinggi adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.1
Dari penjabaran di atas dapat kita lihat, bahwa bicara K3 dapat dikatakan juga sebagai bicara penegakan hukum, dalam hal ini hukum ketenagakerjaan.
K3 dan hukum memiliki irisan yang sama. Kita tidak dapat menyatakan sesuatu pekerjaan harus dikerjakan dengan standar urutan kerja tertentu, atau menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) tertentu tanpa menetapkan Instruksi Kerja/Prosedur Kerja/SOP mengenai pekerjaan tersebut. Prosedur tersebut juga harus disahkan dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja di bagian tersebut untuk menjadi ketetapan yang wajib dipatuhi oleh bagian/unit/seksi tersebut.
Prosedur atau SOP merupakan acuan dan pedoman mutlak yang disepakati oleh manajemen perusahaan terhadap pekerjaan berisiko tinggi, agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang patuh kepada prosedur tersebut diberikan penghargaan atau reward, yang abai dan tidak patuh dijatuhi hukuman serta sanksi. Idealnya K3 bekerja dengan hasil seperti itu.
Kebijakan K3 di suatu negara dilandaskan pada produk hukum K3 yang diterbitkan negara tersebut. Hukum K3 di Indonesia mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Dalam rangka menerbitkan peraturan perundangan mengenai K3, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan. Fakta yang diketahui bersama, yakni UU No. 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sendiri sudah berusia hampir 55 tahun, namun tidak kunjung dibahas ataupun dibahas. Berita mengenai pembahasan K3 dalam RDP di DPR juga jarang terdengar, apalagi jika kita meminta untuk revisi UU Keselamatan Kerja. Kepentingan politik terhadap K3 sendiri masih tergolong minim di Indonesia, dibuktikan dengan paparan di atas. Belum lagi, kita bicara mengenai pengawasan K3 oleh lembaga eksekutif maupun legislatif.
Namun itu jika dikaitkan dengan negara, terlalu luas bukan? Bagaimana kalau kita perkecil kembali di ruang lingkup perusahaan?! Suatu perusahaan baik CV atau PT yang dimiliki oleh satu atau sekelompok orang tergantung skalanya, serta umumnya dipimpin oleh Direktur (dalam UU 1/1970 disebut Pengurus), memiliki peran serta tanggung jawab membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan menjalankan program K3 di perusahaannya. Di sinilah letak politik kepentingan, yakni kepentingan dari pemilik dan pengurus atau manajemen perusahaan. Apakah manajemen mengutamakan profit? ataukah mereka mengutamakan efisiensi dan penghematan? Jika tujuan utama adalah hemat maka K3 akan tampak seperti suatu extracost yang akan membuat para manajer keuangan marah besar, dan akhirnya mencoret anggaran mengenai K3. Ini terjadi dimana-mana, baik di perusahaan subkontraktor kecil hingga perusahaan besar.
Pada kampanye K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan) atau Apel Besar, atau katakanlah pada perayaan Bulan K3 Nasional, seorang direktur akan mengatakan pada seluruh buruh untuk patuh terhadap aturan K3, yang tidak patuh maka akan diberikan sanksi. Namun, bisa jadi direktur tersebut juga yang memutuskan untuk tidak benar-benar mengimplementasikan sistem manajemen K3, direktur tersebut juga yang tidak menganggarkan training K3 pada level manager sampai pengawas atau SPV di lapangan, serta abai dalam memastikan manajemennya memiliki kompetensi standar K3. Direktur tersebut mungkin lalai, mungkin juga kurang mendapatkan pemahaman dan informasi mengenai Sistem Manajemen K3. Permasalahannya, tidak ada satu orang pun yang mampu memberitahu direktur, bahwa kesalahannya terpusat pada kebijakan dan gerak langkahnya.
Sementara itu, hukum dalam dunia K3 erat kaitannya sebagai suatu alat atau parameter yang menyatakan suatu perusahaan patuh pada K3 atau tidak. Standar kepatuhan dapat dipantau dengan cara membandingkan pasal-pasal yang tertera pada produk hukum tersebut untuk kemudian dinilai gap atau selisih pemenuhannya. K3 juga memberlakukan acuan-acuan yang didasarkan pada hukum yang berlaku, contoh pada Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, yang mengatur mengenai Nilai Ambang Batas bahaya paparan di tempat kerja. Standar ini kemudian dijadikan acuan, dipatuhi, dan dijalankan oleh perusahaan. Setidaknya itu yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.
Dalam pelaksanaannya, banyak aspek peraturan perundangan K3 yang tidak mampu dipatuhi oleh perusahaan. Kendala atau alasan ketidakpatuhan cukup banyak: dari disinformasi, aturan sulit dimengerti, tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan program secara konsisten, hingga ketiadaan komitmen manajemen untuk mematuhi aturan tersebut. Perusahaan menjadi tidak patuh, atau tidak menjalankan amanat peraturan K3 yang berlaku.
Hukum K3 hanya terlihat sebagai hukum yang ideal ditegakkan. Namun penegakan di lapangan justru membenturkan kepentingan perusahaan dengan keselamatan dan kesehatan buruh. Hal ini diperburuk juga dengan minimnya pengawasan dari lembaga pemerintah yang minim dari Kementerian Ketenagakerjaan, dibantu Dinas Ketenagakerjaan Provinsi suatu daerah.
Pengawas sendiri hanyalah sebagian kecil dari Disnaker Provinsi yang diamanatkan oleh UU untuk menjadi penegak hukum K3 di tingkat provinsi. Pengawas ketenagakerjaan, sebagaimana pengalaman kami bekerja sama dan berkomunikasi dengan pengawas di daerah, tampak tidak mampu menjangkau seluruh perusahaan yang berada di provinsinya. Dugaan yang kuat mengapa ini terjadi yakni faktor kekurangan personil pengawas, atau cakupan kerja yang terlalu luas, sehingga pengawas yang menjadi penegak hukum K3 sulit menjangkau perusahaan.2
Data Q4 tahun 2024 Kemnaker menunjukkan sebanyak 104 perusahan di Jateng sudah menerapkan SMK3 PP 50.3 Namun pengawas Disnaker hanya melakukan kunjungan kepada sektor manufaktur. Padahal perusahaan di Jawa Tengah mencapai puluhan ribu dengan berbagai jenis lapangan usaha. Ketidakhadiran pengawas ketenagakerjaan mendorong manajemen untuk tidak perlu “patuh terhadap aturan”. Akhirnya, menjadikan penerapan K3 bukan didasarkan pada pemenuhan hukum peraturan perundangan nasional atau daerah, melainkan tuntutan customer/pelanggan saja.
K3 berarti adalah suatu “kesejahteraan” dan “perlindungan” bagi masyarakat ataupun buruh yang berada di bawah naungan suatu organisasi. Berbicara K3 juga berarti berbicara mengenai konsep keadilan, penegakan aturan, ketidakcondongan terhadap suatu kepentingan. Pendekatan K3 seharusnya selalu berada di tengah antara manajemen dan buruh. Tidak timbang sebelah. Pemerintah perlu hadir melalui pengawas ketenagakerjaan pada dinas ketenagakerjaan di daerah. Karena pekerjaan ini tidak akan sanggup ditegakkan oleh seorang Ahli K3 Umum di tempat kerja. Seorang Ahli K3 Umum di perusahaan tidak memiliki pengaruh apalagi membuat keputusan mengenai implementasi Sistem Manajemen K3 untuk keseluruhan operasional perusahaan.
Namun K3 jika dilakukan secara benar dan sesuai penegakan dan pengawasannya maka secara tidak langsung akan memperbaiki sistem lainnya pada perusahaan tersebut. Berikut kaitan antara K3, politik, dan hukum yang dapat kita ambil sebagai benang merah. K3 sebagai tujuan akhir, politik sebagai medium perantara, dan hukum sebagai penegaknya. Panjang umur perjuangan!
Daftar Referensi
Jika Anda menikmati membaca cerita ini, maka kami akan senang jika Anda membagikannya!