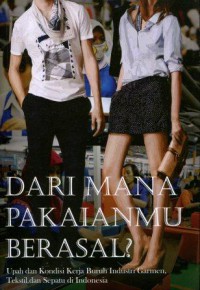
Dari Mana Pakaian dan Sepatumu Berasal?
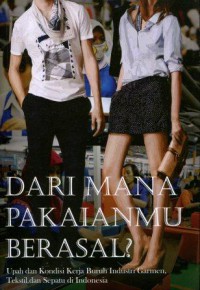
Dari Mana Pakaianmu Berasal: Upah dan Kondisi Buruh Industri Garmen, Tekstil dan Sepatu di Indonesia
Penulis: Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir dan Syarif Arifin
Penerbit: Tanah Air Beta
Tahun Terbit: 2016
Pemain bola, David Beckham dan pemain bola dunia lainnya mungkin tak pernah membayangkan bahwa sepatu olahraga yang mereka pakai, dibuat dari keringat para buruh-buruh perempuan di Tangerang dan Jakarta.
Begitu juga dengan baju olahraga. Baju yang terpampang di mall-mall, pusat pertokoan modern. Ini adalah baju-baju yang tiap hari dibuat oleh jerih payah para buruh pabrik perempuan. Mereka bekerja dengan tekun di pabrik tekstil, namun naasnya, tak bisa dengan mudah memiliki sepatu dan baju-baju yang telah dijual dengan harga mahal ini.
Sebuah buku yang berjudul “ Dari Mana Pakaianmu Berasal?” yang ditulis oleh Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir dan Syarif Arifin dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Lembaga Tanah Air Beta dan Clean Clothes Campaign yang diterbitkan di tahun 2016, kemudian melengkapi catatan-catatan atas nasib yang terjadi pada buruh perempuan di Indonesia.
Buku ini merupakan hasil riset terhadap kondisi dan upah buruh di industri tekstil di Tangerang dan Serang, Banten sekaligus hasil pemetaan kondisi buruh perempuan di Jakarta . Hampir 90% buruh yang bekerja di garmen/tekstil adalah perempuan.
Buku ini juga membuka catatan tentang berbagai bentuk pelanggaran hak dasar buruh perempuan seperti: kebebasan berserikat dan berunding serta hilangnya jaminan upah layak di pabrik. Penelitian ini juga berdasar pada pemerintah dan asosiasi bisnis yang melakukan kebijakan upah murah.
“Menciptakan lapangan kerja dengan selalu merawat iklim investasi adalah alasan yang sering sekali dibuat dan dikatakan untuk mempertahakankan upah murah di Indonesia (Hal.5)”
Upah buruh di Indonesia dalam catatan penulis, paling murah jika dibandingkan negara: Filipina, Thailand, Malaysia, India dan China. Industri tekstil dan garmen sangat mengandalkan upah murah, khususnya sepatu dan baju dari merk-merk terkenal di dunia.
Namun, pencurian upah terus terjadi. Pencurian upah misalnya dilakukan dengan perlakuan pada buruh untuk memperpanjang jam kerja, padahal kerja-kerja lembur seperti ini tidak dibayarkan. Dalam beberapa hal, kondisi ini diperburuk dengan buruh harus mengeluarkan biaya tambahan agar bisa dterima bekerja karena perusahaan mengisyaratkan adanya biaya lamaran/ rekrutmen.
Sementara di sisi lain, penetapan upah minimum tidak banyak menolong kondisi upah, karena banyaknya celah yang dimanfaatkan pengusaha untuk tetap mempertahankan upah rendah bagi para buruh (Hal. 79).
Padahal dalam seluruh persoalan ini, negara dalam hal ini Disnaker tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan upah minimum karena berbagai alasan, seperti: jumlah tenaga pengawas upah yang terbatas, jumlah anggaran yang terbatas dan kewenangan yang terbatas.
Padahal negara harusnya memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran atas upah dan dihilangkannya kondisi kerja buruk.
Dalam catatan serikat pekerja , dalam kurun waktu 2007-2009 banyak buruh yang diberhentikan, kemudian setelah diberhentikan, mereka dipekerjakan kembali sebagai buruh kontrak atau outsourching. Dengan catatan bahwa para buruh ini akan menerima: upah lebih rendah, tidak diangkat sebagai karyawan, kehilangan tunjangan dan tidak boleh berserikat.
Dalam buku ini juga disebutkan, Nining Elitos dari Serikat buruh KASBI mengatakan bahwa jumlah buruh outsourching jumlahnya sebanyak 60%. Sementara Rudi HB Daman dari Serikat buruh GSBI menyatakan bahwa jumlah buruh outsourching ini bertambah 5% pertahunnya (Hal. 39-40)
Selain itu para buruh juga mengalami ancamana relokasi. Pengusaha akan berpindah tempat semaunya di tempat lain/ di kota lain yang gaji buruhnya lebih murah. Akibatnya banyak pemecatan yang dilakukan sewaktu-waktu dan sepihak.
Hal lain, yaitu terjadinya diskriminasi gender pada perempuan, misalnya: diperlakukan secara diskriminatif karena mereka perempuan, seperti dirayu, dicolek tubuhnya. Banyak laki-laki yang menyalahgunakan jabatan untuk merayu buruh buruh perempuan.
Padahal banyaknya larangan untuk membuat serikat pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terus terjadi.
Inilah yang membuat pertanyaan besar terus dilontarkan: Dari mana pakaian dan sepatu kita berasal? Buruh perempuanlah adalah alas kakinya. Ia berkeringat, tak kenal menyerah, walau harus menelan kepahitan: diupah murah, dilecehkan dan selalu dianggap sebagai buruh di kelas paling bawah. Tak punya martabat.
Artikel ini pernah dipublikasikan di Konde.co, 17 Juni 2017
