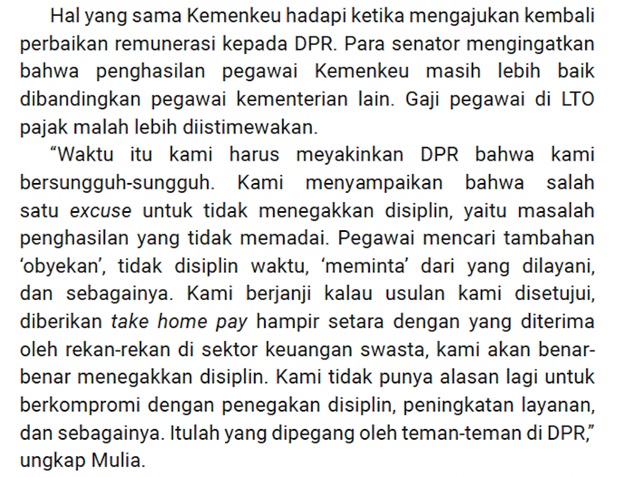Belakangan ini, pemerintah gencar mendorong wacana aparatur sipil negara (ASN) berwirausaha dengan alasan untuk dapat berkontribusi pada perekonomian negara.
Ini tentu menuai reaksi dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sendiri. Sebab, himbauan ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi, khususnya gagasan tentang urgensi penghasilan tunggal (single salary) dan layak (decent salary) bagi seluruh pekerja publik atau ASN se-Indonesia.
Isu penghasilan, dari kacamata ASN, merupakan isu substantif yang kerap menjadi salah satu faktor utama mengapa reformasi birokrasi di Indonesia seakan jalan di tempat.
Ketimpangan penghasilan ASN: isu yang terabaikan
Isu penghasilan sesungguhnya bukan isu baru dalam literatur antikorupsi. Riset terdahulu telah mengungkap bagaimana di bawah kepemimpinan Suharto, rezim Orde Baru melanggengkan kekuasaannya dengan memberikan gaji yang rendah kepada para PNS.
Praktik “uang terima kasih”, pungutan liar (pungli), penggelapan anggaran, dan sejenisnya pun seakan menjelma menjadi sebuah “tradisi” demi bertahan hidup di tengah kecilnya penghasilan.
Ini sejalan dengan studi lapangan saya pada 2014 yang menemukan bahwa praktik korupsi sebagai cara pemenuhan kesejahteraan, khususnya di level birokrat akar rumput, masih terus langgeng.
Riset terbaru saya pada 2021 juga masih menunjukkan kondisi serupa, bahwa persoalan ketimpangan penghasilan adalah salah satu isu substantif yang perlu direspons serius oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Riset ini dihimpun dari hasil wawancara dengan lebih dari 70 informan dan penelusuran dokumen resmi serta wacana di media sosial.
Sayangnya, suara ASN akar rumput kerap diabaikan dalam riset-riset antikorupsi yang berparadigma positivisme (hanya melihat permukaan).
Alih-alih membongkar dimensi struktural dari korupsi, perilaku korupsi ditonjolkan sebagai kegagalan moral individu, dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab individu untuk memperbaiki moral mereka masing-masing.
Kebijakan publik yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi juga telah terjebak pada pemahaman ini, dengan mengutamakan jargon-jargon kosong seperti “integritas” dan “akuntabilitas”.
Integritas dan akuntabilitas itu kemudian diterjemahkan secara seremonial yang diyakini akan bisa diwujudkan lewat instrumen-instrumen formal dalam bentuk pakta integritas, dokumen-dokumen standarisasi, penghargaan-penghargaan, dan pelaporan-pelaporan yang kerap tercerabut dari praktik sehari-hari.
Mencatat pengalaman birokrat dalam reformasi birokrasi
Saya mencoba membandingkan pengalaman 27 ASN dari empat instansi publik terkait reformasi birokrasi, yang juga diperkaya dengan analisis dokumen dan analisis media sosial. Saya menemukan bahwa setidaknya ada dua dimensi utama yang memungkinkan reformasi birokrasi bisa berjalan bebas pungli dan berorientasi pelayanan.
Pertama adalah dimensi material, yaitu penghasilan yang layak dan memotivasi bagi pekerja publik.
Ini adalah salah satu unsur krusial yang telah dibenahi di instansi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada awal periode reformasi mereka. Prosesnya terdokumentasikan dengan sangat apik dalam dokumen terbitan mereka sendiri yang isinya juga memuat testimoni para pegawai.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa masalah pungli dan lemahnya produktivitas sulit diberantas jika penghasilan pegawai masih tidak layak. Sebagai solusinya, Kemenkeu memperkenalkan tunjangan kinerja. Meski besaran gaji pokok yang diterima PNS pada golongan yang sama akan sama besarannya (misal gaji pokok untuk PNS awal karir dan lulusan Strata 1 atau S1 adalah Rp. 2.579.400), pegawai Kemenkeu menerima tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja yang nilainya bisa mencapai 2-3 kali lipat gaji pokok, bahkan lebih. Nominalnya jauh di atas kementerian atau instansi publik lain pada umumnya.
Sebagai ilustrasi, berikut narasi yang mewarnai periode awal reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan:
Sumber: Tangkapan layar buku
Dari sini kita belajar bahwa penghasilan yang layak merupakan prasyarat pembenahan kinerja, bukan sebaliknya. Sayangnya, pembenahan di Kementerian Keuangan khususnya pada dimensi material yang berkeadilan tidak kunjung diikuti oleh instansi publik lainnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menggulirkan delapan area perubahan reformasi birokrasi, tetapi terdapat progres yang amat lambat jika berkenaan dengan perbaikan penghasilan pegawai yang layak dan berkeadilan.
Kedua adalah dimensi manajerial, yakni merujuk pada instrumen-instrumen seperti indikator kinerja, dan berbagai sistem pendukung lainnya, termasuk pelatihan dan prasarana kerja yang memadai.
Dimensi manajerial memang penting, tetapi pembenahan SDM organisasi tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa didukung oleh dimensi material dan malah akan melahirkan skeptisisme. Ini persis seperti yang saya temukan dalam salah satu instansi.
Upaya pemenuhan indikator-indikator manajerial kian menjadi seremoni belaka. Mengisi formulir-formulir, membuat seabrek SOP, menggelar perayaan apalagi membuat maskot, bukanlah hal-hal yang dibutuhkan oleh para ASN jika kita menuntut performa yang prima dari mereka sebagai pekerja.
Paradigma fungsionalis yang dianut oleh praktisi SDM pemerintah sudah layaknya ditinggalkan karena tidak partisipatif dan mengabaikan hak-hak ASN sebagai pekerja. Belum lagi tak jarang kita temukan elit birokrasi yang masih membingkai ASN sebagai ‘abdi’, sosok yang ikhlas bekerja tanpa pamrih sebagai bentuk pengabdian.
Di tengah kondisi yang demikian, kenaikan penghasilan yang dijanjikan dalam bentuk tunjangan kinerja di beberapa kementerian, sebagai imbalan bagi instansi yang telah memenuhi kriteria reformasi birokrasi, tidak kunjung ditunaikan dengan alasan kondisi ekonomi negara yang kurang baik, yang sudah tentu menyebabkan pegawai terdemotivasi dan demoralisasi.
Begitu banyak narasi ASN yang muncul di ruang-ruang publik tentang kekecewaan mereka karena standar ganda yang mereka rasakan. Ada pula ketimpangan yang kian tajam yang tertangkap lewat metafora “Sultan versus Jelata”.
Ini berdampak pula pada munculnya kecenderungan pegawai tidak memberikan semua kemampuan mereka di tempat kerja (quiet quitting) karena tidak mau dirinya semakin dieksploitasi.
Langkah ke depan
Reformasi birokrasi telah digulirkan lebih dari dua dekade dan hasilnya belum juga optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah keengganan pemerintah untuk menggarap serius isu penghasilan ASN.
Alih-alih mendorong PNS berwirausaha, pemerintah harusnya fokus pada reformasi birokrasi yang jangan hanya berpijak dimensi manajerial formal, tapi juga mulai memikirkan penggajian ASN yang lebih mencerminkan keadilan dan keberkelanjutan, termasuk salah satunya soal single salary yang mandek sejak tahun 2015.[]
*Artikel ini pernah terbit di Theconversation.com (30 Mei 2023), dimuat ulang untuk tujuan pendidikan.