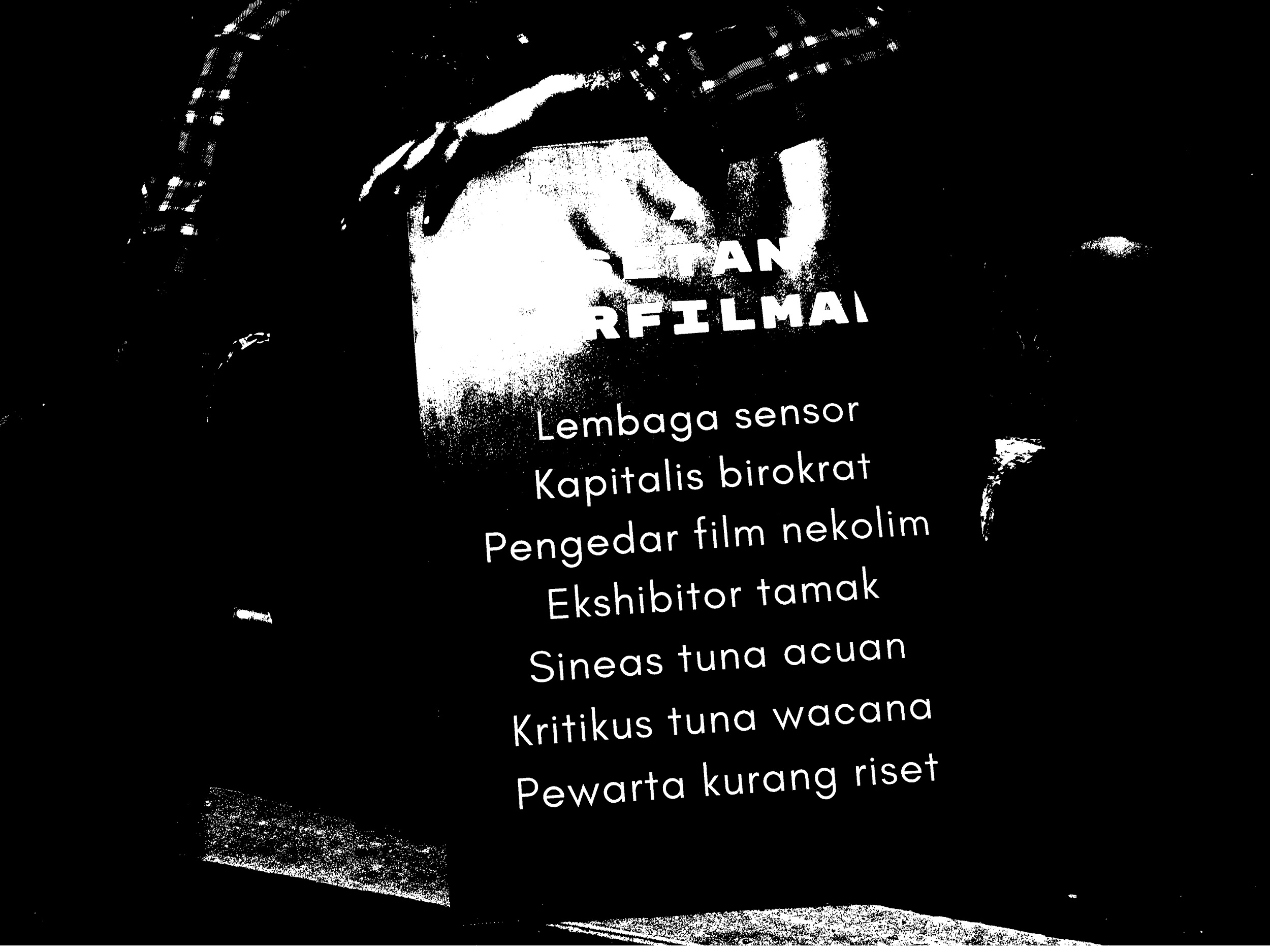Dalam imajinasi saya ketika masih kanak-kanak, menjadi seorang jurnalis serupa dengan superhero dalam cerita fiksi populer. Sebagian kita tentu tahu Peter Parker (Spiderman) dan Clark Kent (Superman). Dalam cerita, selain tokoh yang berperan sebagai superhero, keduanya juga bekerja sebagai jurnalis. Belajar dari dua tokoh fiksi tersebut, saya berpandangan menjadi jurnalis adalah pekerjaan mulia, bervisi keadilan, dan berpihak pada orang-orang yang tertindas.
Namun pandangan itu patah saat saya menginjak bangku kuliah, di usia saya yang baru beranjak 19 tahun. Saat itu saya baru saja berkenalan dengan fakta kematian Fuad Muhammad Syafruddin yang dikenal dengan nama Udin. Seorang jurnalis suratkabar harian asal Yogyakarta, Bernas, yang tewas karena keberaniannya meliput kasus dugaan korupsi calon Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo untuk masa jabatan 1996-2001.
Dunia jurnalisme yang saya khayalkan ketika masih kecil, ternyata adalah dunia yang mengerikan. Udin tewas dibunuh oleh rezim saat bekerja, dan tentu Udin tidak memiliki kekuatan melempar jaring laba-laba atau kekuatan sinar mata laser untuk melawan balik layaknya tokoh fiksi Peter Parker dan Clark Kent. Udin adalah jurnalis suratkabar yang hanya dibekali dengan keberanian dan prinsip keadilan yang kuat.
Kasus pembunuhan Udin menjadi cerita paling mengerikan yang membayangi seorang jurnalis dalam mempertahankan prinsip keadilan. Cerita mengerikan lainnya adalah cerita tentang kondisi kerja jurnalis. Dalam rezim pasar kerja fleksibel, bekerja sebagai jurnalis dipaksa untuk siap hidup dengan upah murah, beban kerja yang tinggi, jam kerja panjang dan hubungan kerja yang rentan untuk dieksploitasi.
Berdasarkan pengalaman saya ketika bekerja sebagai jurnalis lepas pada portal media lokal, upah yang saya terima sangat tidak masuk akal. Hanya dibayar Rp25 ribu per berita. Jika ditotal, selama sebulan, upah yang saya terima hanya mampu untuk mengganti biaya pembelian bensin sepeda motor saya sebulan untuk meliput berita. Sedikit mujur jika upah yang saya terima tersisa, itu pun untuk membeli sebungkus rokok dan segelas kopi sebagai sohib menulis berita.
Saya cukup beruntung, urusan tempat tinggal dan makan, masih ditanggung oleh orang tua saya. Tak jarang pula saya harus bermuka tebal memelas, meminta uang kepada orang tua karena harus mengganti oli motor yang kering akibat perjalanan peliputan berita. Walau tidak sekeren Peter Parker, yang bisa mandiri berpisah dengan Bibi May saat menjadi reporter Daily Bugle, bekerja sebagai jurnalis sungguh saya nikmati tapi tidak dengan upahnya.
Saya termasuk orang yang jarang menghitung berapa artikel berita yang saya liput dan tulis. Seingat saya, bila bernasib baik dan tidak malas-malasan saya bisa menyetor 50-65 berita harian per bulan. Pendapatan saya sebulan berada di kisaran Rp 1.250.000-Rp 1.500.000. Jumlah pendapatan saya tersebut sudah paling mentok, tidak pernah lebih, bahkan lebih sering kurang. Padahal UMK di kota tempat saya tinggal berkisar Rp 4.055.000.
Kondisi serupa juga banyak dialami teman-teman saya sesama jurnalis lapangan yang berstatus lepas dengan media dan suratkabar yang berbeda. Bahkan ada yang hanya menerima upah Rp 600.000-Rp 750.000 per bulannya.
Biasanya, untuk menyiasati kekurangan pendapatan tersebut, para jurnalis mengambil kerja sampingan. Dari bekerja sebagai steward coffeeshop secara part-time, fotografer panggilan, hingga bekerja pada dua atau tiga portal media lainnya.
Hal yang membuat saya miris ketika menekuni dunia jurnalisme adalah kebiasaan di antara para jurnalis daerah tergiur dan menerima berita uncuy–sebuah akronim dari uang cuy, atau umum disebut ‘wartawan bodrek.’[1] Bagi jurnalis dengan status kerja kontrak atau lepas, sebagian menganggap praktik menerima amplop tidak bisa disederhanakan sebagai suap, melainkan memiliki dimensi teknik bertahan hidup, atau sering saya disebut dengan ‘duit coki-coki’.
Praktik semacam itu bukan hal tabu di kalangan jurnalis pada umumnya, secara khusus pada jurnalis yang beredar di kota tempat saya tinggal. Cara narasumber menyuap pun bisa berbeda-beda tergantung posisi jabatan dan kelas sosialnya. Bentuk suap yang sederhana biasanya dengan cara mentraktir kopi dan makan. Dengan pengaruh budaya ewuh-pekewuh alias tidak enakan karena sudah ditraktir, pemberitaan atas narasumber bisa diberitakan dengan frame yang ‘baik’.
Seorang kawan jurnalis pernah menceritakan pengalamannya kepada saya tentang bagaimana ia terjebak dalam situasi yang demikian.
Suatu hari Afwan (bukan nama sebenarnya) berangkat dari rumah pukul 8 pagi dengan mengendarai sepeda motornya. Tujuannya hari itu menyambangi beberapa kantor dinas pemerintahan daerah untuk meliput berita tentang isu dugaan solar bersubsidi untuk nelayan. Nasibnya kurang baik hari itu, hingga pukul 3 sore teleponnya tak kunjung berdering. Afwan di ping-pong oleh narasumbernya, semua kunjungan wawancaranya ditolak dengan berbagai alasan, semua rencana liputannya yang dirancang sedari malam kacau-balau. Situasinya makin sial, karena tabungan beritanya telah habis untuk berita weekend. Hari itu, bahkan Afwan merasa tak dapat memenuhi target berita hariannya.
Hari itu cuaca mendadak hujan. Dengan sigap Afwan menepikan motornya untuk berteduh. Pakaiannya setengah basah. Afwan mengambil sebatang rokok yang sudah lecek dan bengkok karena terpaan hujan di saku kemejanya. Sambil menghisap rokok, dirinya berpikir keras mencari orang yang bisa diwawancarai.
Sepintas, tiba-tiba ia mencoba mengingat beberapa nama, ia mengecek ulang semua kontak di handphone-nya, hingga berakhir di kontak bernama “Rustam KNT”. Rustam adalah ketua serikat nelayan tradisional yang baru dikenalnya pada acara konferensi yang dihadirinya minggu lalu. Doa Afwan di-ijabah, Rustam bisa ditemui untuk wawancara, dengan cepat Afwan membuat pertanyaan wawancara dadakan.
Saat asik merangkai pertanyaan liputan, notif pesan masuk ke Hp-nya, “Mas, nanti ketemuannya di Kaska aja ya, aku lagi pengen ngopi”. Di daerah saya, Kaska adalah resto dan cofeeshop yang harga secangkir kopi semurah-murahnya Rp 35.000 atau lebih mahal dari harga satu berita di media tempatnya bekerja. Afwan bingung, saat melihat isi dompetnya yang hanya tinggal selembar uang Rp 5.000 . Ia juga merasa tidak nyaman jika datang dengan pakaian lusuh setengah basah.
Mengingat hari itu ia belum sama sekali punya bahan untuk menulis berita, ia memaksakan harus berangkat menemui Rustam. Sebelum berangkat, Afwan menelepon temannya untuk meminjam baju dan uang Rp 50.000[sa1] . Beruntung Afwan memiliki teman yang baik hati sehingga masalahnya dibantu oleh temannya. Dengan baju kaos pinjaman dari temannya dan jeans yang masih sedikit baal (basah), serta uang Rp 55.000 ribu ia berangkat menemui Rustam hanya dengan cuci muka.
Sesampainya di lokasi, Afwan disambut baik oleh Rustam bersama teman-temannya yang hari itu ikut nongkrong. Teman-teman Rustam terheran dan bertanya melihat celana Afwan yang masih basah, “Kehujanan tadi dek? Nda bawa jas hujan ya?”. Afwan menjawab, “Ohh, ndak sempat ganti tadi Om. Soalnya cepat-cepat betul bah, aku ke sini”. Rustam menimpali jawaban Afwan sembari sedikit meledek, “Ishh kau ndak bilang tadi bah, Dek. Kalau tau kujemput naik mobil”.
Setengah waktu dari sesi wawancara Afwan belum memesan apa-apa, Rustam kemudian menanyakan, “Ndak pesan kah kau?” Afwan yang malu-malu hanya menjawab, “Nanti sajalah aku, Om.” Dengan nada sedikit sombong Rustam membalas, “Ambil saja lah, nanti aku yang bayar, kalau mau makan, pesan sekalian”. Afwan yang merasa hoki bergegas ke kasir untuk memesan es lemon tea dan nasi goreng.
Afwan merasa sangat senang hari itu, ibarat setali dua uang, dia dapat berita dan makan enak sekaligus. Sepulangnya di rumah, dirinya bergegas menyalakan laptop dan mulai mengetikkan berita. Tiga berita selesai rampung dikerjakannya selama tiga jam lebih. Pada berita terakhir Afwan memberi judul, “Nelayan Miskin Tak Sepenuhnya Merasakan Solar Subsidi”.
Bukan bermaksud untuk menggeneralisir, apa yang terjadi pada Afwan mungkin juga banyak dialami jurnalis lepas lainnya. Mengutip tulisan saya sebelumnya berjudul “Bagaimana Media Merundung Buruh” (Majalahsedane.org, 17 September 2023), pemberitaan adalah proses yang penuh dengan kontrol dan pendisiplinan dan kondisi kerja jurnalis juga tidak lebih baik dari apa yang dialami buruh di pabrik.
Apakah sepiring nasi goreng dan es lemon tea memengaruhi objektivitas Afwan dalam menulis berita? Bisa iya, bisa juga tidak. Namun siapa yang bisa menjamin independensi media massa jika upah yang dibayarkan kepada orang seperti Afwan saja tak mampu membuat tubuhnya mandiri. Industri media dan pemiliknya hanya berkoar tentang jargon kebebasan pers dan independensi pemberitaan, namun tidak dengan kesejahteraan para jurnalisnya.[]
[1] ‘Wartawan bodrek’ adalah istilah harian yang digunakan untuk seseorang jurnalis yang memonetisasi berita untuk kepentingan pribadi.