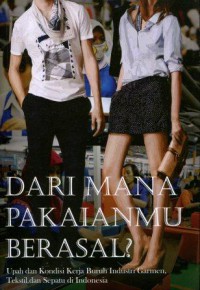Judul Buku: Berpencar, Bergerak!: Pergolakan Perlawanan Harian Buruh di Delapan Sektor Industri
Tahun Terbit: Mei 2024
Penerbit: Tanah Air Beta dan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane
Prolog: Hari Nugroho
Penutup: Jafar Suryomenggolo
Penulis: Ai Rusmiati, Sudiyanti, Jumiyem, Giyati, Ida Fitriyani, Yuni Fitriyanti, Zaenal Rusli, Vindra Whindalis, Corneles Musa Rumabur, Rahmat Jumaedi, Rojali.
Jum’at 28 Juni 2024, Pukul 10.30 siang, dari rumah kontrakan, saya memesan ojek online (Ojol) menuju Stasiun Tangerang. Hari itu saya hendak ke Bogor, untuk mengikuti diskusi buku “Berpencar Bergerak: Pergolakan Perlawanan Harian Buruh di Delapan Sektor Industri” yang diterbitkan oleh Penerbit Tanah Air Beta (TAB) dan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS). Buku ini merupakan seri ketiga dari buku ‘Buruh Menulis’.
Sebelumnya, TAB dan LIPS menerbitkan buku buruh menulis seri pertama tahun 2015 yang berjudul “Buruh menuliskan perlawanannya” dengan melibatkan limabelas orang buruh sebagai penulisnya. Setahun kemudian, pada 2016 seri kedua terbit bersama duabelas orang buruh yang menuliskan pengalamannya. Seri kedua tersebut diberi judul “Menolak Tunduk: Cerita Perlawanan dari Enam Kota”. Di seri kedua, saya adalah salah satu penulisnya.
Langit masih terang. Sekitar dua kilometer perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan deras. “Mbak, cari tempat berteduh dulu, ya,” ajak abang Ojol. “Iya Mas. Hujannya deras banget,” timpalku.
Kami berteduh di emperan ruko. Hujan masih mengguyur. “Saya mau Jum’atan. Jadi tidak bisa menunggu reda,” ucap pengemudi Ojol sembari menyerahkan jas hujan berbahan plastik tipis berwarna biru yang biasa dijual di mini market. “Mbak, pakai jas hujan ya,” tambahnya. Saya tidak sanggup menolak, meskipun hujan deras kami tetap jalan. Tidak mungkin menahan orang yang hendak beribadah.
Setiba di Stasiun Tangerang, pakaian saya basah kuyup. Jas hujan seharga sepuluhribu rupiah itu tak mampu melindungi pemakainya dari guyuran air langit.
Perjalanan Tangerang-Bogor menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) memakan waktu kurang lebih dua jam, dengan dua kali transit, di Stasiun Tanah Abang dan Manggarai.
Sekira pukul 13.15 WIB saya tiba di Stasiun Bogor. Penampilan saya sudah tidak karuan. Perjalanan yang cukup lama di KRL, tak membuat pakaian saya yang basah, mengering. Segera saya mencari kamar kecil untuk merapikan kembali penampilan, meskipun tetap dengan pakaian yang masih sedikit basah.
Di Stasiun Bogor, langit mulai gelap, pertanda akan hujan. Dengan kembali menggunakan Ojol, saya pun segera menuju ke lokasi acara, Café Malabar yang terletak Jl. Malabar No. 22, Bogor.
Sekitar duapuluh menit setibanya di Café Malabar, hujan kembali deras. Meja kursi yang sudah ditata panitia, terpaksa harus digeser agar tak terkena hujan. Beberapa panitia acara tampak khawatir apakah acara dapat berjalan dengan lancar. Selain hujan makin deras, narasumber tak kunjung tiba, sementara waktu acara sudah telat empatpuluh menit dari yang direncanakan pukul 14.00 siang.
Rupanya hujan hari itu merata hampir di semua wilayah.
Sembari menunggu hujan reda, berturut-turut notifikasi Whatsapp di handphone saya berbunyi, “Teh, saya kejebak hujan di fly over“ tulis salah satu narasumber yang menginfokan keterlambatannya. Begitu juga dengan salah satu peserta diskusi, mengabarkan hal yang sama, “Mbak, aku neduh dulu di belakang stasiun. Hujannya deras, aku nggak bawa mantel”.
Sembari menunggu, saya mulai merasa tidak nyaman dengan sepatu yang basah, saya pergi ke minimarket seribu umat di sekitar Café Malabar. Niatnya mau beli sandal jepit, namun harganya tiga kali lipat lebih mahal dari warung Madura. Padahal sandal yang dijual di minimarket dengan warung Madura tak ada bedanya. Hanya mereknya saja yang diganti dengan nama tokonya. Dari pada mengeluarkan uang Rp56 ribu untuk sendal jepit, akhirnya saya memutuskan membeli kaos kaki seharga Rp27 ribu. Beruntung ada sandal jepit ‘nganggur’ yang bisa dipakai ketika sepatuku sedang dikeringkan.
Lambat laun hujan mereda, menyisakan gerimis. Semua narasumber datang hampir bersamaan. Peserta diskusi pun satu per satu datang dan mengambil posisi duduk di kursi yang masih agak basah. Tampak pula beberapa panitia sibuk menyeting zoom, untuk peserta yang tersambung secara daring. Jumlah peserta yang datang kurang lebih 20 orang dari berbagai organisasi. Acara diskusi dimulai.
Acara dibuka oleh Reza, salah satu panitia diskusi dari LIPS. Dalam beberapa kalimat Reza mengantarkan maksud dan tujuan diskusi, lalu menyerahkan ke saya sebagai pemandu acara diskusi alias moderator.
Hari itu adalah kali pertama saya menjadi moderator dalam sebuah acara diskusi buku. Karena alasan saya salah satu alumni dari buruh menulis dan masih sering menulis di beberapa media alternatif, saya dipercayakan oleh kawan-kawan LIPS untuk menjadi moderator dalam acara diskusi buku tersebut.
Meskipun belum pernah punya pengalaman menjadi moderator, dengan rasa percaya diri saya pun menyanggupinya. Saya menganggap ini kesempatan saya untuk belajar.
Saya pun menyiapkan diri: membaca tuntas isi buku, membuat beberapa pertanyaan yang menyangkut isi buku, maupun pertanyaan di luar isi buku, yaitu pertanyaan tetang proses penulisan buku tersebut. Sebagai alumni buruh menulis, tentu saja saya punya bekal pertanyaan khusus tentang maksud dan tujuan dari penerbitan buku yang ditulis sepenuhnya oleh buruh.
Tiga dari sebelas orang penulis buku “Berpencar, Bergerak” yang hadir sore itu adalah Sudiyanti, Ai Rusmiati, dan Zaenal Rusli. Mereka semua buruh yang akan menjadi narasumber diskusi: memaparkan apa yang ditulis dan bagaimana proses mereka menuliskan pengalamannya.
Dalam buku “Berpencar, Bergerak”, Sudiyanti menuliskan pengalaman berlawannya di pabrik elektronik yang memproduksi earphone. Dengan sangat detail, Sudiyanti menjelaskan bagaimana ia bersama beberapa kawan yang tergabung dalam serikat buruh tingkat pabrik mengubah keluhan-keluhan buruh atas buruknya kondisi kerja yang dialami menjadi tuntutan ke perusahaan. Menuntut pergantian bahan kimia berbahaya, menuntut status buruh kontrak menjadi tetap, fasilitas yang memadai untuk buruh perempuan dan seterusnya. Kisah perjuangannya ia tumpahkan menjadi tulisan sebanyak 22 halaman dengan judul “Tidak Sejernih Suara dari Earphone” (hal. 83).
Di sektor garmen, Ai Rusmiati menceritakan hal yang sama. Ai Rusmiati adalah buruh perempuan yang bekerja di salah satu pabrik gramen yang memproduksi merek internasional. Pengalaman Ai Rusmiati yang dituangkan dalam tulisan berjudul “Mengorganisir Perlawanan” (hal. 231) ini memberikan pelajaran penting tentang kegigihan dan keberaniannya melawan kesewenangan perusahaan. Dengan segala keterbatasan dan pengetahuannya sebagai buruh, ia tak pernah lelah mengajak buruh lain untuk berserikat dan meorganisir perlawanan di dalam pabrik.
Cerita perlawanan dari buruh di sektor ritel dituliskan oleh Zaenal Rusli dengan judul “Bekerja dan Berutang: Perlawanan Buruh Alfamart” (hal 109). Di awal tulisannya, Rusli atau Uchie memperlihatkan dinamika kehidupan pemuda era 90an yang tinggal di tengah hiruk-pikuk kota industri, Jabodetabek. Siasat demi siasat yang dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan selalu disandingkan dengan cerita kehidupan jalanan sebagai pengamen. Bagi saya cerita Uchie ini menggambarkan kelas buruh di perkotaan. Nasibnya pun tak berubah ketika ia mendapatkan pekerjaan sebagai buruh ritel. Sistem manajemen ritel yang tak mau rugi membebankan segala risiko kerusakan dan kehilangan barang kepada buruh. Dengan berbagai mekanisme, buruh ritel dijebak utang yang tak ada habisnya. Lagi-lagi perlawanan buruh akan selalu muncul mengejutkan.
Selain cerita perlawanan buruh di sektor Elektronik, Garmen dan Ritel, buku ini juga menceritakan perlawanan buruh di sektor lain: Sektor Kesehatan (Rumah sakit), Pertambangan, Makanan dan Sektor Domestik – Pekerja Rumah Tangga (PRT).
***
Di luar isi buku, pemilihan judul “Berpencar, Bergerak” membuat saya penasaran. Di benak saya, ketika mendengar kata buruh, perlawanan atau perjuangan akan identik dengan kata “bersatu”. Itu yang saya pikirkan ketika menerima buku ini seminggu sebelumnya.
Untuk menghilangkan rasa penasaran, dalam kesempatan diskusi buku ini, saya bertanya tentang arti dan latar belakang pemilihan judul buku tersebut kepada Tim Editor.
Salah satu dari Tim Editor menjelaskan bahwa pemilihan judul dilatari oleh beragamnya organisasi dari peserta buruh yang menuliskan pengalamannya di buku ini. Meskipun mereka memiliki latar organisasi, bahkan ideologi yang berbeda-beda namun ketika di pabrik dan berhadapan dengan kesewenangan perusahaan, mereka bersikap sama: bergerak dan melawan.
“..[y]ang penting melawan dulu. Karena semua buruh pernah mempunyai pengalaman buruk ditindas, ketika serikatnya tunggal, mudah sekali dikontrol,” lanjutnya menegaskan pentingnya perlawanan bagi kelas buruh.
“Nggak apa-apa serikatnya macem-macem, yang penting ketika mereka tetap memperjuangkan anggota, mereka berada di barisan paling depan, bukan membelakangi anggota, tegasnya.
***
Pertanyaan berbeda saya tujukan kepada tiga penulis yang menjadi narasumber diskusi. Pertanyaan saya pertama bagaimana perasaan penulis setelah buku ini terbit? Jawaban para penulis sama, mereka merasa senang dan bangga. Mereka pun berharap pengalamannya yang dituliskan dalam buku ini dapat menginspirasi pembaca, terutama kawan-kawan buruh.
“Buku ini mengingatkan saya di saat-saat melakukan perjuangan yang tidak mudah dilalui. Alhamdulilah dari perjuangan sebagaimana yang saya tuliskan di buku tersebut, akhirnya kami sedikit demi sedikit kami meraih kemenangan, walaupun harus dilalui dengan berbagai kesulitan,” terang Sudiyanti sambil terisak mengingat kembali masa-masa sulitnya.
Para penulis juga menyampaikan kesulitannya di saat proses penulisan. Faktor pertama adalah soal waktu dan alat kerja. Jam kerja yang panjang di pabrik membuat para penulis harus bisa curi-curi waktu istirahatnya untuk menulis, baik di tempat kerja atau di rumah. Untuk mengatasi keterbatasan alat, sebagian besar penulis menuliskan ceritanya dengan tulisan tangan di sebuah buku lalu dikirim ke pendamping.
“Setiap penulis ada pendampingnya. Awalnya kami dibebaskan menulis cerita, setelah kami menuliskan beberapa cerita di buku, pendamping akan banyak bertanya kepada kami dan dari pertanyaan itu kami jadi tau apa yang harus kami tuliskan,” ucap Zaenal Rusli ketika menjelaskan proses ia menulis.
Kesan setelah membaca buku “Berpencar, Bergerak”
Membaca cerita pertama buku ini, buruh pertambangan yang ditulis oleh Corneles Musa Rumambar yang diberi judul “Moker Underground: Perlawanan Buruh PT Freeport Indonesia,” mengingatkan saya pada cerita petualangan lima sekawan. Buku favorit saya waktu Sekolah Dasar (SD).
Echy –biasa saya memanggil– dalam tulisannya menggambarkan dengan baik kondisi lingkungan kerja di bawah tanah: “Pertama kali saya memasuki area penambangan terasa gelap, sepi dan pengap. Tidak terdengar suara apapun dari luar. Saya membuang pandangan ke kiri,kanan, atas dan bawah, hanya bebatuan yang membisu,” (hal. 6). Kalimat yang ditulis Echy sungguh membuat saya serasa berada di cerita itu, yang merasakan kegelapan, pengap dan dinginnya berada di area tambang bawah tanah.
Kisah hidup Jumiyem yang merupakan Pekerja Rumah Tangga (PRT), ketika menjadi tulisan seakan membawa saya pada film-film yang diproduksi stasiun televisi berlogo ikan terbang dalam versi nyata. Form zero to hero layak saya sematkan kepada penulisnya. Tulisan Jumiyem menggambarkan dengan apik seorang perempuan yang berasal dari desa yang gersang, dengan kondisi ekonomi seperti kebanyakan kemudian pergi ke kota untuk bekerja dengan berbekal ijazah SD. Dari tulisan itu Jumiyem bertransformasi menjadi perempuan pemberani, berpendidikan tinggi, bahkan berani bertarung menjadi anggota legislatif. Kemajuan intelektual Jumiem karena kondisi dan demi perjuangan mengangkat derajat kawan-kawannya sesama pekerja rumah tangga.
“Tak sejernih suara earphone” tulisan Sudiyanti buruh di sektor Elektronik, berhasil mempengaruhi saya membenci HRD cabul dan organisasi “Forum” yang melakukan pungli terhadap buruh-buruh yang bekerja di sekitar wilayahnya.
Begitu juga dengan tulisan Zaenal Rusli “Bekerja dan berutang: perlawanan buruh Alfamart”. Dari tulisan ini saya jadi tahu bagaimana buruh Alfamart yang niatnya bekerja agar mendapat penghasilan, justru malah terjebak utang yang tidak pernah mereka rasakan uangnya.
Dari tulisan Rusli saya berpikir bahwa orang-orang yang suka mencuri di Alfamart dan toko lainnya mungkin mereka jahat. Tapi bagi saya, lebih jahat lagi Chairul Tanjung sebagai pemilik ritel tersebut. Seorang konglomerat yang mendapat kekayaan dari tetesan keringat buruh-buruh Alfamart, tetapi masih merampok uang buruh dengan dalih utang. Kalaupun ada selisih barang kenapa tidak membuat sistem pengamanan yang lebih canggih, bukan malah membebankan buruhnya dengan kebijakan pemotongan upah.
Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak kawan-kawan pembaca membacakan Alfatihah untuk Vindra Whindalis, salah seorang penulis buku ini yang sudah meninggalkan kita semua di tahun 2021. Warisan tulisan Vindra mengenai kebobrokan rumah sakit, cocok dengan judul tulisannya “Korupsi berjamaah dan pembangunan serikat buruh di Rumah Sakit”. Tulisan Vindra membongkar bobroknya manajemen rumah sakit di tempat Vindra bekerja, tidak ada empati kepada pasien, yang ada malah mengambil uang dari pasien-pasien BPJS.
Setelah buku ini terbit, apa yang harus dilakukan?
Pertanyaan di atas disampaikan oleh Cristian salah seorang peserta diskusi dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI). Dua penulis yang statusnya masih bekerja menjawab, bahwa mereka masih tetap akan berjuang. “Tulisan di buku itu ditulis pada tahun 2018. Diterbitkan tahun 2024, kondisinya masih sama, belum ada perubahan yang signifikan, makanya saya masih harus berjuang,” ucap Sudiyanti menjawab pertanyaan dari Cristian.
Bagi saya, sebagai alumni buruh menulis, saya jadi mendapatkan keterampilan baru dalam melawan. Yaitu dengan menulis. Artinya, keterampilan menulis saya menambah pengetahuan saya tentang cara melawan. Selain aksi protes, menulis juga dapat digunakan sebagai cara melawan. Dengan begitu meskipun saya tidak lagi dalam organisasi serikat dan tidak lagi bekerja di pabrik, tapi saya masih bisa berkontribusi terhadap gerakan buruh.
Kemampuan menulis membuat saya dapat menyuarakan keluhan harian buruh di balik tembok pabrik. Bagi saya, cerita-cerita harian buruh harus diketahui banyak orang. Dengan menulis saya juga dapat menceritakan di balik ngetred-nya pakaian kekinian yang diproduksi H&M dan merek internasional yang ternyata ada buruh dipersulit ke toilet ketika bekerja. Sebagaimana yang diceritakan oleh Rojali di buku ini.
Dari tulisan Sudiyanti juga mengandung pesan protes yang kuat terhadap perusahaan bernama Samsung. Secara tak langsung Sudiyanti ingin mengatakan bahwa Samsung harus bertanggung jawab atas penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat berdampak kesehatan buruh, maraknya pungli rekrutmen, bahkan pelecehan terhadap buruh perempuan ketika melamar kerja di pabrik pemasok earphone bermerek Samsung.
Begitupun dengan Alfamart yang menindas buruh dengan kebijakan potongan upah atau utang, apabila ada seilisih barang. Seperti yang dialami Andi (bukan nama sebenarnya) ketika diputus kontrak ada utang yang harus dibayar sebesar Rp15.000.000.
Bagi yang bangga memakai sepatu Adidas, ketahuilah bahwa ada 1300 buruh perempuan yang berjuang sampai enam tahun. Mereka dipecat karena menuntut hak, karena mendirikan serikat.
Dengan menulis buruh dapat menyuarakan keluhan dan tuntutannya sendiri. Sebab media nasional saat ini sudah dikuasai penguasa. Sehingga, cerita perlawanan buruh sulit dipublikasi oleh media-media besar. Kalaupun ada yang menuliskan tentang buruh, tidak berimbang. Karena yang diberitakan media-media penguasa lebih banyak menyudutkan buruh: Buruh aksi menyisakan sampah, bikin macet saat aksi, Buruh tuntut kenaikan upah dengan mengendarai motor ninja, aksi buruh mengganggu ketertiban dan seterusnya.
Secara pribadi, menulis adalah bagian dari terapi untuk menyalurkan kemarahan saya atas kondisi yang saya dan kawan-kawan buruh PT Panarub Dwikarya alami. Lewat tulisan saya ingin mengabarkan bahwa untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, sangat sulit.
***
Setelah tiga seri buruh menulis diterbitkan, setidaknya sudah ada 34 orang buruh yang berani bersuara dengan tulisan. Mereka menuliskan ketidakadilan yang dilakukan perusahaan bahkan negara. Semoga keberanian bersuara dari buruh menulis dapat memantik buruh-buruh lainnya untuk berani bersuara dengan menuliskan ketidakadilan yang dialami. Tentu saja dari perspektif buruh itu sendiri dan dengan gaya menulis buruh. Mengutip salah satu tim editor dalam diskusi buku tersebut, “Buruh adalah subjek. Buruh bukan objek penelitian kaum intelektual.” Seperti judul di Pengantar Editor buku ini, Menulislah, Sebelum Dituliskan.
Sebagai penutup saya ingin mengutip kembali kalimat ‘sakti’ yang disampaikan Juan Lee, salah satu peserta diskusi. “Buku ini karya yang penting dalam gerakan. Tulisan di buku ini ditulis dengan bahasa yang lugas, jelas, dapat dipahami dan tidak penuh dengan jargon yang tidak perlu. Buku ini adalah salah satu bukti, bahwa buruh itu adalah intelektual termaju.”[]