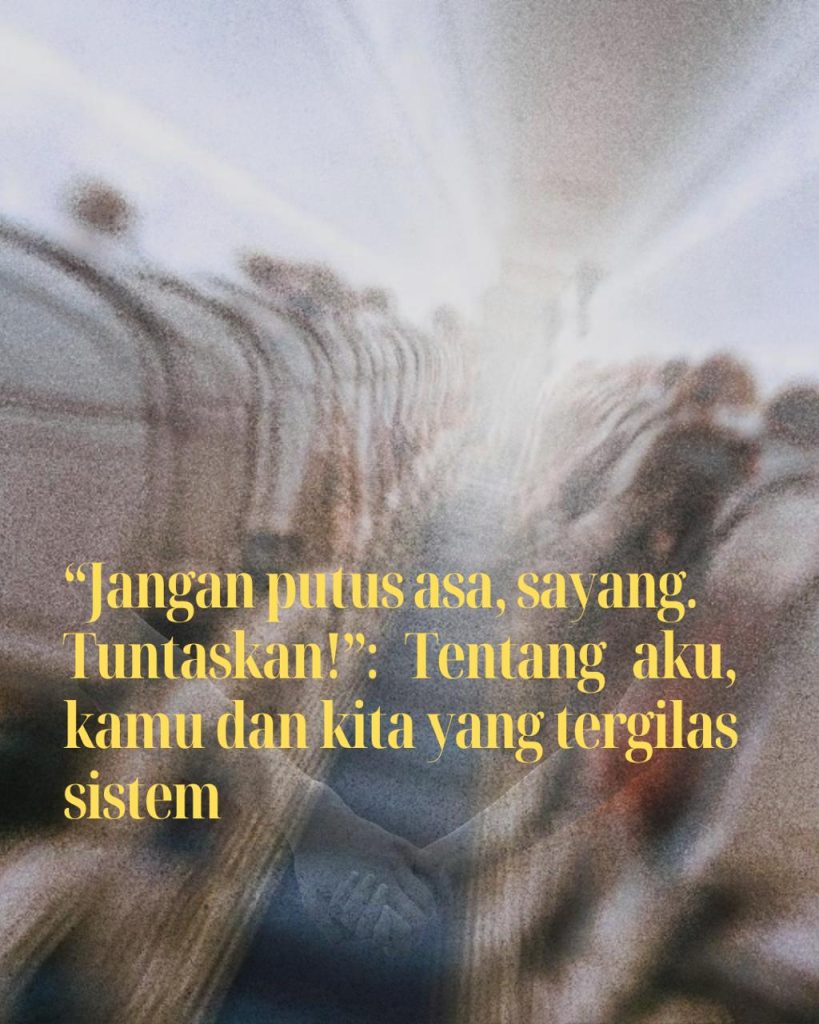“Mas ini suratnya silahkan dibaca, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan,” ujar perempuan berambut ikal berkulit putih dengan jabatan Vice President Cabin Crew. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kami juga tahu keputusan ini sangat berat. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena direksi sudah memutuskan,”lanjutnya.
“Saya menolak PHK ini, ” ujarku singkat setelah membaca sekilas surat tersebut. Marah, bingung, sedih campur aduk perasaanku. Sepanjang jalan menuju tempat parkir aku masih belum bisa berpikir jernih. Jarum speedometer kendaraan yang aku kemudikan hanya bergerak di angka 40 sampai 60. Dari masuk tol, posisiku mobilku terus berada di jalur kiri. Biasanya aku selalu ingin cepat sampai rumah, kali ini aku berharap waktu tidak berputar.
Terbayang wajah polos kedua anak dan istriku. “Bagaimana aku bisa menjelaskan pada mereka bahwa ayah tak lagi punya pekerjaan?” “Bagaimana aku akan membayar cicilan rumah, cicilan mobil yang menggunung?” Rasa takut terasa begitu mencekik. “Bagaimana aku bisa menghidupi mereka?” “Apa yang akan terjadi pada keluargaku, besok?” Isi kepalaku ramai dengan beragam pertanyaan ketakutan dan kekhawatiran.
Aku tidak berani pulang ke rumah, aku tidak tahu harus kemana. Akhirnya aku berhenti sejenak di pinggir tol. Aku harus memikirkan bagaimana caranya agar orang tua dan mertuaku tidak mengetahui bahwa aku dipecat dan aku bukan lagi seorang awak kabin.
Pukulan itu telak. Aku yakin bukan hanya untukku. Tapi juga untuk istri dan anak-anakku. Yang paling berat adalah, bagaimana aku akan menceritakan ini pada orang tua dan mertua. Orang tuaku yang selalu bangga dengan pekerjaanku, mertua yang selalu percaya padaku. “Apakah mereka akan kecewa?” “Apakah mereka akan menganggapku gagal?” Rasa malu itu menghimpit. Membuatku sulit bernapas. Beberapa kali handphone-ku berbunyi tapi aku biarkan. Aku tahu itu telepon dari rumah menanyakan kabarku. Biasanya chat dan telepon dari rumah selalu aku tunggu. Kali ini entah kenapa terasa seperti pisau yang mengiris-iris hati.
Namaku Nathan (bukan nama sebenarnya). Hampir 10 tahun aku bekerja sebagai awak kabin di salah satu maskapai penerbangan yang terkenal sebagai maskapai LCC (low-cost carrier) atau maskapai penerbangan berbiaya hemat. Istriku juga awak kabin di maskapai yang sama. Aku memiliki dua orang putri berusia lima tahun dan dua tahun. Selain sebagai buruh, aku juga mengabdikan diri pada gerakan buruh di sektor awak kabin.
Bersama beberapa kawan, kami mendirikan serikat khusus awak kabin. Aku ingat betul, bagaimana menggebunya semangat kami saat ingin membesarkan serikat. Bagaimana kami berteriak menuntut keadilan. Rasanya tak ada yang bisa menghentikan kami. Keringat menghiasi argumen setiap debat sengit di ruang rapat. Semua demi satu keyakinan hak-hak buruh awak kabin harus direbut dan diperjuangkan.
Namun, dunia ini punya caranya sendiri untuk menghancurkan mimpi. Pagi itu Selasa 26 Maret 2024, melalui selembar surat, di ruangan yang dingin namun tidak mampu mengusir keringat yang membanjiri badanku. Dengan basa basi namun tanpa empati dan tanpa ampun, PHK sepihak menjadi keputusan dewan direksi.
Seketika, duniaku runtuh. Bukan hanya pekerjaanku yang hilang, tapi juga identitasku, organisasiku sebagai wadah perjuanganku. Serikat yang kubangun bersama kawan kawan awak kabin dengan tetesan keringat, kini tak lagi bisa menjadi rumahku. Aku terlempar sendirian di tengah badai.
Sejak sekolah aku suka berorganisasi, karang taruna salah satunya. Ketika bekerja, serikat buruh adalah organisasi yang aku ikuti. Tahun 2021 aku diajak menjadi pengurus salah satu partai elektoral. Setahun kemudian, pada 2022, aku dipercaya untuk menjadi calon legislatif daerah kabupaten.
Banyak yang mempertanyakan kenapa aku mau terlibat dalam partai politik dan jadi caleg. Awalnya karena aku pikir partai politik dan menjadi caleg adalah salah satu jalan perjuangan. Aku kira sama dengan serikat buruh. Jujur awalnya tidak terpikir nyaleg, hanya saja partai tempatku bernaung lolos verifikasi Pemilu. Semua pengurus disuruh untuk nyaleg. Awalnya aku sempat menolak tapi akhirnya aku terima. Aku berfikir, mudah-mudahan bisa jadi contoh bagi pengurus yang lain agar mereka berani jadi caleg.
Sebenarnya aku masuk partai karena mau belajar organisasi politik. Dulu aku pernah berucap kalau perjuangan dan impian organisasi terakhirku adalah di partai politik.
Namun, niat tulusku untuk berjuang di jalur legislatif harus kubayar mahal: kehilangan pekerjaan kebangganku dan keluarga adalah harga yang harus kubayar.
Maskapai tempatku bekerja katanya adalah anak dari BUMN, sehingga aturan pun mengikuti aturan induk. Salah satu aturan adalah Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No S-560/S.MBU/10/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Group Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Parat Politik atau Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dari surat edaran BUMN itulah maskapai tempatku bekerja mengeluarkan surat edaran mengenai larangan keterlibatan pegawai dalam partai politik. Kebijakan itu juga tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), di mana aku menjadi salah satu tim perunding. Sialnya, manajemen menjadikan pasal tersebut sebagai dasar pemecatan terhadapku.
Aku jelas menolak pemecatan tersebut. Selain karena aku harus mempertahankan pekerjaan yang susah payah aku dapatkan, aku merasa diperlakukan tidak adil. Aku ingat betul ketika aku meminta izin secara lisan kepada atasanku. “Selamat ya mas, semoga berhasil. Orang baik pasti ada jalan,” kalimat yang keluar dari atasanku ketika aku sampaikan pencalonan. Kalimat yang di kemudian hari dia sangkal sendiri dengan dalih ‘dikira hanya candaan semata’.
Banyak yang menyalahkan aku dan membenarkan pemecatan itu, termasuk teman-teman perjuanganku. Mereka bilang, “Nathan salah sendiri, melanggar PKB.” Aku merasa di titik terendah. Aku merasa sendiri.
Berhari-hari aku diam. Aku belum punya keberanian untuk menyampaikan kabar pemecatanku. Setiap hari aku keluar rumah, kepalaku terus berpikir keras bagaimana aku menyampaikan kabar buruk ini kepada istri dan dua orang putri cantikku. Anak-anakku yang polos, masih kuingat protes mereka, “Ayah kerja terus sampai malam, cuma ngobrol sama oom dan tante dan selalu pulang malam, ga mikirin aku,” ucap si sulung suatu hari ketika aku pulang malam. Setelah pemecatan itu, mereka mungkin bingung karena ayahnya setiap hari di rumah, melihat wajah ayah yang sering murung, tanpa seragam kebanggaan yang dulu kukenakan.
Aku tak tahu bagaimana harus menghadapi esok, ketika semua mata akan melihatku bukan lagi sebagai pramugara yang membanggakan. Melainkan sebagai seorang yang telah kehilangan segalanya. Bukan tidak mungkin banyak yang beranggapan dan menyalahkan bahwa kegiatanku dan aktivitasku di gerakan buruh bandara yang merusak semua impian keluargaku.
Yang paling menyakitkan adalah membayangkan wajah orang tuaku, wajah kakakku, wajah adik-adikku. Kebanggaan yang dulu begitu nyata, “Apakah akan berubah menjadi rasa malu?” Aku telah mengangkat mereka dari lubang kesusahan, memberikan mereka martabat, namun kini, dengan surat pemecatan aku menarik mereka kembali ke titik awal. Betapa menyedihkannya, ketika kebahagiaan dan kebanggaan sebuah keluarga menjadi begitu rapuh, bergantung pada sehelai seragam dan sebuah pekerjaan yang kini telah sirna.
Dulu, kami hidup di bayang-bayang pemiskinan. Rumah kecil yang kami kontrak bulanan. Aku ingat setiap waktunya membayar sewa kami harus berdebat dengan pemilik rumah meminta waktu untuk mencari uang terlebih dahulu untuk membayar.
Bertahun tahun kami hidup seperti itu. Aku melihat bagaimana kedua orang tuaku berjuang mati-matian, membanting tulang, hanya untuk menyambung hidup. Ayahku awalnya supir angkot metromini jurusan tanah abang-slipi, lalu beralih menjadi sales besi baja ringan. Dengan menjadi sales kondisi ekonomi keluarga kami lumayan membaik. Namun urusan rumah masih harus ngontrak. Rasa sedih selalu menghantuiku. Aku membayangkan jika memiliki gaji yang baik aku akan mengubah kondisi yang menyakitkan ini.
Keajaiban itu datang. Aku diterima menjadi pramugara. Aku tidak menyangka akan diterima. Aku yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas, bisa bersaing dengan ratusan orang yang mempunyai latar pendidikan tinggi. Awalnya aku ragu ketika salah seorang teman sekolahku yang lebih dulu lulus memberi info lowongan kerja di maskapai penerbangan tempatnya bekerja. “Aku bisa gak yah,” kataku ragu. “Coba aja dulu, gak ada salahnya mencoba,” yakin temanku.
Pramugara profesi yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam mimpi. Ketika seragam itu membalut tubuhku untuk pertama kalinya, aku tahu ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini adalah tiket untuk menaikan martabat keluarga kami.
Perlahan tapi pasti, pandangan tetangga mulai berubah. Senyum mereka lebih ramah, sapaan mereka lebih hangat. Aku bisa melihat kekaguman di mata mereka saat aku melangkah keluar rumah dengan seragam rapi, koper di tangan. Orang tuaku, yang tadinya menunduk, kini bisa berjalan tegap. Mereka sering bercerita padaku dengan bangga, “Nak, tetangga sebelah memuji-muji kamu,” atau “Pak RT bilang kamu anak hebat”. Perubahan itu terasa manis, seperti hujan setelah kemarau panjang.
Di keluarga besar, orang tuaku menjadi sorotan. Setiap kumpul keluarga, merekalah yang paling banyak ditanya, paling banyak dipuji. “Wah, anakmu sukses besar ya, sekarang jadi pramugara.” Kalimat itu selalu terucap dengan nada penuh kekaguman. Air mata haru sering kulihat di mata ibu dan senyum tipis di bibir ayah. Sebuah kebanggaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.
Kakak dan Adik-adikku juga ikut merasakan kebanggaan itu. Teman-teman mereka seringkali kagum, “Kakakmu pramugara ya? Keren banget!” Aku melihat mata mereka berbinar kebanggaan di mata adik-adikku. Kebanggaan yang dulu tak pernah bisa kuberikan pada mereka. Rasanya begitu membahagiakan bisa membiayai sekolah adik-adikku, menjadi tulang punggung keluargaku, menaikan martabat keluarga. Jerih payahku bisa membuat tersenyum dan menjadi kebanggaan mereka.
Kini, semua itu terasa begitu pahit. Seragam itu telah lepas dari tubuhku. Gelar “pramugara” yang dulu kubanggakan, kini hanya menjadi kenangan. “Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada tetangga yang dulu memandang kami dengan hormat?” “Bagaimana aku bisa menghadapi tatapan kecewa dari keluarga besar yang dulu memujiku setinggi langit?” “Bagaimana aku harus berhadapan dengan mertua, untuk menjelaskan kondisiku sekarang ini?”
Setelah beberapa hari di jalanan tidak punya tujuan jelas, hanya menghabiskan waktu seharian akhirnya aku beranikan diri berterus terang kepada istri. Malam itu aku ceritakan semua. Aku hanya berani menceritakan kejadian ini kepada istriku “Sayang aku mohon jangan ceritakan keadaan ini ke siapapun sampai keadaannya benar benar siap,” ujarku diakhir cerita. Tidak ada yang terucap dari perempuan yang sudah tujuh tahun aku nikahi. Mata indahnya kulihat berkaca-kaca. Aku tahu dia butuh waktu untuk mencerna semua kejadian ini.
Kemudian rumah kami terasa semakin sunyi, dingin. Bukan karena kurangnya suara, tapi karena tercekik oleh beban pikiran. Cicilan rumah yang dulu bisa kubayar tepat waktu, kini menjadi hantu yang menghantui setiap sudut. Aku terpaksa memutar otak, mencari pinjaman sana-sini, merasakan pahitnya merendahkan harga diri demi secercah harapan. Saat anakku minta mainan baru atau menginginkan buku cerita, dadaku sesak. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku tak punya uang, sementara selama ini aku selalu mengajarkan mereka tentang keadilan dan hak terutama kepada istriku. Tapi sekarang aku tak mampu memberikan hak mereka.
Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tak akan kulepas, perjuanganku. Meskipun tak lagi bersama serikatku, semangat itu tetap menyala. Aku akan berjuang, itu tekadku. Kebetulan organisasiku bergabung dengan federasi. Di federasi itu aku mencoba mencari pijakan baru. Wadah baru untuk menyuarakan ketidakadilan. Bagiku ini bukan lagi tentang diriku, tapi tentang mereka yang senasib, mereka yang tergilas oleh sistem.
Aku mendengar selain aku yang dipecat karena menjadi caleg, ada beberapa orang yang akhirnya mengundurkan diri karena keterlibatan di partai politik. Aku berpikir ini tidak boleh terus dibiarkan. Perusahaan tidak boleh membungkam hak demokrasi buruhnya apapun alasannya. Apalagi setelah aku dan kawan-kawan pelajari, maskapai penerbangan tempatku bekerja bukan BUMN tapi anaknya.
Menerima situasi ini adalah perjuangan terberat. Aku tahu resiko yang akan aku hadapi. “Jangan putus asa, sayang. Perjuanganmu sudah setengah jalan di gerakan buruh bandara. Kamu harus teruskan sampai tuntas.” Kalimat menyejukan yang keluar dari perempuan berhati lembut, perempuan yang aku nikahi sejak 2019. Dia yang tidak pernah terlibat dalam gerakan. Dia yang menghabiskan waktunya untuk terbang dan mengurus anak-anak tetapi dia yang paling paham apa yang disebut dengan PERJUANGAN.
Restu istri, dukungan dari kawan-kawan di federasi dan beberapa beberapa awak kabin yang dulu berjuang bersamaku, mereka tidak lupa denganku masih menghubungiku. Mereka tahu bagaimana rasanya tergilas. “Jangan menyerah!” Pesan singkat itu sering mampir. “Kami tahu perjuangan tidak akan sia-sia, lu udah meninggalkan legacy tetap kuat!” Kata-kata itu, meski sederhana, tapi menjadi pengingat bahwa di luar sana, masih ada orang-orang yang berharap pada perjuanganku. Mereka adalah wajah-wajah yang kukenal, yang dalam setiap senyum kami, ada mimpi besar. Kini mereka menjadi penopang, di saat aku hampir tumbang.
Dukungan mereka yang membuatku berani menolak tawaran uang ratusan juta, dan tawaran jabatan yang menggiurkan tapi dengan syarat aku meninggalkan serikat. Menghadapi sendiri tanpa pengacara gugatan pihak perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial menjadi kesepakatan di Federasi. Buatku dan organisasi, kasusku adalah pembelajaran yang sangat berharga. Aku bersyukur walaupun organisasi kami baru, tetapi untuk kasusku banyak kawan yang membantu. Kami terhubung dengan banyak jaringan, banyak yang bersolidaritas dalam berbagai bentuk.
Selain melayani gugatan dari pihak perusahaan di jalur litigasi atau proses penyelesaian kasus/sengketa melalui jalur pengadilan, kami juga melakukan upaya pengadvokasian melalui jalur nonligitasi (penyelesaian kasus di luar pengadilan seperti kampanye, aksi, negosiasi, dll).
Selain mempersiapkan dokumen untuk sidang, mendatangi Komnas HAM, DPRD, kampanye media sosial adalah langkah-langkah yang aku dan organisasiku lakukan. Ini bukan hal yang mudah. Aku harus bolak-balik mendatangi kantor-kantor itu. Juga, harus belajar keras cara membuat jawaban gugatan, mempersiapkan bukti dan saksi-saksi.
Walaupun tekadku kuat tapi ada hari-hari ketika aku merasa begitu rapuh, begitu lelah, terutama ketika harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa instansi pemerintah, wakil rakyat tidak serta merta memiliki keberpihakan dengan persoalan buruh. Ngurus kasus di tengah persoalan ekonomi yang belum ada solusi membuatku merasa tertekan. Bagaimana bisa seseorang menerima nasib seberat ini begitu banyak ketidakpastian? Aku sering bertanya pada diriku sendiri, “Apakah ini semua sepadan?” “Apakah pengorbanan ini akan benar-benar menghasilkan perubahan?”
Setiap senyum palsu yang kuberikan pada keluargaku, kepada serikatku, kepada kawan kawanku. Senyum yang kuharap bisa menyampaikan “Hai kawan, semua baik-baik saja”. Aku tidak mau melihat kawan-kawanku menjadi sedih. Aku tidak mau melihat keluargaku menjadi terpukul. Aku tidak mau melihat anggota serikat menjadi kehilangan semangat. Aku tidak mau melihat kawan-kawan seperjuanganku menjadi kehilangan harapan. Aku tidak mau melihat istri dan anak anakku putus asa. Aku tidak mau melihat mereka semua berhati pilu. Itulah sebabnya aku hanya selalu berkata, “Semua baik-baik saja.” Terasa seperti kebohongan besar yang menyesakkan dada.
Perjuangan ini bukan hanya melawan perusahaan atau kebijakan. Perjuangan terbesar itu ada dalam diriku, melawan keputusasaan, melawan rasa bersalah, dan melawan ketakutan akan bayangan masa depan yang semakin buram.
“Aku adalah seorang pejuang!” Demikian selalu aku teguhkan dalam hati. Walau dalam kenyataannya aku sudah tidak sanggup berjuang. Aku baru mengetahui bahwa pejuang bisa terluka. Aku seorang ayah yang harus tetap bisa berdiri tegak demi istri dan anak-anakku. Aku juga seorang anak yang mencoba tegar di hadapan orang tuaku dan mertuaku, meskipun hatiku sangat hancur.
Perjuanganku itu aku sadari sekarang. Bukan sekadar soal anggota serikat, bukan hanya tentang menuntut hak-hak buruh di sektor bandara. Lebih dari itu, ini adalah tentang keluarga. Setiap teriakan “Hidup buruh!”, “Hidup awak kabin!” yang dulu lantang dikumandangkan, kini bergema pilu. Semua ini menyadarkanku bahwa di balik perjuangan besar , ada harga yang harus dibayar mahal oleh orang-orang tercinta di rumah.
Aku berjuang untuk ratusan awak kabin yang bahkan di antara mereka aku tak tahu nama dan wajahnya. Tapi pada saat yang sama, aku gagal melindungi “serikat” terkecil dan paling penting dalam hidupku. Kami harus merelakan rumah impian kami terjual karena tidak mampu membayar cicilan. Tidak ada keluhan dari bidadari-bidadariku ketika kami akhirnya harus numpang di rumah mertua, yang tentunya berbeda dengan rumah kami sendiri.
Aku, yang dengan gagah berani berjuang untuk kesejahteraan anggota serikat, tak pernah menyangka bahwa keluargaku sendiri yang akan menjadi korban terbesar dari idealisme itu. Istriku, dengan senyum tipisnya, selalu berusaha menyemangatiku, meskipun aku tahu dia menahan kecemasan yang luar biasa.
Suatu malam ketika aku tenggelam dalam lamunan, dia mendekatiku, “Jangan pedulikan kondisi keuangan. Biarkan aku yang mengambil tanggung jawabnya, asalkan kamu tetap fokus saja berjuang untuk pekerja bandara,” lirihnya dengan mata berkaca-kaca. Dadaku sesak mendengar kalimat itu. Dia tahu, dia sangat tahu bagaimana kondisi keuangan kami. Dia juga tahu betapa menakutkannya cicilan kami.
Sebuah janji yang begitu besar, begitu tulus, keluar dari bibir perempuan yang paling kucintai. Dia bersumpah akan menjaga kondisi keuangan keluarga dengan sekuat tenaga, seolah-olah beban itu ringan. Bagaimana mungkin aku bisa menanggung ini. Dia rela memikul beban berat, mengorbankan segalanya, demi perjuangan yang mungkin tak akan pernah memberinya apa-apa secara materi. Air mataku menetes, bukan hanya karena haru, tapi juga karena rasa bersalah yang menusuk.
“Jangan berhenti, kawan!” Semangat yang aku dapat dari kawan-kawan Federasi. Suara mereka selalu menggelegar di sekretariat, atau di sela-sela pertemuan federasi yang melelahkan. “Perjuangan ini lebih besar dari satu orang. Kamu sudah mengukir jejak!” Kata-kata penyemangat itu meskipun sering terasa hampa di tengah kekusutan batinku, tetap aku pegang erat. Mereka percaya padaku, pada perjuangan ini, bahkan ketika aku sendiri mulai meragukannya.
Di tengah ketegaran dan kegalauanku, tebersit untuk mencari pekerjaan. Berbekal jaringan pertemananku yang lumayan luas, aku coba kontak kawan-kawan. Beberapa membuahkan hasil. Ada tawaran menjadi pramugara lagi, bantu kawan di kantor pengacara dll. Setiap tawaran pekerjaan yang datang, bagaikan angin sejuk yang sesaat membelai, namun juga membawa dilema yang menyesakkan. Bukan hanya soal diriku lagi, melainkan tentang janji yang telah terucap, tentang api perjuangan yang tak boleh padam. Setiap kali ada panggilan wawancara atau tawaran posisi, aku tak pernah mengambil keputusan sendiri. Aku selalu melayangkan pertanyaan ini kepada orang-orang terdekatku, orang-orang yang memahami denyut nadiku sebagai aktivis.
Yang pertama kuberi tahu adalah istriku. Dia yang paling merasakan pahitnya pengorbanan ini. Dia yang paling berhak memberikan pandangan. Kuceritakan detail pekerjaannya, gaji yang ditawarkan, kondisi kerja. Kutatap matanya dalam-dalam, mencari secercah persetujuan. Namun yang kudapati seringnya adalah sorot mata lelah yang dipaksakan untuk tegar. Dia selalu berkata, “Pikirkan baik-baik, Yang. Apa ini akan membuatmu bahagia? Dan yang terpenting, apakah ini akan mencederai perjuanganmu?” Suaranya pelan, namun setiap kata mengandung beban berat yang ia pikul sendirian.
Selain istriku, kawan-kawan di federasi juga aku minta pertimbangan “Bagaimana menurut lu? Apakah pekerjaan ini bisa menjadi jembatan untuk perjuangan, atau malah akan menjadi belenggu?” ujar Andi (bukan nama sebenarnya) pengemudi di organisasiku yang punya perspektif luas. Aku mendengarkan nasihatnya dengan seksama, mencerna setiap kata, mencoba menimbang antara kebutuhan pribadi dan idealisme gerakan. Andi bagaikan kompas moral bagiku, penentu arah agar aku tak tersesat dalam godaan materi.
Tak lupa, aku juga berdiskusi dengan beberapa kawan seperjuangan seperti Indra dan Rizal (juga bukan nama sebenarnya ) mereka berdua sudah lebih dulu menjadi korban pemecatan pada saat pandemic Covid-19. Mereka adalah rekan-rekan yang memahami pahitnya dipecat, getirnya hidup tanpa kepastian, namun tetap teguh memegang panji-panji perjuangan. “Menurut kalian, apakah aku harus mengambil pekerjaan ini? Atau ini hanya akan menjadi pengkhianatan terhadap semua yang sudah kita bangun?” Pertanyaan itu selalu keluar dari bibirku dengan nada getir. Aku mencari kejujuran dari mereka, bahkan jika kejujuran itu berarti menampar kenyataan bahwa aku mungkin harus terus menahan diri dari kenyamanan demi prinsip.
Setiap masukan, setiap saran yang mereka berikan, terasa seperti bilah pisau yang mengiris-iris. Di satu sisi, ada desakan naluri untuk menstabilkan kembali keuangan keluarga, untuk melihat senyum lepas di wajah istri dan anak-anakku, untuk melunasi tumpukan cicilan yang terus menumpuk. Di sisi lain, ada suara hati yang berteriak, “Bagaimana dengan perjuangan? Bagaimana dengan janji yang sudah kau ukir?”
Keputusan selalu terasa sulit, seolah aku berdiri di persimpangan jalan yang tak berujung. Apakah mengambil pekerjaan berarti mengkhianati rekan-rekan yang masih berjuang? Apakah tetap menganggur berarti mengorbankan kebahagiaan keluargaku sendiri? Dilema ini tak pernah berakhir, dan setiap kali aku melihat kerutan di dahi istriku, atau mendengar suara lelahnya, rasa sedih itu semakin pekat, mengingatkanku betapa beratnya harga sebuah idealisme.
Hidup memang seringkali terasa sedang mempermainkanku, melemparkan ranjau di setiap jejak yang kupijak. Setelah semua perdebatan batin, semua dilema yang mencekik, aku akhirnya memilih jalan yang terasa paling berat, namun juga paling jujur pada diri sendiri dan perjuangan ini. Aku memutuskan untuk fokus mengerjakan apa yang bisa kukerjakan, apa pun itu, sambil terus menunggu keputusan dari sidang kasus pemecatanku yang tak kunjung usai. Setiap hari terasa bagai detik-detik di ruang tunggu, penuh ketidakpastian dan harapan yang terus menipis.
Di tengah ketidakpastian terlintas sebuah ide gila, kuliah kembali. Dulu, aku beruntung mendapatkan beasiswa S1 Manajemen di salah satu universitas di Ibu kota. dari perusahaan tempatku bekerja, sebuah kemewahan yang kini hanya tinggal kenangan. Sekarang, di tengah statusku sebagai seorang yang dipecat, tanpa penghasilan tetap, aku harus memulai semuanya dari nol. Aku memilih Universitas X jurusan Hukum. Mengapa Hukum? Mungkin karena aku ingin memahami lebih dalam seluk-beluk keadilan yang selama ini kukejar, ingin memiliki senjata yang lebih tajam untuk berjuang.
Namun yang membuat hatiku remuk setiap kali memikirkan keinginan untuk kuliah adalah kenyataan bahwa aku dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti ini, dari mana uang itu akan datang? Saat keraguan membanjiri, suara istriku kembali menjadi penawar, sekaligus penambah luka yang dalam. Dengan mata yang sudah terlalu sering kutemukan sembab di malam hari, dia menatapku, memegang tanganku erat, dan berucap dengan suara bergetar namun tegas, “Jangan khawatir soal itu, Sayang. Aku yang akan mengambil tanggung jawab ini untuk membiayai kuliahmu sampai kamu menjadi seorang advokat.”
Setiap kata itu menusuk, mengguncang jiwaku. Dia, yang seharusnya tidak memikul segala beban, kini justru memikul tanggung jawab berat. Aku tahu, ini bukan sekadar janji manis. Aku melihatnya mulai mengambil pekerjaan apa saja, bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengorbankan waktu istirahatnya, menguras tenaganya. Wajahnya yang dulu berseri, kini seringkali terlihat pucat dan lelah. Aku bisa merasakan beban yang kini ia pikul di pundak mungilnya, hanya demi mewujudkan mimpiku, mimpi yang sebenarnya adalah untuk perjuangan orang lain.
Seolah takdir mendukung keinginanku di federasi aku dipindahkan divisi. Dari divisi organisasi yang dulu penuh strategi dan perencanaan, kini aku berada di divisi advokasi. Sebuah divisi yang menuntut pemahaman hukum yang mendalam. Seolah semesta berkonspirasi, mendorongku untuk benar-benar mendalami bidang ini, menyiapkan diri untuk pertarungan hukum yang lebih besar.
Melihat istriku berjuang begitu keras, mengorbankan segalanya demi pendidikanku, membuat air mataku tak henti mengalir. Setiap buku hukum yang kubaca, setiap kuliah yang kuhadiri, terasa seperti pengkhianatan kecil terhadap dirinya. “Bagaimana bisa aku belajar di saat dia berpeluh mencari nafkah?” “Bagaimana bisa aku tenang menimba ilmu sementara dia berjuang mati-matian menjaga agar dapur kami tetap mengepul?” Ini bukan lagi tentang biaya, ini tentang pengorbanan yang tak ternilai, tentang cinta yang begitu besar sehingga mampu menghancurkan hati.
Masa depan seorang advokat yang dulu kubayangkan dengan gagah, kini terasa begitu berat. Setiap langkahku di koridor kampus, setiap lembar jawaban yang kutulis, terasa basah oleh keringat dan air mata istriku. Aku berjuang untuk para pekerja, iya. Tapi yang sebenarnya berjuang mati-matian untukku adalah dia, belahan jiwaku, yang rela meremukkan dirinya sendiri demi melihatku berdiri tegak, memegang toga seorang advokat. Kesedihan ini terlalu dalam untuk diungkapkan, sebuah beban yang mungkin tak akan pernah bisa kubayar lunas.
Setelah kurang lebih lima bulan berjuang di meja Pengadilan Hubungan Industrial, April 2025 akhirnya putusan atas kasusku keluar. Membaca putusan hakim sejujurnya aku kecewa, walaupun hasilnya sudah diperkirakan. Hakim mengesahkan pemecatanku karena melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Walaupun dalam pertimbangnya hakim menyatakan bahwa maskapi penerbangan tempatku bekerja, bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Putusan yang bertentangan menurut kami, padahal saksi ahli dari pihakku adalah seorang yang mengerti dan aktivis ternama di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Terkait larangan terlibat dalam partai politik yang tercantum dalam PKB jelas melanggar hak demokrasi.
“PKB mau huruf besar semua dan dilapisi emas tidak lebih hebat dari Hak Asasi Manusia,” terang HA pada saat kesaksian di pengadilan. Bisa saja ada kekhilafan dalam penyusunan PKB, tetapi tetap harus memelihara dan memperjuangkan norma HAK. Apakah aku salah atau benar hak Asasiku tidak boleh hilang hanya gara-gara PKB.
Penjelasan yang sangat mudah dipahami, tetapi sayang hakim-hakim di PHI lebih mengedepankan unsur ketenagakerjaan dibandingkan perspektif HAM. Tetapi itulah peradilan perburuhan. Banyak orang mengatakan bahwa PHI adalah kuburan buruh, aku juga paham bahwa tidak pernah ada yang benar-benar dimenangkan secara mutlak. Tetapi inilah tahapan yang harus aku dan jutaan buruh yang bersengketa harus lalui.
Saat ini kasusku sudah masuk tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA), aku tidak tahu berapa lama hakim di MA akan menyelesaikan kasusku. Aku juga tidak tahu apakah dikasasi ini hakim akan memenangkan aku atau menguatkan putusan PHI.
Banyak yang aku dapat dari perjalan hampir dua tahun ini. Pertama adalah peran istri yang sangat berpengaruh dalam perjuangan ini yang kedua keluarga besar dan teman di organisasi adalah bagian yang sangat penting dalam menguatkan aku.
Kedua, aku ingin menyampaikan jangan pernah berharap pada instansi-instansi pemerintah mau berlabel Hak Asasi Manusia, wakil rakyat atau ketenagakerjaan. Perjuangan buruh sesungguhnya ada di jalanan bukan lewat audience atau dialog.