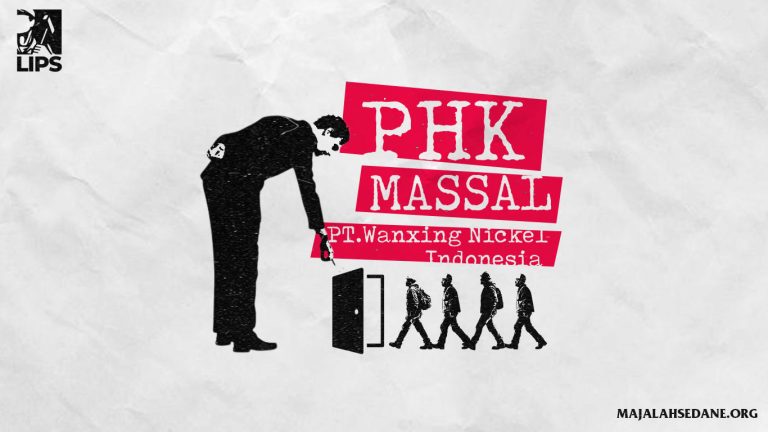
Pemecatan Massal di Morowali: Jalan Legal yang Rasional dari PT Wanxiang Nickel Indonesia
Dilansir dari beberapa media di nusantara, setelah kunjungan SMM Nickel Industry Field Trip pada Juni 2024, muncul berbagai dinamika di PT. Wanxiang Nickel Indonesia. 6 Juni 2024 terjadi mogok kerja buruh menuntut perbaikan kondisi kerja, upah, dan fasilitas di smelter Bahomotefe. 30 April 2025 demo kembali pecah karena keterlambatan pembayaran gaji dan kekurangan lembur. 4 September 2025 Disnaker Provinsi Sulteng melakukan pemeriksaan penggunaan TKA, ditemukan pelanggaran administrasi dan ketidaksesuaian jabatan dengan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Laode Hafid, ketua serikat buruh NIKEUBA di PT. Wanxiang yang juga terkena pemecatan massal mengatakan, sejak Maret hingga September tahun 2025, perusahaan telah melakukan pemecatan secara bertahap terhadap 1900 buruh secara sah dengan pemenuhan hak sesuai aturan ketenagakerjaan. Alasan efisiensi muncul dikarenakan calon investor baru tidak ingin memakai buruh lama. Baik buruh lokal maupun TKA.
Dari sampel peristiwa kronologi 2024-2025 yang terjadi di PT. Wanxiang, bisa kita lihat deretan peristiwa mogok kerja, demo, pelanggaran penggunaan TKA hingga pemecatan massal. Jika kita bawa sampel beberapa peristiwa tersebut secara urut dalam kerangka teori Varieties of Capitalism (VoC)1, pilihan calon investor baru untuk tidak menggunakan buruh lama menjadi sangat rasional dan lebih mudah dipahami. Dalam kerangka VoC tersebut, terdapat dua model yang umum dan bertolak belakang. LME (Liberal Market Economies) dengan pasar tenaga kerja fleksibel, tenaga kerja dipandang sebagai biaya dan minim intervensi negara. Sebaliknya, CME (Coordinated Market Economies) yang menekankan proteksi normatif, dialog sosial, tenaga kerja sebagai aset investasi jangka panjang. Masing-masing punya pasangan strategi hubungan industrial yang kompatibel. LME kompatibel dengan strategi Low Road2 (efisiensi biaya, upah rendah, kontrak fleksibel, pelatihan minim, union avoidance3, persaingan lewat harga murah), sedangkan CME kompatibel dengan startegi High Road4 (upah layak, stabilitas kerja, investasi SDM, dialog sosial, persaingan lewat kualitas dan inovasi).
Indonesia mengambil jalan tengah: model campuran. Dari CME, diambil bagian perlindungan normatif bagi buruh, hak-hak dasar, upah minimum, proteksi sosial, dan ruang berserikat. Dari LME, lewat UU Cipta Kerja, makin ditegaskan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kompetisi bebas antar industri. Liberal tapi protektif, dua kata lucu.
Fleksibilitas pasar kerja dan perlindungan normatif, jika diinstal bersamaan dalam sistem operasi ketenagakerjaan Indonesia, menjadi kompromi politik yang menambah variasi bug dari kapitalisme.
Namun di Wanxiang, sisi protektif dari regulasi ketenagakerjaan yang menekankan “Pemecatan harus dihindari sebisa mungkin” sebagai elemen positif dari CME, pada kenyataannya hanya sebatas aturan. Dialog sosial berjalan hanya antara pengusaha dan kolektif buruh, tanpa melibatkan serikat buruh. Melibatkan serikat, berarti membuka pintu intervensi pemerintah melalui tripartit, sesuatu yang dianggap tidak efisien oleh manajemen. Praktiknya jelas strategi Low Road.
Jika melihat kronologi sebelumnya, mulai dari mogok kerja 6 Juni 2024, demo 30 April 2025, hingga pemeriksaan TKA pada 4 September 2025, rentetan itu bisa dipandang oleh calon investor sebagai hambatan bagi stabilitas produksi ke depan. Kemudian, jika kita lihat jumlah pengangguran yang aktif mencari kerja di Indonesia, berdasarkan data dari Trading Economic, pada Maret 2025, diperoleh angka pengangguran terbuka sebesar 7,28 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa suplai tenaga kerja masih cukup tinggi, kemudian daya tawar buruh rendah. Hal-hal tersebut menjadikan pemecatan massal, tentunya dengan kompensasi yang sesuai regulasi, menjadi pilihan rasional yang didorong oleh calon investor kepada manajemen lama PT. Wanxiang. Bukan hanya sekadar untuk efisiensi biaya dengan melepaskan diri dari beban tanggungjawab dan pelanggaran administrasi sebelumnya, tapi juga sekaligus mereset budaya kerja lama, menghapus kebiasaan lama, sekaligus menghilangkan serikat buruh yang mulai resisten terhadap manajemen, meminimalisir pontensi lahirnya serikat baru yang dianggap menghambat profitabilitas ke depan. Sebuah strategi Low Road yang legal, sekaligus karpet merah bagi praktik union avoidance.
Sampai saat ini, untuk industri di wilayah Morowali, regulasi bisa dikatakan protektif, tapi praktiknya liberal. Protektif sebatas aturan, tapi di lapangan ada ruang fleksibel bagi strategi efisiensi perusahaan. Tanpa inovasi, model ini berpotensi menjadi masalah serius saat bonus demografi menuju Indonesia [C]EMAS 2045.
Salus operrriorum suprema lex esto [terj. Kesejahteraan buruh adalah hukum tertinggi]
Vivat Inoperosi
- Varieties of Capitalism (VoC) adalah pendekatan dalam studi ekonomi politik yang membedakan sistem kapitalis menjadi dua tipe utama: Liberal Market Economies (LME) yang mengandalkan pasar bebas seperti Amerika Serikat, dan Coordinated Market Economies (CME) yang lebih mengutamakan koordinasi antar lembaga seperti Jerman. Pendekatan ini menekankan bahwa institusi dan cara negara mengatur hubungan ekonomi memengaruhi strategi perusahaan dan hasil ekonomi. Konsep ini dikembangkan oleh Peter A. Hall dan David Soskice dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2001. ↩︎
- Strategi low road merupakan pendekatan yang mengutamakan pemotongan biaya melalui upah rendah dan kondisi kerja minim demi keuntungan cepat, mengabaikan hubungan kerja yang baik. ↩︎
- Union avoidance adalah upaya perusahaan mencegah pembentukan atau keterlibatan serikat buruh agar dapat mengontrol hubungan kerja tanpa campur tangan serikat. ↩︎
- High Road merupakan strategi manajemen yang menekankan investasi pada kualitas tenaga kerja melalui upah layak, pelatihan, dan hubungan kerja yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan jangka panjang. ↩︎