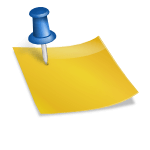Abu Mufakhir
Peneliti di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
“Abdi sanes nyandak taneuh jang dikantongan, atanapi diasupkeun ka keresek. Abdi mah ngan ngolah taneuh kanggo melak cabe jeung tomat. Tibatan tanahna nganggur, bari ku nteu sapira luasna, lain ribuan hektare siga nu diangge ku perusahaan swasta, encan mun gagal panenna.”
(Saya bukan mengambil tanah untuk dikantongin (dimasukkin saku celana), atau dimasukan ke kantong plastik. Saya mengolah tanah hanya untuk menanam cabe dan tomat. Daripada tanahnya nganggur, lagi pula luasnya juga tidak seberapa, tidak seperti ribuan hektare yang disewakan pada perusahaan swasta, belum lagi kalau gagal panen).
Politik perkampungan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah strategi pihak perkebunan dalam pembangunan, pengaturan ruang dan penataan pemukiman buruh kebun –baik emplasmen,[1] maupun perkampungan sekitar perkebunan—berikut dengan pranata-pranata sosialnya, sebagai bagian dari sistem kontrol dan pengawasan. Salah satu bentuk pokok dari politik perkampungan adalah politik isolasi dan konsentrasi, dengan cara membuat pemukiman buruh perkebunan terkonsentrasi dan terisolasi. Tujuan dari politik perkampungan dalam hal ini adalah melakukan pengendalian atas kehidupan sehari-hari masyarakat buruh perkebunan, membangun mekanisme pendisiplinan, juga relasi ketergantungan untuk menstabilkan proses akumulasi.
Politik Perkampungan
Ketika memasuki gerbang perkebunan teh Malabar, jalan raya beraspal berubah menjadi lebih lebar dan halus, kondisi ini berbeda jauh dengan jalan menuju perkampungan yang masih menggunakan pasir dan batu. Kemudian tidak jauh dari pintu gerbang dan pos Satpam, berdiri empat rumah besar dengan arsitektur Belanda, lengkap dengan cerobong asap dan mesin pemanas air di atapnya. Rumah itupun dihiasi dengan kebun bunga, dilengkapi garasi mobil, juga antena parabola. Ketika masuk lebih dalam, tidak jauh dari pabrik pengeringan teh, terdapat bungalow berlantai dua dengan kondisi yang lebih mewah. Lengkap dengan taman dan tenda kecil dengan meja dan kursi untuk menikmati sore-sore sambil minum teh. Rumah itu diperuntukan bagi pejabat perkebunan ketika melakukan kunjungan kerja. Kondisinya berbanding terbalik dengan bedengan (emplasmen), dan mayoritas rumah di sekitar perkebunan, yang sempit, sesak, dan lembab, juga berdempetan dengan kandang kambing. Mereka juga harus menimba dari sumur untuk mengambil air, lantai dapur dari tanah, masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, dan suplai listrik yang hanya tersedia 12 jam per hari.
Pagi hari kerja, penulis menyaksikan jeep Ford double cabin lalu-lalang keluar masuk pabrik, menghantar pejabat perkebunan. Ketika sore memasuki waktu penimbangan, akan terlihat hilir mudi truk-truk tua dengan asap hitam, mengangkut buruh pemetik teh yang menggunakan penutup kepala, berwajah lelah, berjejal berdiri, bersama dengan keranjang teh di pundaknya.
Kenyataan tersebut: antara jalan raya perkebunan dengan jalan perkampungan, rumah mewah pejabat perkebunan dengan bedengan kumuh pekerja perkebunan, jeep Ford double cabin yang kokoh dengan truk tua pengangkut buruh pemetik, memberikan gambaran mengenai bagaimana perkebunan membangun dan mengelola jarak, serta menciptakan garis pemisah antara masyarakat buruh perkebunan sebagai masyarakat pinggiran dengan manajemen perkebunan sebagai pusat otoritas. Pengelolaan jarak dan pembentukkan garis pemisah merupakan salah satu strategi pelembagaan kekuasaan pihak perkebunan dalam bentuk pengaturan ruang. Selain penataan pemukiman buruh yang dibangun sedemikian rupa, dengan membuatnya terkonsentrasi di tengah-tengah perkebunan, sehingga kehidupan sehari-hari buruh selalu berada dalam pengawasan, sekaligus relatif terisolasi dari berbagai macam perkembangan di luar perkebunan.
Dari jarak status tersebut, pihak perkebunan kemudian merawat kewibawaan dan mengukuhkan keabadian dirinya sebagai pusat otoritas terkuat. Tidak cukup di areal perkebunan sebagai tempat kerja, kekuasaan pihak perkebunan juga dengan mudah merembes masuk ke institusi sosial-politik perkampungan. Sebagai contoh, kantor desa Sindangsari, dusun tempat perkebunan teh Malabar berlokasi, berdiri di atas tanah milik perkebunan. Kenyataan ini merupakan salah satu gambaran bagaimana dominasi perkebunan berjalan. Perkebunan juga rutin memberikan bantuan sosial, dan dengan begitulah perkebunan dapat terus merawat posisinya sebagai pengayom dan penjaga masyarakat desa. Jarak dan pemisah tersebut secara halus telah menempatkan perkebunan sebagai subjek pemberi yang tulus; sedangkan masyarakat-buruh perkebunan ditempatkan sebagai subjek penerima yang harus selalu bersikap tahu diri, patuh dan tunduk. Bekerja sepenuh hati, apapun kondisi kerja yang mereka alami, hubungan kuasa antara pemberi dan yang diberi tak bisa digugat. Walaupun buruh pemetik teh yang merupakan mayoritas dari seluruh buruh perkebunan teh Malabar hanya mendapatkan upah Rp400-600 ribu per bulan, jauh di bawah ketentuan UMK Bandung.
Kekuasaan perkebunan berpusat pada Administratur (Adm) perkebunan, pejabat tertinggi di perkebunan teh Malabar. Kekuasaan seorang Adm perkebunan tidak hanya karena ia seorang atasan, wakil dari maharaja Direktur Utama PTPN VIII, tapi juga secara sosial, ia adalah simbol dari orang yang bijak, di tangannya-lah mayoritas penduduk desa Banjarsari menggantungkan hidup.[2] Penduduk desa yang berpapasan dengan Adm, umumnya akan mencium tangan, seperti halnya mencium tangan seorang Kyai. Tradisi ini adalah bentuk merembesnya kekuasaan administrator perkebunan ke dalam institusi perkampungan.
Pola reproduksi dan distribusi pelembagaan “kekuasaan” juga berlangsung dalam praktik kerja. Seperti pola rekruitmen warisan, dari ibu turun ke anak perempuannya, pola rekruitmen berdasarkan kekerabatan, seperti dari paman kepada keponakannya. Hal ini membuat hegemoni perkebunan berjalan lebih efektif. Buruh cenderung tidak melakukan perlawanan karena yang merekrut, atau menjadi mandor misalnya adalah paman sendiri. Kemudian, nyaris seluruh pemetik perempuan selalu berdandan lebih dulu sebelum berangkat kerja. Padahal tempat kerja mereka berada di tengah-tengah perkebunan, dengan satu-satunya lelaki adalah mandor. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan berdandan sebelum bekerja. Namun menjadi masalah ketika alasan berdandan itu untuk menyenangkan dan menghindari amarah sang mandor. Ketika buruh pemetik tidak berdandan, sang mandor biasanya akan marah. Jika sang mandor marah, hidup terasa lebih sulit lagi. Telah menjadi rahasia umum, mandor adalah pelaku utama kekerasan seksual terhadap buruh perempuan. Penulis kebetulan sekali, menemukan seorang mandor pada pagi hari sudah mengonsumsi minuman keras di salah satu pos keamanan di depan pabrik pengolahan.
“…. Glek-glek….” lalu mabok.
Posisi mandor sebagai representasi lelaki, merupakan pihak yang superior. Ia memiliki kekuasaan langsung untuk memutuskan apakah seorang buruh perempuan pemetik masih bisa bekerja atau tidak esok harinya, apakah bisa mendapatkan pinjaman uang atau tidak dari koperasi, dlsbnya. Mandor mabok merupakan representasi dari bahaya, ancaman dan kekerasan. Ini adalah bentuk dari dominannya kultur patriarki (melalui mandor sebagai simbol terdekatnya) yang diproduksi oleh perkebunan secara terus menerus, salah satunya melalui praktik konsentrasi perempuan pada jenis pekerjaan sebagai pemetik, dan menjadi mandor adalah hak eksklusif laki-laki.
Kekuasaan perkebunan yang merembes masuk ke institusi perkampungan, menyebabkan pendisiplinan dan mekanisme kontrol terhadap buruh kebun tidak hanya berlangsung dalam ruang kerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pejabat perkebunan seperti asisten kebun, sinder (pengawas) pabrik, sinder kebun, mandor besar, sampai mandor kecil, merembes masuk ke institusi formal pedesaan, menjadi perangkat desa seperti LPM (Lembaga Pemberdayan Masyarakat), BPM (Badan Perwakilan Masyarakat), dan Dewan Sekolah, bahkan kantor desa berdiri di atas tanah milik perkebunan. Pihak perkebunan juga membentuk aparatus-aparatus ideologisnya dengan menempatkan pejabat perkebunan sebagai Imam sholat Jum’at, atau menjadikan mandor sebagai guru ngaji di emplasemen. Secara rutin perkebunan juga memberikan bantuan untuk perbaikan sekolah, masjid, dan bantuan sosial kepada masyarakat ketika perayaan Iedul Qurban, dan Lebaran, termasuk yang dilakukan melalui program tanggung jawab perusahaan. Semua ini adalah bagian dari strategi pihak perkebunan untuk mendapatkan legitimasi dan status kekuasaannya.
Secara sederhana, perkebunan merupakan keseluruhan fenomena dan hubungan-hubungan yang timbul akibat proses produksi dan distribusi komoditas perkebunan. Pada proses produksi, hubungan tersebut ditandai dengan dominasi dan hegemoni pihak perkebunan terhadap masyarakat-buruh perkebunan, yang tidak selalu kasat mata. Kekuasaan perkebunan atas kepemilikan tanah, patronase, dan kultur patriarki, adalah inti dari politik perkampungan, sumber dari penjinakkan dan pendisiplinan. Hal tersebut sering disebut sebagai plantocracy: tatanan sekaligus nilai moral ekonomi yang berlaku di perkebunan (Chaterjee, 2001).
Plantocracy secara mendasar berada dekat dengan tatanan yang sudah berlaku lebih dulu pada masyarakat feodal. Perkebunan cukup menerapkannya secara lebih intensif. Perkebunan tak ubahnya tuan tanah, pengayom dan penjaga nilai-nilai luhur, serta bapak dan suami. Dalam kondisi ini perkebunan memiliki tiga wajah sekaligus: tuan tanah, pemuka masyarakat, dan bapak. Mapannya plantocracy di perkebunan teh Malabar milik negara ini, memperlihatkan hubungan antara kultur warisan kolonial-feodal dengan kapitalisme. Hal ini, membuat kelas pekerja di perkebunan menghadapi dua hal sekaligus: tatanan feodal dan kapitalisme.
Konfrontasi [3]
Ada banyak bentuk perlawanan yang dilakukan oleh buruh perkebunan Malabar, seperti memperlambat kerja, memasukkan batu ke dalam keranjang teh agar beratnya bertambah ketika ditimbang, melakukan mogok spontan tanpa dukungan serikat. Bentuk-bentuk perlawanan yang juga umum dilakukan oleh buruh manufaktur. Namun, ada bentuk perlawanan buruh perkebunan lainnya yang tidak pernah ada di buruh manufaktur, yaitu reklaiming tanah tempat mereka bekerja. Hanya saja perlawanan itu dilakukan oleh pensiunan, bukan buruh aktif. Walaupun begitu, bentuk perlawanan dengan melakukan aksi reklaiming tetap tidak umum bagi pensiunan di sektor nonperkebunan. Kisah perlawanan itulah yang penulis dapatkan dari dua pensiunan buruh golongan IA (golongan terendah bagi buruh tetap), yang terlibat dalam aksi-aksi reklaiming tanah milik PTPN VIII. Tanah tempat dimana mereka dulu bekerja.
Walau tanpa jumlah yang pasti, ada banyak pensiunan perkebunan Malabar tergabung ke dalam serikat petani AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria). Mereka terlibat dalam aksi-aksi reklaiming tanah PTPN VIII, karena tidak memiliki tanah setelah pensiun, baik untuk tempat tinggal maupun untuk aktivitas bertani, padahal uang pensiun mereka sangat kecil. Sejak pensiun pada 1988, sampai 1990, uang pensiun mereka hanya Rp45 ribu. Baru naik menjadi Rp110 ribu pada 2003. Mereka berdua bekerja di perkebunan Malabar bersama istrinya yang menjadi buruh harian lepas selama 30 tahun (1958 sampai 1988). Hidup mereka melekat, dan bergantung dengan perkebunan teh Malabar.
Ketergantungan terhadap pihak perkebunan terus berlanjut ketika pensiun. Kebanyakan pemetik, setelah pensiun kembali bekerja dengan status harian lepas, karena uang pensiun yang jauh dari cukup untuk hidup sehari-hari. Sampai kemudian fisik mereka tidak sanggup lagi untuk berkeliling perkebunan dan memanggul keranjang. Ketika itu, mereka akan menumpang tinggal di rumah anaknya, bercocok tanam untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari di sekitar bedengan. Tapi itu hanya dapat dilakukan jika anak mereka bekerja di perkebunan. Jika tidak, mereka harus benar-benar keluar dari emplasmen. Upah murah saat bekerja, serta kecilnya uang pensiun, membuat mereka tidak bisa membeli tanah untuk mendirikan rumahnya sendiri. Sementara mereka juga tidak tahu tempat lain, orang tua mereka dulu juga bekerja di perkebunan dan tinggal di emplasmen. Selain menjadi buruh perkebunan, aktivitas produktif yang mereka paling pahami adalah bertani. Masalahnya kepemilikan tanah telah dimonopoli oleh pihak perkebunan. Untuk terus melanjutkan hidup, mereka kemudian harus masuk ke desa-desa di sekitar perkebunan, mencari tanah yang bisa dibeli untuk mendirikan rumah dan bercocok tanam. Tak semuanya berhasil. Kondisi bertahan hidup seperti itulah yangkemudian mendorong mereka terlibat dalam aksi-aksi reklaiming.
Banyaknya pensiunan yang terlibat dalam aksi-aksi reklaiming, setidaknya menjelaskan bahwa permasalahan buruh perkebunan tidak hanya terletak pada upah murah, tapi juga akses terhadap tanah sebagai alat produksi. Tanah sebagai ikatan sosial paling pokok. Mengolah tanah adalah cara hidup yang paling mereka pahami selain menjadi buruh perkebunan. Bagi mereka, tempat dimana mereka lahir, adalah tempat terbaik dimana mereka mati. Karena itu, antara upah yang layak, serta akses terhadap tanah untuk dikelola secara mandiri, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada kasus ini, reklaiming merupakan wujud perlawanan terhadap monopoli tanah dan uang pensiun yang sangat kecil. Cermin dari bertemunya persoalan upah murah, tingginya ketergantungan terhadap perkebunan, dengan persoalan akses terhadap tanah.
Catatan
[1] Pemukiman pekerja perkebunan yang disediakan oleh perkebunan dalam bentuk bedengan-bedengan
[2] Menurut Sekdes Banjarsari, 60% dari 6500 penduduk Banjarsari bekerja di perkebunan. Wawancara Sekdes Banjarsari, 28/09/2011
[3] Bagian ini didapat melalui wawancara dengan dua pensiunan PTPN VIII yang menjadi anggota serikat petani AGRA, dan terlibat dalam aksi-aksi reklaiming tanah milik PTPN VIII. Wawancara dilakukan pada 27 September 2011