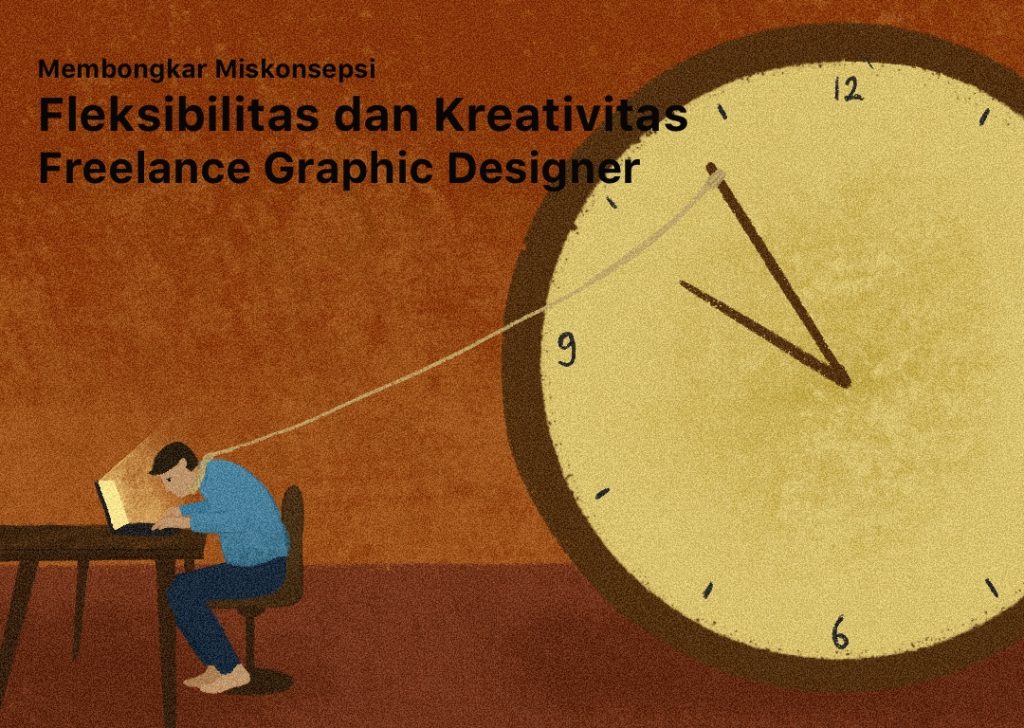Di tengah informaslisasi dan pasar kerja fleksibel, menjadi freelance adalah pilihan yang dianggap memberikan keuntungan tersendiri bagi generasi kelahiran tahun 2000-an. Generasi yang dibesarkan di tengah berkembangnya teknologi informasi. Tren menjadi freelance dianggap pekerjaan yang memiliki kebebasan, kemandirian, keleluasaan mengatur waktu kerja, dan tidak terikat dengan perusahaan. Pasar kerja freelance pun difasilitasi oleh ketersediaan platform freelance untuk mempermudah mencari klien.
Bahkan, bagi para pemula dalam sektor industri kreatif, seperti desain grafis, menjadi freelance adalah langkah wajib pertama dalam memperkenalkan diri secara profesional di dunia kerja. Belum memiliki pengalaman project prestisius sebelumnya untuk ditampilkan pada portfolio, tentu saja freelance adalah solusi utama dalam menangani keadaan ini. Namun, sangat penting untuk mengetahui realitas dari beberapa mindset mengenai kekurangan dan kelebihan untuk menjadi seorang freelancer!
Pandangan masyarakat awam terhadap freelance graphic designer atau pekerja desain grafis lepas, kerap berkutat dalam dua bentuk asumsi: kerja untuk mendapatkan imbalan atas kreativitas seni, atau mendapatkan imbalan atas sekadar kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi.
Sekilas, dua narasi sederhana di atas tidak tampak kontrakdiktif ataupun mustahil untuk berjalan beriringan. Namun, kenyataan bahwa kreativitas manusia kini tereduksi menjadi sebuah barang dagangan dapat mengalihkan esensi kreativitas itu sendiri secara praktis—mencari ide akan terasa seperti berada di dalam kondisi terbatas, alih-alih sebagai momen mengembangkan imajinasi.
Sergio Tischler (2005) mengidentifikasi ‘batasan’ dari kreativitas sendiri adalah waktu; monetisasi kreativitas akan menuntun individu untuk secara alamiah menyesuaikan penggunaan kreativitas sebagai modal dengan aturan bermain suatu industri. Maka, indikator ‘waktu’ menjadi standar untuk mengukur upah kerja dengan menggunakan kreativitas tersebut, seperti dalam wujud tenggat waktu atau deadline.
Oleh karena itu, terlepas dari memiliki keistimewaan menguasai alat produksi—perangkat laptop serta ‘printilan’ software mahal dari Adobe—daripada buruh-buruh sektor lain, sebagian besar freelance graphic designer masih merasa akan lebih baik untuk menormalisasikan imbalan rendah dengan bobot kerja tinggi (Karygan dan Demir, 2017).
Kondisi rentan ini kerap terjadi kepada freelancer muda. Dengan pengalaman yang minim mereka kerap menghadapi miskonsepsi lain, seperti status bekerja tanpa kontrak dinilai akan membuat seorang pekerja lepas menjadi lebih leluasa dalam memilih atau menolak suatu pekerjaan. Narasi ini tidak seratus persen salah, sebagaimana seorang freelance dengan keadaan sudah memiliki pekerjaan tetap lain, memang akan merasa lebih tenang untuk memilah pekerjaan pada platform freelance yang bergerak di dunia virtual.
Bahkan, kegiatan freelancing dapat menjadi wujud dari konsep work for labor semata. Guy Standing (2011) ketika membahas mengenai tren kerja prekariat, mendefinisikan konsep work for labor sebagai aktivitas menjalin koneksi, mencari kerja tambahan, atau menguasai satu skill baru tanpa dibayar siapapun—tetapi sangat penting untuk mempertahankan atau mendapatkan pekerjaan selanjutnya. Menurut Standing, freelance graphic designer sendiri dapat dikategorikan sebagai bagian dari prekariasi, atau sistem kerja dengan ketidakpastian sebagai seorang tenaga kerja tersebut (Frase, 2013).
Berbicara mengenai kepastian, fleksibilitas kerja freelance graphic designer hanya merupakan ilusi semata. Namun, ketiadaan akses terhadap jaminan kesehatan, kepastian status dan arah karier, kecukupan memenuhi kebutuhan minimum, dan keamanan dalam menjalankan hak berserikat merupakan sejumlah prasyarat yang harus dikorbankan oleh freelance graphic designer demi mendapatkan fleksibilitas.
Berdasarkan laporan riset ketika saya berkesempatan untuk mewawancarai R.A. Dita Saraswati, Direktur Riset dan Pendidikan dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI), menjadi freelance terkadang memang merupakan kondisi paling sesuai untuk para graphic designer sebagai mata pencaharian. Mengisahkan preferensi pribadi untuk bekerja sebagai seorang freelancer, ia kemudian menyampaikan:
“Aku menyebutnya ‘kedinamisan’ ya, karena ‘ribet’ pekerjaan desain grafis. Kalau desain itu mengandalkan situasi dan kreativitas, sehingga terkadang kita enggak bisa menuliskan berdasarkan waktu, sampai malam pun bisa kita kerjain tergantung kreativitas lead kita,”
Dita Saraswati, Direktur Riset dan Pendidikan dari ADGI
Selain itu, Dita juga mengemukakan bahwa ‘waktu’ mau tidak mau telah menjadi tantangan sekaligus batasan paling mutlak untuk menuntaskan kerja. Terutama, dalam memastikan seorang freelancer tidak terlalu bekerja di luar proporsi dari keterbatasan upah yang diterima.
“Dari sini akhirnya muncul cara kerja tersendiri yang memanfaatkan waktu, bagaimana ia mengakali agar yang ia terima sepadan.”
Dita Saraswati, Direktur Riset dan Pendidikan dari ADGI
Pernyataan Dita ini sejalan dengan tulisan dari John Holloway (2002) yang mendeskripsikan keadaan ini dalam konsep “power-to” dan “power-over” dalam konteks studi buruh. Istilah “power-to”atau ‘kekuatan untuk melakukan sesuatu’ merujuk kepada tindakan naluriah seorang manusia, seperti mengembangkan kreativitas. Namun, bertahan hidup di dalam sistem kapitalisme telah mematikan “power-to” dan mengalihkan sistem kerja menjadi istilah “power-over”atau keadaan di mana terdapat batasan-batasan dalam bentuk dan keuntungan ekonomis dalam melakukan produksi (Holloway dalam Webster dan Randle, 2016).
Dengan demikian, dalam pasar ekonomi dengan keikutsertaan seorang freelancer untuk mengonversi kreativitas menjadi sebuah moda produksi, seluruh kemampuan untuk berimajinasi dan berpikir kreatif yang dimiliki secara ‘alamiah’ ini menjadi terkontrol oleh sebuah keterbatasan. Dalam konteks ini, keterbatasan tersebut adalah kehadiran ‘waktu’ sebagai batasan sekaligus indikator determinan. Michael Burawoy (1983) merumuskan pandangan atas keadaan ini sebagai indikator rate fixing, di mana waktu sebagai patokan untuk mengukur produktivitas dan efisiensi kerja dalam menentukan upah.
Secara garis besar, diskursus dengan istilah-istilah kompleks tersebut bermaksud untuk menjelaskan bahwa pemberi kerja di platform freelance akan menentukan deadline atau tenggat waktu secara sempit. Padahal, keterbatasan waktu tersebut kerap tidak diiringi dengan bobot kerja yang mempermudah seorang graphic designer untuk mengeksekusinya. Entah itu berupa instruksi kurang jelas, konstan meminta revisi besar dan upah yang tidak sepadan.
Akibatnya, seorang graphic designer akan merasa kebutuhan untuk membatasi daya kreativitas-nya dengan langkah pragmatis. Seperti minim modifikasi dari referensi, hasil desain tidak terlalu maksimal, sampai dengan terdorong untuk melakukan plagiasi maksimal. Para pemberi kerja di situs-situs platform freelance tentu tidak akan memperdulikan kondisi tersebut, beberapa tidak segan menganggap enteng dengan memberi upah rendah atau—enggan membayar sama sekali (hit-and-run) dalam kasus kerja freelance dari situs tak tepercaya.
Suka duka menjadi seorang graphic design freelance tidak serta-merta menjadikan pekerjaan ini terlarang atau seratus persen perlu dihindari—melainkan, tujuan artikel ini adalah untuk mengedukasi. Penting untuk mengidentifikasi, bahwa seorang graphic design freelance dapat dikatakan memiliki otonomi atau keleluasaan lebih besar dari buruh-buruh lain dengan memiliki perangkat seperti laptop untuk alat produksi.
Oleh karena itu, sebaiknya seorang graphic design freelance tidak ragu untuk memilah pekerjaan dengan bobot dan upah cenderung seimbang. Kenyataan ini kerap diimplementasikan seorang freelance yang sudah memiliki sejumlah pengalaman—tidak perlu terlalu berpengalaman atau expert, tetapi penting untuk sekadar memahami kiat ‘waras’ dan bertahan di tengah gempuran aturan bermain atau rules of play dalam persaingan ketat pasar graphic design. Setiap menit, ada ratusan pekerjaan baru, dengan ratusan freelancer selain kamu.
“the idea of creative labour has a strong popular appeal, promising, as it does, a fulfilling marriage of art and work. Yet, much work in creative industries is not creative at all” . [Gagasan mengenai pekerjaan kreatif menawarkan gambaran sangat menarik, seperti memadukan seni dan bekerja. Akan tetapi, sebagian besar pekerjaan di industri ini sama sekali tidak kreatif].
Clark, 2009.
Pernyataan Clark (2009) di atas menunjukkan realita dari kerja freelancer graphic design. Konsekuensi melakukan komodifikasi atau ‘menjual’ kreativitas itu sendiri adalah perlahan merasa kehilangan esensi dari kreativitas—berimajinasi dan menuangkan ide ke kanvas di layar komputer kini, secara perlahan, menjadi tidak terlalu menyenangkan lagi.[]
Referensi
Burawoy, M. (1983). Between the Labor Process and the State: The Changing Face of Factory Regimes Under Advanced Capitalism. American Sociological Review, 48(5), 587–605.
Clark, D. (2009). Crunching Creativity: An Attempt to Measure Creative Employment. Creative Industried Journal. 2(3). 217—230.
Frase, P. (2013). The Precariat: A Class or a Condition?. New Labor Forum, 22(2). 1—14.
Holloway, J. (2002). Change the World Without Taking Power. Pluto Press.
Kaygan, P., dan Demir, O. (2017). The Cost of ‘Free’ in Freelance Industrial Design Work: The Case of Turkey, The Design Journal, 20(4). 493—510.
Morgan, G., Word, J., dan Nelligan, P. (2013). Beyond the Vocational Fragments: Creative Work, Precarious Labour, and the Idea of Flexploitation. The Economic and Labour Relations Review, 24(3). 397—415.
Tischler, S. (2005). Time of Reification and Time of Insubordination dalam Bonefeld dan Psychopedis. (ed). (2005). Human Dignity: Social Autonomy and the Critique of Capitalism. Ashgate.
Webster, J., dan Randle, K. (2016). Virtual Workers and the Global Labour Market. Palgrave Macmillan.
Penulis
-
Bebby Namira Nur Muslim
-
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia