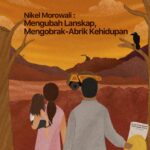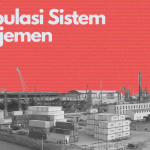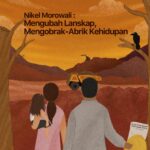Menurut International Labour Organization (ILO), dialog sosial itu mencakup perundingan, konsultasi, dan pertukaran informasi antara wakil dari pemerintah, pengusaha dan buruh/serikat buruh untuk membahas isu-isu seputar ketenagakerjaan demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam kerangka tripartit ini, serikat buruh diposisikan sebagai mitra setara dengan fungsi representasi, kontrol sosial dan advokasi kelas buruh.
Namun, realitas di lapangan, khususnya area Morowali, mayoritas serikat buruh di Morowali sepertinya menunjukkan degradasi peran pada posisi ini. Praktik dialog sosial di Morowali menciptakan ilusi sedang menguat padahal justru secara tidak sadar mengalami kemunduran. Mayoritas petinggi serikat buruh di wilayah ini secara sadar memberi diri dengan mengatasnamakan organisasinya menjadi tim sukses guna mendukung paslon-paslon Bupati. Afiliasi semacam ini menunjukkan pergeseran posisi serikat buruh dari mitra independen menjadi mitra subordinat elit lokal.
Kooptasi serikat buruh juga tidak berhenti pada kekuasaan politik lokal saja, tetapi sejak lama berlangsung melalui kooptasi langsung oleh pengusaha dengan pola ekonomi transaksional. Kooptasi dilakukan melalui kerjasama bisnis antara elit serikat buruh dan manajemen perusahaan. Semisal, proyek pengadaan barang, jasa penyedia tenaga kerja, akses fasilitas khusus di luar perundang-undangan, atau dukungan finansial bagi struktur organisasi buruh. Hal-hal tersebut tentu merupakan hal yang positif bagi perkembangan serikat buruh yang mempertahankan independensi garis perjuangan. Tetapi dalam banyak kasus, independensi tersebut memudar, sehingga relasi ini membentuk ketergantungan ekonomi elit serikat buruh kepada pengusaha, yang secara langsung memengaruhi sikap dan arah perjuangan organisasi.
Dalam analisis Peggy Kelly soal proses dialog sosial di Indonesia, rintangan utama bagi dialog sosial yang sehat adalah rendahnya kapasitas dalam konteks hubungan industrial antara mitra dalam tripartit untuk melaksanakan dialog sosial secara efektif, krisis kepercayaan antara mitra dalam tripartit, intervensi aparat keamanan, cara penanganan perselisihan industrial, diskriminasi gender, hingga minimnya pengawasan ketenagakerjaan. Namun ada satu hal yang luput dari analisis tersebut, yakni kooptasi halus oleh elit pemerintah lokal dan pengusaha, di mana serikat buruh secara sadar menjadi subordinasi kekuasaan dan kepentingan modal demi keuntungan personal atau kelompok kecil, buruh akar rumput kehilangan representasi.
Fakta empiris terbaru memperkuat gejala kooptasi ini. Dengan banyaknya masalah pelanggaran ketenagakerjaan di area Morowali yang belum selesai, aksi protes memperingati May Day 2025 di Morowali hanya meriahkan oleh dua serikat buruh, meskipun secara administratif terdapat lebih dari sepuluh serikat buruh terdaftar secara resmi. Ketidakhadiran mayoritas serikat dalam aksi yang menyangkut kepentingan langsung buruh serta tidak adanya dialog nyata oleh serikat buruh dengan pemangku kepentingan menjadi bukti konkret gejala hegemoni dan kooptasi elit politik dan pengusaha.
Fenomena ini mengingatkan pada dominasi FSPSI sebelum 1998, yang menjadi alat kelas elit politik dan kapital ketimbang alat perjuangan kelas buruh. Perbedaannya, jika dulu bersifat koersif, hari ini bersifat hegemonik. Dalam kerangka teori Antonio Gramsci, ini merupakan bentuk hegemoni di mana subordinasi tidak terjadi melalui tindakan represi langsung, melainkan melalui kooptasi halus. Serikat buruh diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan dan modal. Hegemoni tercipta ketika elit serikat kehilangan independensi dan masuk ke jaringan kekuasaan, baik politik maupun ekonomi, lalu menerima konsensi sebagai pengganti perjuangan. Ilusi narasi kemitraan industrial yang mematikan daya kritis.
Dalam perspektif Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam The Narrow Corridor, relasi negara dan masyarakat sipil idealnya berada dalam koridor sempit yakni Shackled Leviathan, di mana negara cukup kuat untuk menegakkan hukum dan memberikan pelayanan, namun juga cukup dibatasi oleh masyarakat sipil yang aktif, bebas dan berdaya. Dalam konteks Morowali, kooptasi serikat buruh oleh kekuasaan lokal dan pengusaha justru menjauhkan kondisi ini dari shackled Leviathan menuju despotic Leviathan, yang mana masyarakat sipil, dalam hal ini serikat buruh kehilangan fungsi pengawasan.
Elit serikat buruh yang masuk ke ranah kekuasaan secara informal dan transaksional, menggunakan organisasi buruh sebagai alat politik pribadi dan bisnis kolektif, menjadikan kedekatan dengan penguasa dan pengusaha bukan sebagai kemenangan kelas pekerja, melainkan awal dari subordinasi. Ini menghasilkan pertukaran dukungan politik dan loyalitas terhadap modal dengan pelemahan gerakan akar rumput yang lebih progresif. Energi perlawanan dialihkan ke dalam birokrasi politik dan ekonomi sehingga menjadi stagnan.
Gejala kooptasi serikat buruh oleh politik lokal dan relasi bisnis perusahaan di Morowali menciptakan ilusi partisipasi aktif serikat buruh tanpa substansi perjuangan kelas. Serikat buruh, yang semestinya mempertahankan independensi dalam mengawasi kekuasaan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan lokal dan kekuatan modal. Fungsi kontrol kekuasaan terkait ketenagakerjaan menjadi bergeser, menjadikan serikat buruh menjadi bagian dari jaringan patronase politik dan ekonomi.
Dalam situasi ini, dialog sosial kehilangan nyawanya. Tanpa kebebasan berserikat yang sejati dan tanpa independensi organisasi, dialog sosial tidak lebih dari sekadar formalitas birokratik tanpa perjuangan. Maka, SB/SP yang harusnya singkatan dari serikat buruh/serikat pekerja, mungkin untuk konteks serikat dominan di Morowali akan bergeser menjadi serikat Birokrasi/serikat Pengusaha.
SALUS OPERARIORUM SUPREMA LEX ESTO
Jika Anda menikmati membaca cerita ini, maka kami akan senang jika Anda membagikannya!