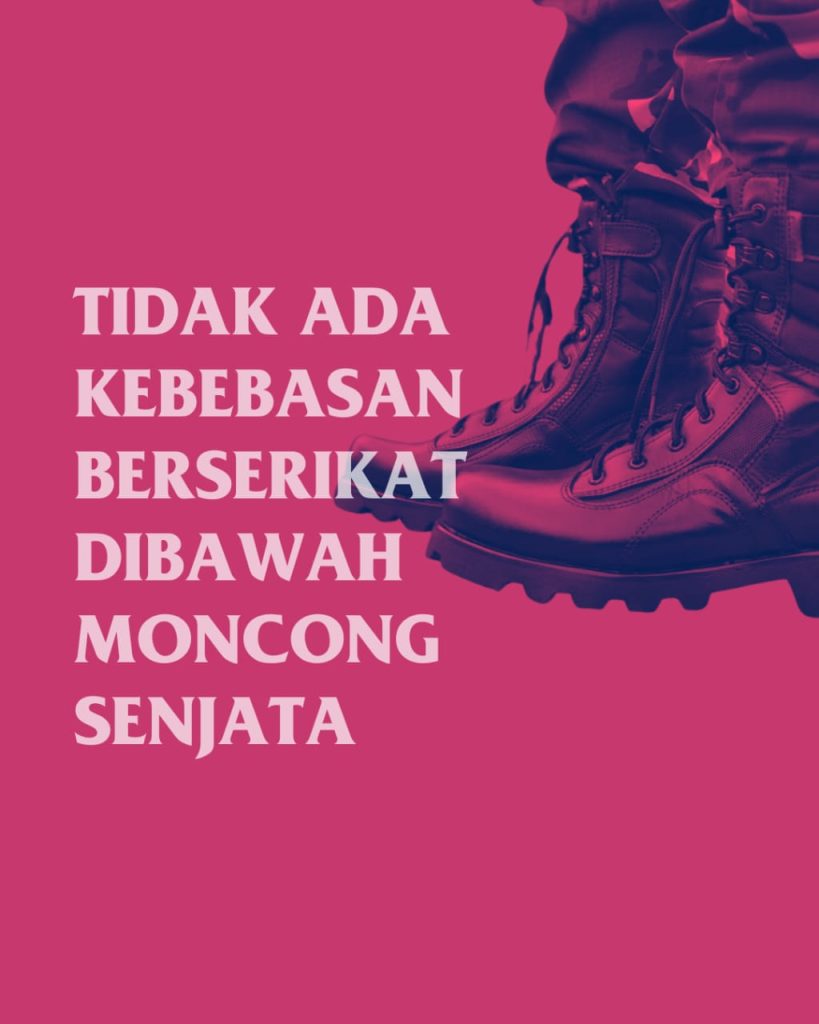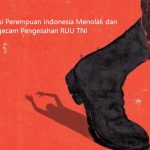Pengesahan revisi RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 merupakan ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berunding. Kebebasan berserikat dan berunding merupakan pilar utama kaum buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan. Meskipun dalam aksi-aksi massa penolakan UU TNI hanya sedikit serikat buruh yang terlibat. Tentu saja, semua orang mengetahui buruh dan serikat buruh sedang disibukkan dengan kasus-kasus pemecatan, yang semakin brutal.
Pantauan Ekspedisi Indonesia Baru, dari 20 hingga 25 Maret 2025 aksi massa menolak UU TNI dan militerisme serta menuntut tentara kembali ke barak terjadi di 45 wilayah dari Banda Aceh hingga Manokwari. Rata-rata aksi massa diikuti oleh pelajar dan buruh yang tidak berserikat. Dalam diskusi-diskusi informal para buruh dan pencari kerja mengomentari UU TNI, “Di saat kami sulit mendapatkan pekerjaan terdapat orang-orang kuat yang dobel job dengan kepastian kerja dengan upah berdigit-digit.”
Pengalaman memperlihatkan bahwa pembatasan ruang demokrasi menyulitkan gerakan buruh meraih kesejahteraan. Tidak akan pernah ada kebebasan berserikat, kesejahteraan dan perbaikan kondisi kerja di bawah moncong senjata. Misalnya, mogok nasional yang dilakukan serentak di berbagai kota dari 24 hingga 27 November 2015 tidak menghasilkan apapun selain represi keras dari aparat keamanan dan pemecatan terhadap buruh yang mogok (Arifin, 20 Desember 2021). Contoh lain yang lebih mengerikan terjadi di perusahaan arloji, PT Catur Putra Surya pada 1993. Tuntutan perbaikan kondisi kerja dan kenaikan upah minimum dijawab dengan pemecatan dan penyiksaan terhadap 19 buruh. Satu di antara buruh tersebut dibunuh. Pemecatan, penyiksaan dan pembunuhan tersebut melibatkan Komando Distrik Militer 0816 Sidoarjo Surabaya Jawa Timur. Ya, salah satu buruh yang dipecat, disiksa dan dibunuh tersebut adalah Marsinah.
Kasus pemogokan 2015 dan 1993 relatif berbeda. Pada 1993, aparat keamanan baik tentara maupun polisi diberikan ruang oleh peraturan perundang-undangan untuk dilibatkan dalam penyelesaian kasus-kasus perburuhan. Yaitu melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 342 Tahun 1986, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 120 Tahun 1988 dan Surat Keputusan Komandan Bakorstanas Nomor 02 Tahun 1990 tentang Pedoman Penanggulangan Kasus-kasus Hubungan Industrial. Peraturan-peraturan tersebut mengizinkan kepolisian dan tentara mengatasi kasus-kasus perburuhan, termasuk memaksa buruh yang mogok untuk bekerja kembali.
Pada 2015, peraturan yang membolehkan intervensi tentara dan polisi dalam kasus perburuhan sudah tidak berlaku. Meskipun dalam kasus-kasus kecil, terutama di kawasan industri, di bandara dan di pelabuhan selalu terdapat cerita tentara maupun polisi berusaha mengintervensi persoalan buruh dengan menghadiri perundingan bipartit atau tripartit. Tak jarang pula terdapat cerita aparat tentara atau polisi yang menyediakan diri sebagai mediator kasus perburuhan.
Memang dalam 15 tahun terakhir beberapa serikat buruh kerap mengandalkan jasa tentara untuk melatih para anggotanya menjadi ‘laskar demonstrasi’. Namun, watak dasar serikat buruh dan militer jauh berbeda. Misalnya, prinsip dasar serikat buruh demokrasi sedangkan militer pada garis komando. Serikat buruh mempraktikkan dialog dan diskusi, militer mempraktikkan instruksi dan kepatuhan.
Namun, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, memungkinkan pemerintah daerah melibatkan aparat keamanan dalam menghadapi masalah perburuhan. Peraturan tersebut melengkapi pengerahan aparat keamanan untuk pengamanan objek vital nasional, seperti yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620 Tahun 2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri.
Setelah peraturan objek vital nasional, pada 2014, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko diwakili Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero. Perjanjian kerjasama tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kawasan industri sebagai aset strategis bagi investasi asing (rmol.id, 21 Mei 2014). Tentu saja yang dimaksud adalah pemastian kawasan industri dari protes masyarakat terkhusus dari pemogokan buruh.
Menurut PBHI, kerjasama TNI dengan lembaga sipil terus bertambah sejak 2015. Sebanyak 31 MoU pada 2015, 30 MoU pada 2019 dan 41 MoU pada 2024. Selain itu, tentara pun diberikan kesempatan utnuk menduduki jabatan penting di perusahaan industri ekstraktif, perhutanan dan perkebunan. Selain tentara, polisi pun dilibatkan dan dipergunakan untuk menindas buruh dan tani yang menolak proyek strategis nasional.
Terbaru adalah kasus pengambilalihan PT Duta Palma Group oleh PT Agrinas Palma Nusantara Persero, pada awal Maret 2025. Sebelumnya, aset PT Duta Palma Group disita Kejaksaan Agung akibat tindak pidana pencucian uang. Jajaran direksi PT Agrinas dipegang oleh mantan tentara, yaitu Direktur Utama oleh Letjen TNI Purn Agus Sutomo, mantan TNI-AD yang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI-AD dan Pangdam V Brawijaya; Direktur Perkebunan oleh Cucu Somantri mantan Staf Khusus Kasad. Saat ini menjabat Ketua dan Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029; Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah Bachtiar Utomo, purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang pernah menjabat Wadan Kodilat TNI AD; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko oleh M. Wais Fanshuri. Di jajaran komisaris terdapat Wisnoe Prasetja Boedi sebagai komisaris utama, yang pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.
Menurut Imparsial, sepanjang 2024 hingga 2024 terdapat 41 kasus kekerasan yang melibatkan dan dilakukan oleh prajurit TNI. Dari angka tersebut, korbannya berjumlah 67 orang, 17 di antaranya meninggal dunia. Menurut KontraS sepanjang 2023-2024 sebanyak 641 peristiwa kekerasan yang melibatkan polisi dengan korban 754 orang menderita luka-luka dan 38 lainnya meregang nyawa.
Sebagaimana diketahui, UU TNI hasil revisi memperluas peran tentara, memperteguh peran tentara yang telah menduduki jabatan-jabatan sipil dan kerap dilibatkan dalam mengontrol gerakan buruh. Menurut Imparsial, pada 2023 terdapat 2.500 prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil (CnnIndonesia.com, 4 Maret 2025). Dengan UU tersebut tugas tentara terdiri dari dua, yaitu melaksanakan operasi perang dan operasi militer selain perang.
Tugas operasi selain perang terdiri atas 16 poin. Dari ke-16 poin tersebut, tugas yang berpotensi memberangus kebebasan berserikat dan berunding adalah tugas tentara untuk mengamankan objek vital nasional, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber. Penjelasan “membantu tugas pemerintah di daerah” adalah “… serta mengatasi masalah akibat pemogokan …”.
Dengan poin-poin di atas, gerak-gerik serikat buruh dalam bentuk kampanye di media sosial, perundingan dengan manajemen, pemogokan di dalam pabrik dan protes massal di jalan raya dapat dikategorikan sebagai ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara. Bagi militer gerak-gerik serikat buruh bukan lagi sebagai hak demokratis untuk menuntut kesejahteraan. Ruang gerak serikat buruh makin terbatas.
Seturut dengan revisi UU TNI, DPR RI pun telah membahas untuk segera merevisi UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik. Tentu saja perubahan tersebut untuk menyelaraskan tugas polisi dengan tentara. Misalnya, dalam draf RUU Polri Pasal 16 ayat 1 huruf q disebutkan Polri berwenang melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
Perubahan lainnya menyebutkan, Polri bertugas untuk mengoordinasi, mengawasi, dan melakukan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh UU, dan bentuk pengamanan swakarsa. Pasal ini berpotensi menjadikan Polri sebagai superbody investigator, menyediakan ruang bagi “bisnis keamanan” (Tempo.co, 23 Maret 2025), dan menghambat gerakan buruh mengampanyekan masalah perburuhan di media sosial.
Dengan gambaran di atas, peran dan posisi TNI dan Polri akan saling melengkapi dan menguatkan, sekaligus meminggirkan hak demokratis buruh. Cerita tersebut mengingatkan kembali pada peran pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial dan politik ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang berlaku dari 1969 hingga 2000.
ABRI merupakan kekuatan gabungan dari Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Selain memiliki senjata dan gelontoran anggaran keamanan, ABRI merupakan kekuatan politik sekaligus aparat kekerasan negara yang dibentuk dan dipupuk secara historis melalui dua trayek, yaitu penguasaan sumber-sumber ekonomi dan penguasaan komando teritorial dari tingkat provinsi hingga desa. ABRI merupakan kekuatan politik mandiri, berpengaruh dan menentukan (Aditjondro 2004: 3). Tentara dan polisi pernah dibesarkan dalam wadah yang sama, yang menganggap protes rakyat sebagai ancaman, gangguan dan rongrongan terhadap negara. Oleh karena itu, watak brutal di tubuh aparat kepolisian dan tentara telah berlangsung bertahun-tahun.
Pada 2000, upaya untuk mempreteli kekuatan ABRI tidak benar-benar berhasil. Dwifungsi ABRI secara resmi dihapuskan. Lembaga kepolisian dan tentara dipisahkan. ABRI pun tidak memiliki keistimewaan memiliki perwakilan di parlemen. Namun secara politik kekuatan tentara bercokol kuat. Mereka berhasil menyebarkan, mempertahankan mengumpulkan kekuatannya dengan menduduki peran-peran strategis di lembaga negara, memasuki atau mendirikan partai politik, mendirikan yayasan dan menjadi pemasok tenaga kerja di bidang jasa keamanan (Widoyoko, dkk., 2003: 12-15). Kekuatan utama militer masih memiliki struktur yang utuh dari tingkat provinsi hingga desa, terdiri atas Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Pada akhirnya, pengesahan UU TNI dan revisi UU Polri tidak hanya memperlihatkan dimensi ketergantungan negara terhadap modal asing yang mengandalkan buruh murah, tapi ketergantungan negara terhadap aparat kekerasan antidemokrasi untuk menindas buruh agar selalu patuh pada kebijakan upah murah tanpa kepastian kerja.