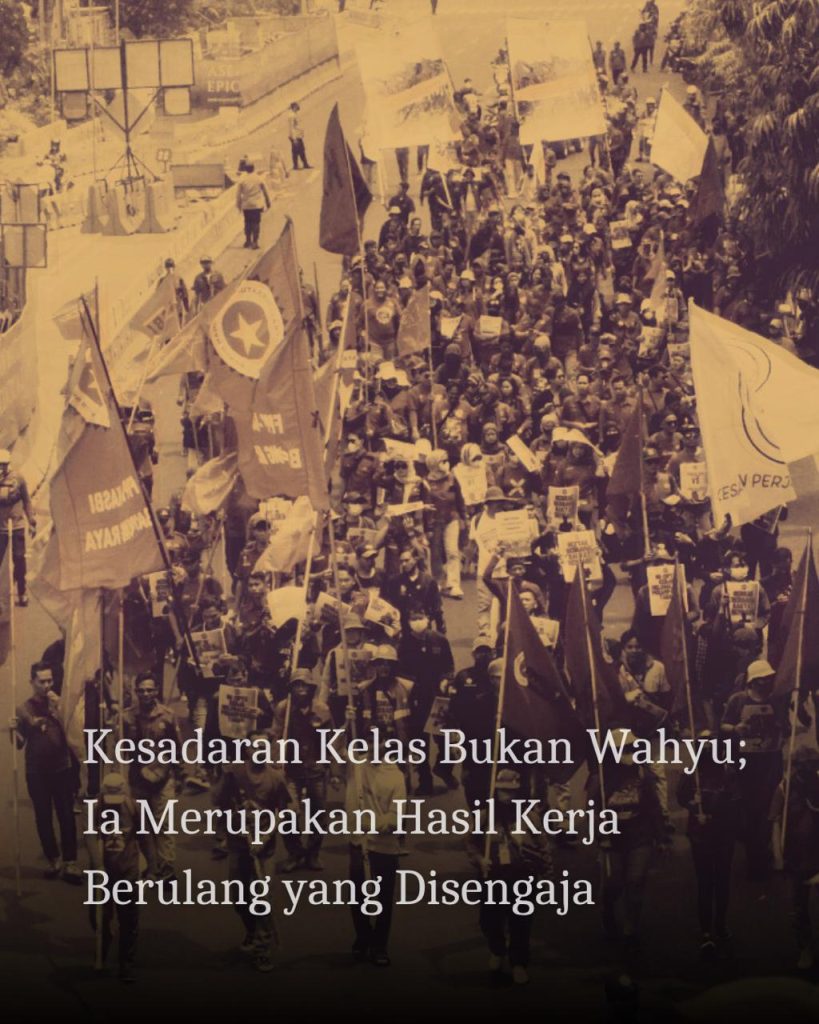“The working class did not rise like the sun at an appointed time. It was present at its own making”– E.P. Thompson
Beberapa waktu lalu, buruh ojek online menggelar mogok nasional. Mereka menuntut sistem kerja yang lebih adil dan pembagian tarif yang lebih manusiawi. Tak lama berselang, muncul diskusi soal Almazt Fried Chicken—gerai makanan cepat saji yang menggaji buruhnya di bawah upah minimum provinsi (UMP). Sementara itu, di Cirebon, ribuan buruh PT Yihong Novatex Indonesia mengalami PHK sepihak dengan dalih penutupan pabrik. Tiga kasus ini memperlihatkan wajah buruh Indonesia hari ini: bekerja di sektor yang berbeda—logistik digital, makanan cepat saji, dan garmen manufaktur—namun diikat oleh pengalaman yang sama: ketidakadilan struktural yang berulang.
Namun, yang mencolok bukan hanya praktik eksploitasi itu sendiri, melainkan minimnya solidaritas dari sesama buruh. Di media sosial, buruh yang melawan justru kerap mendapat komentar sinis: “Syukuri saja masih bisa kerja!” atau “Kalau nggak mau digaji segitu, ya cari kerja lain!.” Komentar-komentar seperti ini tidak hanya datang dari buzzer pendukung kapital dan negara, melainkan juga dari sesama buruh. Fenomena ini memantik pertanyaan: mengapa buruh yang sama-sama tertindas justru saling menyalahkan, bukannya mendukung?
Kesadaran Kelas Tidaklah Otomatis
Banyak yang beranggapan bahwa pengalaman eksploitasi secara otomatis akan melahirkan kesadaran kelas. Kenyataannya, sering kali yang terjadi justru sebaliknya: ketika dihadapkan pada ancaman pemecatan, banyak buruh memilih tunduk, menjilat atasan, bahkan mengkhianati kawan-kawannya yang berjuang. Hal ini bukanlah soal moral individu, melainkan cerminan dari bagaimana kesadaran kelas tidak muncul dengan sendirinya.
E.P. Thompson menegaskan bahwa “Kelas bukanlah kategori tetap, melainkan terbentuk melalui proses sejarah dan perjuangan kolektif.” Ia menyatakan bahwa “Kelas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan suatu proses yang berlangsung (class is not a thing, it is a happening)” (Thompson, 1963: 9). Lebih jauh, Thompson memperingatkan: “Kita tidak bisa membayangkan dua kelas yang sepenuhnya terpisah, masing-masing dengan keberadaannya sendiri yang mandiri, lalu baru kemudian dikaitkan satu sama lain. Sebaliknya, kelas terbentuk melalui pengalaman hidup manusia dalam sejarah mereka sendiri, dan pada akhirnya, hanya itulah definisinya” (Thompson, 1963: 11).
Di Indonesia, banyak buruh tidak merasa dirinya buruh: driver ojek online disebut “mitra”, buruh UMKM merasa sebagai “tenaga bantu”, buruh perkantoran menolak disebut buruh karena asosiasi negatif, bahkan buruh NGO kerap tidak menyadari posisi mereka dalam relasi kerja. Tanpa pengalaman kolektif atau organisasi, mereka tidak merasa sebagai bagian dari satu kelas yang sama.
Hal ini tak lepas dari hegemoni ideologis, sebagaimana dijelaskan Antonio Gramsci. Menurutnya, kelas dominan tidak hanya memerintah dengan kekuatan ekonomi dan hukum, tetapi juga melalui “kepemimpinan intelektual dan moral” (Gramsci, 1971: 57). Nilai-nilai kapitalisme ditanamkan sebagai common sense, cara pandang sehari-hari yang tampak masuk akal, tapi sesungguhnya “fragmentaris, tidak utuh, dan kontradiktif” (Gramsci, 1971: 423). Maka tak heran jika aksi mogok atau pendirian serikat justru dianggap mengganggu, dan eksploitasi dipandang sebagai hal wajar.
Struktur Ekonomi yang Menghambat Kesadaran
Selain faktor ideologis, struktur ekonomi Indonesia turut menghambat tumbuhnya kesadaran kelas. Kita tengah mengalami deindustrialisasi prematur—kemunduran sektor industri sebelum mencapai kematangan. Modal lebih banyak mengalir ke sektor perdagangan, properti, dan digital yang cepat untung, alih-alih ke manufaktur yang padat karya. Muchtar Habibi menyebut ini sebagai ciri khas transisi agraria di negara kapitalisme pinggiran yang tidak mengikuti pola pusat (Habibi, 2021: 13).
Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun dari 21,11% (2014) menjadi 18,67% (2024) berdasarkan data BPS 10 tahun terakhir. Dampaknya, sektor informal dan semiformal mendominasi. Berdasarkan definisi ILO, buruh informal adalah mereka yang tidak tercatat dalam sistem hukum ketenagakerjaan: tanpa jaminan sosial, kontrak kerja, atau upah minimum. Status buruh disamarkan sebagai “mitra,” “usaha keluarga,” atau “pengusaha mikro.” Praktik outsourcing juga memperparah situasi ini.
Michael Kalecki (1943) menekankan bahwa pengangguran struktural bukanlah anomali, melainkan bagian dari fungsi normal kapitalisme. Meskipun secara statistik tercatat “bekerja”, buruh informal esensinya menjalankan fungsi yang sama dengan pengangguran struktural dalam sistem kapitalisme. Ia menulis, “Disiplin di pabrik-pabrik dan stabilitas politik lebih dihargai oleh para pemimpin bisnis daripada keuntungan” (Kalecki, 1943: 329). Dalam rezim full employment, pemecatan akan kehilangan perannya sebagai tindakan disipliner, posisi sosial bos akan tergerus, dan kepercayaan diri serta kesadaran kelas kaum pekerja akan menguat. Maka, buruh informal yang rentan sejatinya adalah bagian dari “populasi surplus relative,” sebagaimana dijelaskan Marx, kalau mereka berfungsi menekan upah dan memperlemah posisi tawar buruh-buruh yang berada di inti produksi (formal). Kondisi ini juga mempertentangkan buruh yang berada di sektor formal dengan mereka yang pengangguran struktural—biasanya dijadikan pengusaha alasan menjustifikasi praktik upah murah.
Menurut data BPS Februari 2025, 59,4% buruh Indonesia berada di sektor informal, dengan proporsi perempuan mencapai 55,81%. Bila menggunakan pendekatan ILO yang lebih komprehensif, proporsinya bisa melampaui 70%. Seperti ditulis Mike Davis, buruh informal adalah populasi yang “telah dikeluarkan dari sistem dunia” dan tidak memiliki prospek realistis untuk diintegrasikan kembali (Davis, 2006: 199). Sementara Portes dan Haller (2005) melihat ekonomi informal sebagai wajah paling telanjang dari ketidakstabilan kapitalisme global.
Organisasi Adalah Jalan
Jika kesadaran kelas tidak otomatis maka ia harus diproduksi: melalui pengalaman perjuangan, pendidikan politik, dan kerja organisasi. Di tengah fragmentasi dan dominasi ideologi kapitalis, pengorganisiran menjadi jalan penting untuk membangun kesadaran kelas.
Sayangnya, tingkat keanggotaan serikat buruh saat ini masih sangat rendah. Berdasarkan data Kemenaker, dari sekitar 50 juta buruh formal, hanya 3,2 juta yang menjadi anggota serikat, hanya sekitar 6,4% dari total buruh formal yang terlibat langsung dalam serikat buruh. Union density Indonesia hanya sekitar 12,99%. Selain itu, sebagian besar anggota serikat buruh adalah buruh senior. Buruh muda dan buruh di sektor informal cenderung tidak terorganisir.
Di sinilah peran organisator menjadi penting. Gramsci menyebut peran mereka sebagai “pembujuk tetap” (permanent persuader), bukan sekadar orator, melainkan partisipan aktif dalam membentuk realitas politik melalui praksis (Gramsci, 1971: 10). Mereka menjadi penghubung antara pengalaman konkret dengan kesadaran struktural.
Lebih jauh, perlu juga upaya serius untuk memetakan dan mengorganisir sektor-sektor baru: buruh kognisi, guru honorer, buruh kontrak yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, hingga ASN non-struktural. Seperti ditekankan Thompson, kelas adalah proses historis. Tidak ada kesadaran yang tumbuh tanpa interaksi dan pengorganisiran.
Kerja pengorganisiran bukan sekadar aktivitas reaktif terhadap penindasan, melainkan upaya aktif menciptakan kehidupan kolektif yang berdaya. Seperti dikatakan Michael Hardt dan Antonio Negri, “proyek politik dari multitude bukan hanya untuk melawan dominasi, tetapi membangun bentuk kehidupan baru” (Hardt & Negri, 2004: 358).
Siapapun yang menyadari posisinya dalam relasi kelas kapitalisme harus ambil bagian dalam pengorganisiran harian: di tempat kerja, lingkungan tinggal, ruang digital, atau ruang publik. Dari pengorganisiran harian itu lalu ditransformasikan menjadi organisasi-organisasi perlawanan. Tentu organisasi yang memiliki agenda politik jangka panjang. Karena kesadaran tidak diasumsikan melainkan harus ditransmisikan.
Siapa pun yang menyadari posisinya dalam relasi kelas kapitalisme, harus mengambil bagian dalam kerja-kerja pengorganisiran harian: baik di tempat kerja, lingkungan tinggal, ruang digital, maupun ruang publik lainnya. Dari proses inilah kesadaran kolektif dibentuk, dirawat, dan diperluas.
Pengorganisiran harian tidak berhenti pada aksi-aksi sporadis atau solidaritas. Ia perlu ditransformasikan menjadi organisasi-organisasi perlawanan yang terstruktur, organisasi yang tidak hanya mampu merespons ketidakadilan, tetapi juga memiliki agenda politik jangka panjang untuk mengubah struktur yang menindas. Sebab, kesadaran tidak diasumsikan melainkan harus ditransmisikan: melalui relasi yang dibangun, pengalaman yang dibagikan, dan arah politik yang diperjuangkan bersama.
Sebagai penutup, tulisan ini adalah seruan untuk kembali pada kerja-kerja mendasar dalam perjuangan kelas: membangun dan memperkuat organisasi. Di tengah situasi yang jelas tidak menguntungkan gerakan rakyat secara multidimensi dan dalam banyak sisi, organisasi akan selalu menjadi syarat dalam perjuangan kelas—bukan pelengkap, apalagi pilihan.
Benny Agung adalah anggota aktif Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR).
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik (BPS). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025. Jakarta: BPS, 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS). Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2014–2024. Jakarta: BPS, 2024.
Davis, Mike. Planet of Slums. London: Verso, 2006.
Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers, 1971.
Habibi, Muchtar. “Laju Kapital dan Dinamika Kelas Ekonomi Informal Perkotaan.” Jurnal Pisma 40, no. 3 (2021): 13–29.
Hardt, Michael, and Antonio Negri. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York: Penguin Press, 2004.
Kalecki, Michał. “Political Aspects of Full Employment.” The Political Quarterly 14, no. 4 (1943): 322–331.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Data Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nasional Tahun 2023. Jakarta: Kemenaker, 2024.
Portes, Alejandro, and William Haller. “The Informal Economy.” In The Handbook of Economic Sociology, 2nd ed., edited by Neil J. Smelser and Richard Swedberg, 403–425. Princeton: Princeton University Press, 2005.
Thompson, E.P. The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz, 1963.